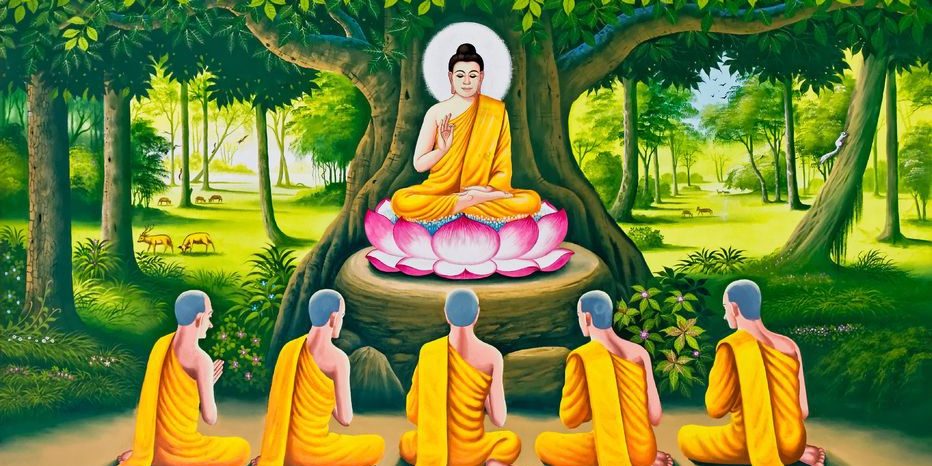Riwayat Hidup Buddha Gotama
PENDAHULUAN
Keberadaan
agama Buddha tidaklah terlepas dari riwayat hidup Siddhattha Gotama (Sanskerta:
Siddhārtha Gautama) yang kemudian dikenal dengan sebutan Sang Buddha (Ia Yang
Telah Sadar), sebagai penemu dan pengajar ajaran yang juga disebut dengan
Buddha Dhamma (Ajaran Buddha).
Riwayat
hidup Buddha Gotama yang dipaparkan di bawah ini hanyalah merupakan garis besar
dari kehidupan Beliau selama 80 tahun yang dimulai dari kelahiran-Nya sebagai
Pangeran Siddhattha hingga kemangkatan mutlak-Nya (Pali: parinibbāna;
Sanskerta: parinirvāna), serta beberapa peristiwa penting dalam
kronologi pembabaran Dhamma oleh-Nya. Riwayat hidup Buddha Gotama ini juga
merupakan kompilasi dari beberapa sumber termasuk Tipitaka Pali, seperti kisah
Pencarian Mulia yang terdapat di dalam Sutta Ariyapariyesana (Majjhima Nikaya
26, Tipitaka Pali).
Kelahiran dan Kehidupan Istana Pangeran Siddhattha
KELAHIRAN BODHISATTA
Ratu Mahāmāyā, ratu utama dari Raja Suddhodana – raja dari kerajaan suku
Sākya (Sokyā, Sakka, Sākiyā), yang sedang mengandung dengan usia kehamilannya
sudah mencapai sepuluh bulan, melakukan perjalanan dari Kapilavatthu
(Sanskerta: Kapilavastu), ibu kota Kerajaan Sākya, menuju Devadaha, kota tempat
tinggal ayahnya, Raja Añjana – raja dari kerajaan suku Koliyā, untuk melakukan
persalinan di sana.
Saat itu, hari bulan purnama, di bulan Vesākha (baca
: Wesakha)
[1],
tahun 623 Sebelum Era Umum (secara konsensus sejarawan awal abad ke-20
menetapkan tahun 563 SEU) atau tahun 80 Sebelum Era Buddhis (SEB).
Dalam perjalanan tersebut, Ratu Mahāmāyā yang juga dikenal dengan nama
Māyādevī, bersama rombongan kerajaan melewati Taman Lumbini (sekarang berada di
wilayah Nepal), sebuah hutan pohon shala
sāla (Pali: Latin:
Shorea
robusta) – tempat wisata yang terletak di antara Kapilavatthu dan
Devadaha, di Nepal Selatan. Saat itu semua pohon
sāla di hutan
tersebut sedang berbunga dari bawah pohon hingga pucuknya. Melihat keindahan
taman tersebut Ratu Mahāmāyā memutuskan untuk beristirahat dan berjalan-jalan
di dalamnya.
Ketika Sang Ratu berjalan-jalan melihat Taman Lumbini, ia menghampiri
sebatang dahan pohon
sāla yang merunduk dengan bunga yang sedang
merekah. Pada saat berdiri dan memegang dahan pohon
sāla ia merasakan
tanda-tanda kelahiran dan para pelayannya segera membentuk lingkaran dan
menutupi area tersebut dengan tirai. Demikianlah, dengan posisi berdiri dan
berpegangan pada dahan pohon
sāla tersebut Ratu Mahāmāyā melahirkan
seorang pangeran, Sang Bodhisatta (Calon Buddha; baca:
Bud-dha).
Pada hari yang sama, lahir pula: Putri Yasodharā yang kelak menjadi istri
Sang Pangeran, Pangeran Ānanda yang kelak menjadi pembantu tetap Sang Buddha,
Channa (Sanskerta: Chandaka) yang kelak menjadi kusir Sang Pangeran, Kanthaka
yang kelak menjadi kuda Sang Pangeran, Menteri Kaludayi yang kelak mengundang
Sang Buddha untuk berkunjung kembali ke Kapilavatthu, Pohon
Pippala
atau disebut Pohon
Bodhi (Latin:
Ficus Religiosa), dan
munculnya empat jambangan harta (Pali:
Nidhikumbhi).
Setelah melahirkan, Ratu Mahāmāyā dengan membawa Sang Pangeran kembali ke
Kota Kapilavatthu diiringi oleh para penduduk dari kedua kota, Kapilavatthu dan
Devadaha.
TAWA DAN TANGIS PETAPA ASITA
KĀLADEVALA
Kelahiran Sang Pangeran membawa kebahagiaan bagi
seluruh kerajaan termasuk seorang petapa bernama Asita yang dikenal juga
sebagai Kāladevala yang merupakan guru pribadi raja. Petapa Asita segera
berkunjung ke istana Raja Suddhodana di ibu kota Kapilavatthu untuk melihat
pangeran kecil tersebut.
Ketika Petapa Asita telah tiba dan melihat adanya
32 tanda dari seorang Manusia Agung (Mahāpurisa) pada bayi tersebut,
ia memberikan penghormatan kepada-Nya. Melihat sang guru kerajaan yang
seharusnya mendapatkan penghormatan dari seluruh rakyat kerajaan termasuk raja,
tetapi justru memberi penghormatan kepada Sang Pangeran, Raja pun turut memberi
penghormatan kepada putranya.
Setelah itu Petapa Asita tertawa gembira karena
bahagia sebab Pangeran kelak akan menjadi seorang Buddha. Tetapi kemudian ia
menangis karena bersedih sebab usianya yang sudah tua membuat ia tidak bisa
menunggu bayi tersebut dewasa hingga menjadi seorang Buddha dan membabarkan
ajaran-Nya.
UPACARA PEMBERIAN NAMA
Lima hari setelah Sang Pangeran lahir, Raja
Suddhodana mengadakan upacara pembasuhan kepala dan pemberian nama, sesuai
dengan tradisi India kuno, dengan mengundang para brahmana (brahmin) terpelajar
dan terkemuka. Di antara 108 brahmana yang diundang terdapat delapan brahmana yang
terkemuka.
Setelah melihat tanda-tanda kebesaran pada tubuh
Pangeran, tujuh di antara mereka yaitu Rāma, Dhaja, Lakkhanā, Jotimanta
(Jotimantī), Subhoja (Bhoja), Suyāma, dan Sudatta memprediksikan dua
kemungkinan yaitu bahwa Pangeran akan menjadi seorang Raja Dunia atau akan
menjadi seorang Buddha jika Ia meninggalkan kehidupan keduniawian dan menjadi
petapa.
Tetapi Kondañña (Yañña), salah satu dari
kedelapan brahmana itu, dan yang paling muda, menyatakan dengan memastikan
bahwa hanya ada satu kemungkinan yaitu Pangeran akan menjadi seorang Buddha.
Pernyataan Kondañña ini akhirnya diterima oleh semua brahmana.
Para brahmana terpelajar tersebut juga
memberitahu raja bahwa sang pangeran akan meninggalkan kehidupan duniawi dan
menjadi petapa setelah ia melihat empat penampakan, yaitu orang tua, orang
sakit, orang mati, dan petapa.
Setelah itu, para brahmana memberi-Nya nama Siddhattha
(Sanskerta: Siddhartha) yang berarti “yang berhasil mencapai
tujuannya”, dan dengan nama keluarga Gotama (Sanskerta: Gautama).
WAFATNYA RATU MAHĀMĀYĀ
Pada hari ketujuh setelah melahirkan Pangeran
Siddhattha , Ratu Mahāmāyā wafat, dan adiknya Mahāpajāpatī Gotamī yang juga
istri Raja Suddhodana menggantikan posisi Ratu Mahāmāyā sebagai ratu sekaligus
ibu bagi pangeran kecil. Dari hubungan Raja Suddhodana dengan Mahāpajāpatī
Gotamī melahirkan seorang pangeran bernama Nanda dan seorang putri bernama
Sundari Nanda (Rupananda).
Mahāpajāpatī Gotamī merawat Pangeran Siddhattha
seperti merawat putranya sendiri, Pangeran Nanda. Pangeran Nanda sendiri lahir
beberapa hari setelah Pangeran Siddhattha lahir.
Setelah Ratu Mahāmāyā wafat, ia dilahirkan
menjadi seorang putra dewa dengan nama Māyādevaputta (Santusita) di surga
Tusita .
PERAYAAN BAJAK TANAH
Tiba waktunya bagi Kota Kapilavatthu mengadakan perayaan musim tahunan yang
disebut dengan Perayaan Bajak Tanah. Raja Suddhodana mengajak pergi Pangeran
Siddhattha yang telah berusia beberapa tahun ke perayaan tersebut. Dan Raja pun
turut membajak bersama-sama dengan para petani.
Pada saat perayaan yang berlangsung meriah, para pengasuh yang ditugaskan
untuk menjaga Pangeran merasa sangat tertarik dengan jalannya perayaan
tersebut. Mereka ingin menyaksikannya dan akhirnya meninggalkan Pangeran di
bawah bayangan pohon jambul (Latin:
Eugenia Jambolana). Dan pada saat
itu suasana di sekitar pohon jambul tesebut menjadi tenang dan sepi sehingga
sesuai untuk meditasi. Pangeran kecil pun duduk bersila dan melakukan meditasi
dengan konsentrasi memperhatikan masuk-keluarnya nafas (Pali:
ānāpāna
bhāvanā).
Ketika para pengasuh kembali, mereka merasa heran sekali melihat Pangeran
sedang bermeditasi, dan dengan cepat mereka melaporkannya kepada Raja. Raja
dengan diiringi oleh para petani berbondong-bondong datang untuk menyaksikan
peristiwa ganjil tersebut. Dan mereka pun menemukan Pangeran sedang duduk
bermeditasi dan tidak menghiraukan kehadiran orang-orang yang datang
memperhatikannya. Hal itu terjadi karena pada saat itu Pangeran berada dalam
keadaan Jhāna, yaitu keadaan dimana kesadaran sedang berkonsentrasi secara
penuh. Melihat hal itu Raja memberi hormat untuk kedua kalinya kepada putranya
tersebut.
MASA KECIL DAN PENDIDIKAN
Semasa kecil, Pangeran Siddhattha hidup dalam kemewahan dan dirawat oleh
para pengasuh sebaik mungkin. Seluruh pengiring-Nya muda-muda, berpenampilan
menarik, cantik, tampan, dan berbadan lengkap. Jika ada yang sakit, maka orang
itu tidak diijinkan tinggal di istana dan akan digantikan oleh orang lain. Sang
pangeran di kenakan beraneka ragam perhiasan, kalung bunga, minyak wangi dan
pernak-pernik yang semerbak. Tutup kepala, jubah, dan mantel-Nya seluruhnya
didatangkan dari Negara Kasi. Untuk menyenangkan hati Pangeran Siddhattha, Raja
Suddhodana membuatkannya tiga kolam teratai di istananya, yaitu Kolam Uppala
dengan teratai birunya, Kolam Paduma dengan teratai merahnya, dan Kolam
Puṇḍarīka dengan teratai putihnya.
Ketika Pangeran Siddhattha berusia tujuh tahun, Ia mulai menjalani
pendidikan-Nya. Kedelapan brahmana terkemuka, yang dahulu diundang raja untuk
meramalkan masa depan pangeran, menjadi guru-guru-Nya yang pertama. Setelah
guru-guru tersebut mengajarkan semua pengetahuannya kepada pangeran, Raja
Suddhodana mengutus-Nya untuk berguru kepada guru lain bernama Sabbamitta.
Brahmana Sabbamitta yang tinggal di daerah Udicca, berasal dari keturunan
terkemuka dan ahli dalam bahasa dan tata bahasa, serta fasih dalam Kitab
Veda
dan keenam Vedāṅga yang terdiri dari ilmu fonetik (
śikṣā), upacara
keagamaan (
kalpa), tata bahasa (
vyākaraṇa), ilmu tafsir kata (
nirukta),
ilmu metrum persajakan (
chandas), dan ilmu perbintangan (
jyotiṣa).
Sang Pangeran mampu mempelajari semua mata pelajaran yang Ia terima dari
guru-Nya, termasuk ilmu kemiliteran, bela diri seperti tinju, gulat, anggar,
dan berkuda. Ia adalah siswa yang terpandai dan terbaik dalam segala hal bahkan
menjadi lebih pandai dari guru-guru-Nya. Ia adalah siswa yang paling bijak dan
satu-satunya yang banyak bertanya kepada para guru dan kakak seperguruan-Nya.
Ia juga anak yang terkuat, tertinggi, dan tertampan di kelas. Meskipun Pangeran
Siddhattha adalah siswa yang terpandai, Ia tidak pernah lalai dalam bersikap
santun dan memberikan penghormatan yang sepantasnya terhadap guru-guru-Nya.
Sang Pangeran tidak pernah menyia-nyiakan waktu. Ketika Ia sedang tidak ada
pekerjaan, Ia akan menyendiri di tempat yang tenang dan berlatih meditasi. Dan
meskipun Ia juga terlatih dalam seni memanah dan dalam pemakaian senjata,
tetapi Ia tidak suka melukai makhluk lain. Ia juga menghindari pembunuhan atau
penganiayaan hewan jinak sekalipun, seperti kelinci dan kijang.
WELAS ASIH SANG PANGERAN
Sifat welas asih Pangeran Siddhattha tercermin dalam kehidupan
sehari-hari-Nya seperti menghentikan dan menasihati seorang pelayan-Nya yang
sedang memukuli seekor ular dengan tongkat.
Pada kesempatan lainnya, ketika pangeran sedang beristirahat di bawah pohon
dalam waktu bermainnya bersama sahabat-sahabat-Nya dan juga sepupunya, Pangeran
Devadatta, Ia tiba-tiba melihat seekor angsa jatuh dari angkasa. Ia tahu bahwa
Pangeran Devadatta telah memanah angsa tersebut. Dengan segera Pangeran
Siddhattha menolong angsa tersebut. Pangeran Devadatta juga mengejar angsa itu,
namun Pangeran Siddhattha berhasil terlebih dulu mengambil angsa itu dan dengan
lembut Ia menarik anak panah yang menusuk angsa tersebut serta memberikan obat
pada lukanya.
Pangeran Devadatta yang baru saja tiba menuntut agar unggas itu diserahkan
kepadanya, namun Pangeran Siddhattha menolaknya. Akhirnya terjadilah
perselisihan dan saling debat. Pangeran Devadatta bersikukuh bahwa angsa itu
adalah miliknya karena ia yang memanahnya. Sedangkan Pangeran Siddhattha
mengatakan bahwa Ia yang berhak atas angsa itu karena Ia telah menyelamatkan
hidupnya, sedangkan si pemanah tidak berhak akan angsa yang masih hidup
tersebut. Akhirnya Pangeran Siddhattha mengusulkan agar permasalahan ini dibawa
ke mahkamah para bijak untuk memperoleh jawaban atas siapa yang berhak atas
angsa tersebut.
Setelah diajukan ke mahkamah para bijak, akhirnya salah satu dari para bijak
tersebut berseru, “Semua makhluk patut menjadi milik mereka yang menyelamatkan
atau menjaga hidup. Kehidupan tak pantas dimiliki oleh orang yang berusaha
menghancurkannya. Angsa yang terluka ini masih hidup dan diselamatkan oleh
Pangeran Siddhattha. Karenanya, angsa ini mesti dimiliki oleh penyelamatnya,
yaitu Pangeran Siddhattha!”
[2]
PERNIKAHAN
Kekhawatiran Raja Suddhodana terhadap apa yang dikatakan oleh Petapa Asita
dan terhadap ramalan Brahmana Kondanna mengenai Pangeran Siddhattha, berusaha
membuat putranya tersebut merasa nyaman dan bahagia. Segala hal-hal yang buruk
dijauhkan dari diri putranya termasuk hal-hal mengenai sakit, tua, mati, dan
petapa. Selain itu raja juga membangun tiga buah istana untuk putranya pada
setiap musimnya, yaitu Istana Ramma untuk musim dingin, Istana Suramma untuk
musim panas, Istana Subha untuk musim hujan.
Pada saat itu tahun 607 SEU (547 SEU) atau tahun 64 SEB, Pangeran Siddhattha
berusia enam belas tahun, Ia tumbuh sebagai seorang pria muda yang tampan dan
perkasa. Dan perangai-Nya yang suka merenung serta welas asih-Nya yang tanpa
batas semakin jelas. Hal ini sangat membuat raja khawatir dan memanggil para
penasihat istana untuk menemukan jawaban agar sang pangeran tetap mewarisi
singgahsananya daripada menjadi seorang Buddha. Dan akhirnya diputuskan untuk
mencari gadis tercantik dan menikahkannya dengan pangeran. Kemudian Raja
Suddhodana memerintahkan untuk mengirim berita kepada delapan puluh ribu
kerabat Sakya-nya dan meminta mereka untuk memperkenankan putri-putri mereka
untuk datang ke istana agar pangeran dapat memilih salah satunya sebagai istri.
Berita pemilihan istri tersebut ditanggapi negatif oleh para pangeran Sakya
yang beranggapan bahwa Pangeran Siddhattha tidak memiliki kemampuan sebagai
seorang ksatria dan seorang pengecut yang tidak memiliki kemampuan seni bela
diri dan seni berburu untuk melindungi dan mencari nafkah keluarganya kelak.
Menanggapi hal ini Raja Suddhodana merasa sangat tersinggung dan menemui
putranya serta menceritakan permasalahannya. Pangeran lalu berkata bahwa Ia
akan mempertunjukkan kemahiran-Nya dalam pertandingan apapun, termasuk panahan
dihadapan semua pangeran dan putri Sakya.
Dalam pertandingan, Pangeran Siddhattha akhirnya dapat mengalahkan semua
lawannya dalam segala pertandingan. Dengan ini para pangeran dan putri Sakya
akhirnya bergembira mengetahui hasilnya, sekaligus merasa tegang siapa yang
akan dipilih pangeran untuk menjadi istri-Nya. Akhirnya pilihan Pangeran
Siddhattha jatuh pada Putri Yasodharā, sepupu-Nya yang cantik, putri dari Raja
Suppabuddha dari kerajaan Koliya dan Ratu Amita, saudara perempuan Raja
Suddhodana.
MELIHAT PENAMPAKAN PERTAMA:
ORANG TUA
Pada tahun 535 S.E.U (595 S.E.U) atau tahun 52 S.E.B, memasuki usia-Nya yang
kedua puluh delapan tahun, Pangeran Siddhattha tidak lagi merasa senang akan
segala kemewahan dan hiburan di sekeliling-Nya. Ia menjadi jenuh dan ingin
melihat dunia luar. Ia merasa penasaran untuk mengetahui kehidupan rakyat dan
hal-hal di luar tembok istana. Setelah mendapatkan ijin dari ayah-Nya, Ia
akhirnya keluar istana ditemani oleh Channa, kusir-Nya. Orang-orang ramai
berdiri di kedua sisi jalan dan menyambut-Nya dengan hangat. Semuanya terasa
semarak dan indah karena telah diperintahkan oleh raja untuk menyingkirkan
hal-hal yang buruk dari tempat yang akan dilalui oleh pangeran.
Namun tidak lama kemudian, tiba-tiba seorang lelaki tua melintas di
sepanjang jalan tanpa sempat dicegah. Sang pangeran sangat terkejut dengan apa
yang tampak oleh-Nya. Ia sangat terkesima dan tidak mengetahui apa yang tengah
dilihat-Nya, dan Ia bertanya kepada kusir-Nya, Channa, apa yang telah
dilihatNya itu. Channa menjelaskan bahwa itu disebut dengan orang tua, orang
yang tidak akan hidup lama lagi, dan semua orang tanpa kecuali akan mengalami
hal itu tanpa bisa dicegah. Pangeran Siddhattha segera memerintahkan Channa
untuk kembali ke istana karena Ia menjadi tidak bergairah lagi untuk berkeliling
kota . Ia sangat sedih dan terguncang pikirannya oleh apa yang dilihat-Nya. Ia
berpikir bahwa diri-Nya sendiri, istri-Nya, ayah-Nya, ibu angkat-Nya, dan semua
orang yang dicintai-Nya akan menjadi tua. Ia ingin tahu apakah ada yang bisa
mencegah dan mengatasi usia lanjut ini.
Mendengar apa yang terjadi pada putranya, raja menjadi khawatir dan sedih.
Ia memerintahkan orang-orangnya untuk menambah penjaga di sekitar tempat itu
dan untuk menambah pelayan wanita dan gadis penari untuk menghibur sang pangeran
sepanjang waktu.
MELIHAT PENAMPAKAN KEDUA:
ORANG SAKIT
Empat bulan kemudian, Pangeran Siddhattha sekali lagi memohon kepada
ayah-Nya untuk keluar istana. Namun Ia tidak ingin kunjungannya diumumkan atau
dipersiapkan karena Ia ingin melihat segala hal, termasuk kehidupan sehari-hari
rakyat-Nya. Raja Suddhodana mengijinkan-Nya dengan berat hati karena masih
merasa gundah terhadap apa yang terjadi selama kunjungan pertama pangeran.
Namun, karena cinta dan kasihnya kepada putranya, ia mengijinkan pangeran melakukan
kunjungan untuk kedua kalinya.
Hari kunjungan pun tiba. Ditemani oleh Channa, pangeran menyamar sebagai
pemuda dari keluarga bangsawan. Ia berjalan kaki melihat-lihat kehidupan
rakyatnya secara apa adanya. Tidak ada penyambutan, panji-panji ataupun
penebaran bunga. Semua rakyat sibuk dengan pekerjaannya sendiri untuk mencari
penghidupan. Namun ketika Ia tengah berjalan, tiba-tiba terdengar suara seorang
lelaki yang menangis tersedu-sedu karena kesakitan. Pangeran mencari sumber
suara itu dan menemukan seorang lelaki yang sedang berbaring di tanah sambil
memegang perutnya dan berguling-guling kesakitan, wajahnya penuh dengan
noda-noda hitam. Ia berusaha memohon pertolongan, tetapi tidak ada yang
memperdulikannya, sebaliknya orang-orang menghindarinya. Melihat hal ini
pangeran merasa terguncang untuk kedua kalinya. Dengan penuh welas asih
pangeran segera mendekati orang itu, tanpa bisa dicegah oleh Channa. Pangeran
yang memangku kepala orang itu berusaha menenangkan dan bertanya apa yang
terjadi, namun tanpa sepatah katapun keluar dari mulut orang itu. Akhirnya
pangeran bertanya kepada Channa apa yang telah terjadi. Dan Channa pun menjawab
bahwa orang itu sedang sakit dan semua orang tanpa kecuali akan mengalami hal
itu. Mendengar hal itu, Pangeran Siddhattha sangat sedih mengetahui semua
fenomena duniawi ini. Lalu, bersama dengan Channa , Ia kembali ke istana karena
tidak lagi bersemangat meneruskan kunjungan-Nya.
Setelah mengetahui apa yang telah terjadi selama kunjungan pangeran dari
Channa, Raja Suddhodana kembali menjadi sedih dan memerintahkan kembali untuk
memperbanyak penjaga dan jumlah pelayan dan gadis penari.
MELIHAT PENAMPAKAN KETIGA:
ORANG MATI
Dengan menikmati kesenangan dan kemewahan hidup istana setelah kunjungan
kedua, perasaan desakan spiritual yang dirasakan-Nya menjadi sedikit berkurang.
Tetapi sekitar empat bulan kemudian, Pangeran Siddhattha kembali memohon untuk
keluar dari istana untuk melihat kotanya kembali lebih dekat. Dengan berat hati
raja pun mengijinkannya.
Seperti halnya kunjungan kedua, pangeran menyamar sebagai pemuda dari
keluarga bangsawan dan juga ditemani oleh Channa yang juga berpakaian berbeda
untuk menyembunyikan identitasnya. Di tengah perjalanan, tampak oleh-Nya
iring-iringan orang tiba di jalan. Orang-orang tersebut mengusung sebuah tandu
yang di dalamnya terdapat seorang lelaki kurus kering terbujur kaku dan
ditutupi sehelai kain serta diiringi oleh orang-orang yang menangis. Merasa
heran, pangeran bertanya kepada Channa mengenai orang yang terbaring di dalam tandu
tersebut. Channa pun menjelaskan bahwa orang itu telah mati, semua orang pasti
akan mati tanpa terkecuali.
Pemandangan yang tidak menyenangkan ini terjadi tanpa seorang pun mampu
untuk mencegahnya. Pemandangan ini sungguh menyentuh hati pangeran selama
kunjungan-Nya yang ketiga itu. Pangeran Siddhattha tidak lagi bergairah
meneruskan kunjungan-Nya. Diiringi oleh Channa, dengan diam Ia kembali ke
istana dan memasuki kamar-Nya sendirian. Ia duduk dan merenungkan dalam-dalam
apa yang baru saja dilihat-Nya. Dalam hati Ia berkata: “Alangkah mengerikannya!
Setiap orang kelak akan mati dan tak seorang pun mampu mencegahnya. Harus ada
cara untuk mengatasi hal ini. Akan Kucari cara agar ayah, ibu, Yasodharā, dan
semua kerabat-Ku yang tercinta tak akan pernah menjadi tua, sakit, dan mati.”
Channa kembali mengabarkan kepada raja bahwa pangeran buru-buru pulang
setelah melihat mayat. Mendengar hal ini raja kembali menjadi sedih. Walaupun
ia telah berusaha sekuatnya untuk mencegah putranya agar tidak melihat hal-hal
yang tidak menyenangkan, penampakan yang tak terduga terjadi untuk ketiga
kalinya sebagaimana yang diramalkan oleh kedelapan brahmana.
MELIHAT PENAMPAKAN KEEMPAT:
PETAPA
Pangeran Siddhattha lebih sering menyendiri dan merenungkan ketiga
pemandangan yang telah dijumpai-Nya selama berkunjung ke kota . Namun, karena
merasa belum puas dengan apa yang telah Ia ketahui sekarang, Ia menjadi sangat
penasaran ingin mengetahui lebih lanjut sisi lain kehidupan, yang mungkin belum
pernah dilihat-Nya. Sementara itu Raja Suddhodana senantiasa berusaha
menyenangkan dan mengalihkan pikiran pangeran dari ketiga peristiwa tersebut.
Untuk beberapa bulan, usaha raja nampak berhasil. Tetapi sifat ingin tahu dan
suka merenung dari pangeran tidak mudah tergoyahkan oleh sumua hiburan yang ada
dalam istana. Dan Empat bulan kemudian, Ia kembali memohon kepada ayah-Nya
untuk diperkenankan keluar istana lagi untuk berwisata ke taman kerajaan dan
melihat sisi lain dari kehidupan. Raja tidak memiliki alasan apapun untuk
menolak permohonan santun putranya itu.
Ditemani oleh Channa, pangeran menuju taman istana melalui Kota
Kapilavatthu. Setelah sampai di taman dan ketika pangeran tengah duduk dan
menikmati taman tersebut, tampak oleh-Nya seorang lelaki dengan kepala yang
dicukur bersih datang dari kejauhan. Dan pangeran pun bertanya kepada Channa
siapakah orang itu. Channa menjawab bahwa oran itu adalah seorang petapa,
seseorang yang meninggalkan kehidupan berkeluarga. Pangeran merasa terdorong
untuk mengetahui lebih lanjut siapa petapa itu. Bagi-Nya, petapa itu tampak
mengagumkan dan mulia, tidak seperti orang lainnya. Pangeran yang merasa tidak
puas dengan jawaban Channa, mendekati petapa itu dan bertanya mengenai diri
petapa tersebut. Petapa itu pun menjelaskan prihal dirinya.
Setelah pangeran mendengar penjelasan prihal diri petapa tersebut, bagaimana
ia hidup, dan bagaimana ia menemukan jalan kebahagiaan atas dirinya, pangeran
merasa bahagia dan menyadari bahwa adanya jalan sejati untuk mengatasi
penderitaan hidup.
LAHIRNYA RĀHULA
Ketika Pangeran Siddhattha masih di dalam taman dan benak-Nya dipenuhi
dengan gagasan untuk hidup bersih dan murni sebagai petapa, seorang kurir
kerajaan yang diutus oleh Raja Suddhodana mengabarkan bahwa Putri Yasodharā
telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang tampan. Mendengar kabar ini,
pangeran justru bersedih hati dan berujar: “
Rāhu jāto, bandhanam jātam”[3]
(“Sebuah ikatan telah lahir, sebuah belenggu telah muncul!”
). Kelahiran
putra-Nya tersebut dianggap merupakan halangan karena kecintaan-Nya kepada
keluarga dan anak-Nya yang baru lahir tersebut akan menimbulkan kemelekatan
yang akan merintangi niat-Nya untuk menjadi petapa, seperti yang Ia inginkan.
Mengetahui apa yang diutarakan pangeran saat menerima berita itu, Raja
Suddhodana kemudian memberi nama cucunya tersebut dengan nama “Rāhula”, yang
berarti “ikatan”.
Pelepasan Keduniawian Pangeran Siddhattha
Keempat penampakan agung terjadi satu per satu.
Apa yang telah diramalkan kedelapan brahmin cendekia menjadi kenyataan.
Di istana kediamannya, Raja Suddhodana tengah
mengadakan pesta besar-besaran. Makan malam besar disajikan dan beberapa
pelayan wanita cantik disiapkan untuk melayani Sang Pangeran untuk merayakan
kelahiran cucu Raja Suddhodana – Rāhula, yang lahir pagi itu.
Sang Pangeran, yang baru saja kembali dan
perjalanan-Nya yang bahagia, tampak lebih bahagia dibandingkan perjalanan
sebelumnya. Ia bahagia karena mengetahui bahwa cara untuk mencapai kebahagiaan
sejati adalah dengan melepaskan keduniawian dan menjadi petapa.
Bagaimanapun juga, Pangeran tidak ingin
mengecewakan ayah-Nya. Dengan tenang Ia menyantap makan malam tanpa merasa
tertarik dengan nyanyian dan tarian yang disuguhkan untuk-Nya. Benak-Nya
dipenuhi dengan keinginan untuk membebaskan semua makhluk dan usia tua,
penyakit, dan kematian, yang semuanya menyengsarakan, menekan, dan menyedihkan.
MENINGGALKAN ISTANA
Sekitar pertengahan malam, Pangeran Siddhattha
terbangun. Ia duduk bersilang kaki di bangku, lalu melihat ke sekeliling. Semua
gadis penari, penyanyi, dan pemusik tengah tidur malang-melintang di lantai
kamar itu. Pangeran merasa sangat jijik dengan pemandangan ini; dalam
pandangan-Nya, tubuh mereka semua tergeletak seperti tidak ada bedanya dengan
mayat di pekuburan.
Pangeran Siddhattha, semakin tidak melekat pada
kelima objek kenikmatan indrawi, yang semuanya bukan merupakan kebahagiaan
sejati, namun sebaliknya menimbulkan kesulitan dan derita yang lebih mendalam.
Tekad Pangeran Siddhattha semakin kuat. Inilah
waktunya untuk meninggalkan kehidupan rumah tangga. Ia kemudian meninggalkan
kamar itu perlahan-lahan dan Ia melihat Channa, yang tengah tidur dengan
membaringkan kepalanya di ambang pintu. Pangeran Siddhattha membangunkannya dan
meminta untuk mempersiapkan Kanthaka, kuda-Nya.
Channa menaati permintaan-Nya. Segera Ia membawa
tali kekang dan beberapa perlengkapan lainnya yang dibutuhkan, lalu menuju ke
kandang kuda kerajaan. Sementara itu, Pangeran Siddhattha merasa bahwa Ia perlu
menengok istri dan putra-Nya yang baru lahir sebelum meninggalkan keduniawian.
Dengan hati penuh cinta, Pangeran berdiri diam di
pintu sambil memandangi mereka. Ia tak berani memindahkan tangan Putri
Yasodharā dan menimang putra-Nya meskipun Ia sangat ingin melakukannya, karena
Ia tidak menginginkan Putri Yasodharā terjaga dan tidak mengijinkan-Nya pergi.
Setelah bertekad bulat, Ia keluar dan kamar tersebut dan menutup pintu
perlahan-lahan.
Channa dan Kanthaka sudah siap dan menunggu
Pangeran di depan istana kediaman-Nya. Pada malam purnama, di bulan Āsāḷha,
tahun 594 Sebelum Era Umum (tahun 534 SEU secara konsensus sejarawan) atau
tahun 51 Sebelum Era Buddhis, di usia ke 29 tahun, pada waktu jaga pertengahan
malam, diam-diam Pangeran Siddhattha meninggalkan istana dengan menunggangi
Kanthaka. Channa, yang terlahir pada hari yang sama dengan Sang Pangeran, ikut
meninggalkan istana dengan berpegangan pada ekor kuda tersebut. Mereka berhasil
menerobos ketatnya penjagaan dan meninggalkan Kota Kapilavatthu.
MEMOTONG RAMBUT
Pangeran Siddhattha menunggangi si kuda putih
Kanthaka yang melesat dengan kencang. Namun setelah sesaat perjalanan, sebuah
gagasan muncul pada-Nya untuk memandangi Kapilavatthu. Ia menghentikan kuda
istana itu dan membalikkan badan untuk memandangi kota tersebut untuk terakhir
kalinya. Tepat di tempat kuda istana Kanthaka berhenti itu akhirnya dibangun
sebuah kuil suci (cetiya) yang disebut Cetiya Kanthakanivatta. Setelah itu, Ia
melanjutkan perjalanan-Nya melewati tiga kerajaan, yaitu: Sākya, Koliyā, dan
Mallā. Sepanjang malam, Ia menempuh jarak sejauh tiga puluh yojana (satu yojana
setara dengan dua belas mil) Akhirnya Ia tiba di tepi Sungai Anomā dan
menyeberanginya.
Saat itu hari telah pagi. Pangeran Siddhattha
turun dan punggung Kanthaka. Ia meminta Channa untuk pulang kembali ke
Kapilavatthu bersama dengan Kanthaka serta tanda kebesaran kerajaan, dan
meninggalkan-Nya seorang diri. Channa memohon untuk mengikuti-Nya menjadi
petapa, tapi Pangeran Siddhattha melarangnya. Setelah Pangeran Siddhattha
menyerahkan Kuda Kanthaka beserta tanda kebesaran kerajaan-Nya, Ia menghunus
pedang dan memotong rambut-Nya yang panjang. Lalu, dilemparkan-Nya rambut itu
ke udara. Kini rambut-Nya sepanjang lebar dua jari dan tidak memanjang lagi
sampai akhir hayat-Nya.
Setelah itu, Ia menukar pakaian-Nya dengan
pakaian petapa, dan Ia memerintahkan Channa untuk segera kembali ke
Kapilavatthu. Channa memberi sembah kepada Bodhisatta dengan sangat hormat,
membawa serta tanda kebesaran kerajaan dan kuda kerajaan Kanthaka, lalu pergi
meningggalkan Bodhisatta seorang diri.
Dalam perjalanan pulang, Kanthaka yang bersedih
sejak perpisahan itu, tidak lagi dapat menahan dukanya, dan akhirnya meninggal
di perjalanan. Setelah berpisah dengan dua sahabat akrabnya, Channa akhirnya
melanjutkan perjalanan ke Kapilavatthu sambil meratap dan menangis.
Kehidupan Petapa Gotama
Setelah
memutuskan untuk meninggalkan keduniawian dan menjadi seorang petapa,
Siddhattha Gotama tinggal di Anupiya-ambavana, sebuah hutan mangga (Pali: amba;
Sanskerta: āmra; Latin: Magnifera indica) di dekat Kota Anupiyā,
tidak jauh dari Sungai Anomā selama tujuh hari pertama. Kemudian pada hari
kedelapan Ia pergi sejauh tiga puluh yojana menuju ke Rājagaha
(Sanskerta: Rājagṛha), ibu kota Kerajaan Magadha, di India Utara[1]. Di Rājagaha,
Ia menolak tawaran Raja Bimbisāra[2] yang akan
memberikan separuh kekuasaannya setelah mengetahui identitas Siddhattha Gotama
yang merupakan seorang pangeran.
DUA
ORANG GURU
Kemudian
Petapa Gotama melanjutkan perjalanan-Nya dengan menuruni Bukit Pandava (Pali: Paṇḍava-pabbata;
Sanskerta: Pāṇḍavaḥ-parvata) dan menuju ke Kota Vesāli[3], ibu kota
negara Konfederasi Vajjī[4], salah
satu negara dari 16 Mahājanapada (Negara Besar)[5]. Saat itu
Vesāli merupakan tempat tinggal seorang guru agama terkemuka bernama Āḷāra
Kālāma (Sanskerta: Ārāḍa Kālāma) bersama dengan para siswanya. Āḷāra Kālāma
diyakini telah mencapai beberapa tingkat pencapaian spiritual dari meditasi
hingga pada tingkatan konsentrasi yang tinggi yang disebut Jhāna Tataran
Kekosongan (Pali: ākiñcaññāyatana jhāna; Sanskerta: ākiṃcanyāyatana
dhyāna)[6].
Petapa Gotama memutuskan menjalani hidup suci dengan bergabung dalam persamuhan
Āḷāra Kālāma.
Dalam
waktu singkat karena memiliki kepandaian yang luar biasa, Petapa Gotama telah
mampu menguasai ilmu yang diajarkan oleh Āḷāra Kālāma bahkan mencapai
pencapaian yang sama dengan guru-Nya itu. Mendengar hal tersebut Āḷāra Kālāma
berniat menyerahkan setengah pengikutnya kepada petapa Gotama. Namun setelah
merenungkan sifat dan manfaat dari pencapaian-Nya ini, Ia menyimpulkan bahwa
ajaran yang Ia praktikkan tersebut tidaklah membawa pada Pembebasan Sejati.
Oleh karena itu Ia mohon pamit kepada guru-Nya untuk melanjutkan pencariannya
atas jawaban terhadap persoalan hidup dan mati, usia tua, dan penyakit, yang
senantiasa dipikirkan-Nya.
Petapa
Gotama segera meninggalkan Vesāli dan berjalan menuju negara Magadha. Ia
menyeberangi Sungai Mahī, dan sejenak kemudian sampai di sebuah pertapaan lain
di tepi sungai itu. Pertapaan itu dipimpin oleh seorang guru agama yang sangat
dihormati bernama Uddaka Rāmaputta (Uddaka, putra Rāma). Kemudian Petapa Gotama
pun bergabung dan menjadi siswa dari Uddaka Rāmaputta. Dalam waktu yang singkat
pula, Petapa Gotama mampu menguasai ilmu dan mencapai hasil yang diajarkan oleh
Uddaka Rāmaputta.
Setelah
itu Uddaka Rāmaputta pun akhirnya mengajarkan Petapa Gotama ajaran dari Rāma,
mendiang ayahnya yang telah mencapai Jhāna Tataran Bukan Pencerapan Maupun
Bukan Tanpa-Pencerapan (Pali: nevasaññānāsaññāyatana jhāna; Sanskerta: naivasaṃjñānāsaṃjñāyatana
dhyāna)[7]
sebagai hasil praktik meditasinya tersebut. Saat itu Uddaka Rāmaputta sendiri
belum mencapai tahap konsentrasi dari hasil praktik ajaran mendiang ayahnya
tersebut, ia hanya memiliki pengetahuan teori dari praktik yang diwariskan
kepadanya.
Dengan
keteguhan, ketekunan, konsentrasi dan perhatian murni, Petapa Gotama
mempraktikkan teknik meditasi yang diajarkan oleh gurunya tersebut hingga
dengan segera Ia berhasil mencapai tingkatan Jhāna Tataran Bukan Pencerapan
Maupun Bukan Tanpa-Pencerapan. Mendengar pencapaian siswanya tersebut, Uddaka
Rāmaputta merasa gembira dan memberikan penghormatan kepada Petapa Gotama
dengan meminta-Nya untuk memimpin dan menjadi guru dari semua siswa di
pertapaannya tersebut termasuk dirinya. Naumn, setelah merenungkan sifat dan
manfaat dari pencapaian-Nya tersebut, Ia menyimpulkan bahwa ajaran yang Ia
praktikkan tersebut tidaklah membawa pada Pembebasan Sejati. Petapa Gotama
akhirnya meninggalkan pertapaan Uddaka Rāmaputta.
MENJALANI
PRAKTIK PERTAPAAN KERAS
Setelah
meninggalkan pertapaan Uddaka Rāmaputta, Petapa Gotama menuju ke Senā-nigāma
(kota niaga Senā)[8]
di Uruvelā dan memutuskan untuk menetap di Hutan Uruvelā yang berada tidak jauh
dari kota niaga tersebut. Selama tinggal di sana, Petapa Gotama pernah
dihinggapi oleh rasa takut dan ngeri yang dapat Ia taklukkan. Di sana pulalah
Petapa Gotama bertemu dengan kelompok 5 orang petapa (Pali: pañcavaggiyā;
Sanskerta: pañcavargya) yang bernama Koṇḍañña (Aññāta-Kondañña)[9], Bhaddiya,
Vappa, Mahānāma, dan Assaji. Kelimanya menemani Petapa Gotama dengan harapan Ia
segera menjadi Buddha.
Selama
di Hutan Uruvelā, Petapa Gotama menjalankan latihan tapa yang paling berat (dukkaracariya),
yang sulit dipratikkan oleh orang biasa. Ia menyatakan tekad usaha kuat beruas
empat yang dikenal sebagai padhāna-viriya, sebagai berikut: “Biarlah
hanya kulit-Ku yang tertinggal! Biarlah hanya urat daging-Ku yang tertinggal!
Biarlah hanya tulang belulang-Ku yang tertinggal! Biarlah daging dan darah-Ku
mengering!” Dengan tekad ini, Ia tak akan mundur sejenak pun, namun akan
melakukan usaha sekuat tenaga dalam praktik itu.
Dalam
praktik pertapaan yang keras tersebut, Petapa Gotama berlatih untuk mengurangi
makan sedikit demi sedikit hingga tidak makan sama sekali. Karena melakukan hal
tersebut, tubuh-Nya berangsur-angsur menjadi semakin kurus dan akhirnya hanya
tinggal tulang belulang. Karena kurang makan, sendi-sendi dalam tubuh dan
anggota tubuh-Nya menyembul seperti sendi rerumputan atau tanaman menjalar yang
disebut āsītika dan kāḷa (Latin: Polygonum aviculare dan S.
lacustris).
Enam
tahun sudah Petapa Gotama menjalankan pertapaan yang keras dan tiba pada tahap
kritis saat Ia berada di ambang kematian. Hingga suatu hari ketika
berjalan-jalan, Ia pingsan dan terjerembab karena tubuh-Nya dilanda panas yang
tak tertahankan dan karena kurang makan berhari-hari. Ketika itu, seorang anak
laki-lagi pengembala yang kebetulan lewat di tempat terjatuhnya Petapa Gotama
membangunkan-Nya dan anak gembala itu menyuapkan air susu kambing bagi-Nya.
MENCARI
JALAN LAIN UNTUK MENCAPAI PENCERAHAN
Setelah
mempraktikkan pertapaan keras selama enam tahun, pada suatu saat di hari
pertama bulan mati, di bulan Vesākha, tahun 588 Sebelum Era Umum (528 SEU) atau
tahun 45 Sebelum Era Buddhis (SEB), Petapa Gotama merenungkan bahwa Ia belum
juga mencapai Pencerahan Sempurna, belum mencapai Pengetahuan Segala Sesuatu (sabbaññuta
nāna). Saat merenungkan apakah ada cara lain untuk mencapai Pencerahan
Sempurna, Ia teringat bahwa Beliau pernah mengembangkan dan mencapai Jhāna
Pertama saat mempraktikkan ānāpāna bhāvanā ketika duduk di bawah
keteduhan pohon jambul/jamblang (Latin: Eugenia Jambolana) sewaktu
perayaan bajak tanah yang diselenggarakan oleh ayah-Nya, Raja Suddhodana.[10]
Setelah
merenungkan manfaat dari ānāpāna bhāvanā (meditasi memperhatikan nafas),
sejak saat itu Petapa Gotama meninggalkan praktik tapa keras dan selalu menuju
ke Desa Senāni untuk menerima dana makanan serta makan setiap pagi guna
memulihkan kondisi tubuhnya. Dengan demikian Ia bisa melanjutkan pencarian-Nya
dengan menggunakan latihan pengembangan ānāpāna bhāvanā .
Melihat
Petapa Gotama keluar dari praktik pertapaan keras dan mengubah cara
latihan-Nya, kelima petapa, yang selama ini menemani dan melayani Petapa Gotama
selama enam tahun dengan pengharapan yang tinggi, mulai meragukan-Nya dan
berpikir Ia telah berhenti berjuang dan kembali menikmati kemewahan.
Setelah
itu, kelima petapa meninggalkan-Nya dan menuju ke Taman Rusa (Pali: Migadāya,
Sanskerta: Mrigadava), di Isipatana dekat Bārānasī (Benares; Varanasi). Setelah
para petapa yang melayani-Nya tersebut meninggalkan diri-Nya, Petapa Gotama
hidup menyendiri di Hutan Uruvelā. Ia berdiam dalam suasana yang sangat
terpencil, hidup dalam kesunyian total yang mendukung tercapainya kemajuan yang
luar biasa dalam pengembangan konsentrasi-Nya.
PERSEMBAHAN
DANA MAKANAN DARI SUJĀTĀ
Pada
hari kelima belas di bulan Vesākha, tahun 588 SEU (528 SEU) atau tahun 45 SEB,
ketika fajar menyingsing, Petapa Gotama membersihkan tubuh-Nya, lalu pergi
menuju ke sebatang pohon jawi (Pali: ajapāla nigrodha; Latin: Ficus
benghalensis; banyan India). Ia duduk di bawah pohon itu sambil menunggu
waktu untuk pergi menerima dana makanan.
Saat
itu pula merupakan waktu bagi masyarakat setempat untuk memberikan penghormatan
kepada para dewa, tidak terkecuali Sujātā, seorang dermawati, putri dari Senānī
– seorang hartawan di kota itu, yang telah lama melakukan penghormatan kepada
dewa penjaga pohon jawi karena telah terpenuhi harapannya untuk memiliki
seorang putra.
Sujātā
bangun pagi-pagi dan menanak sendiri nasi susu untuk persembahan. Saat menanak
nasi susu, ia memerintahkan pembantu perempuannya, Puṇṇa, untuk membersihkan
kaki pohon jawi tempat kediaman dewa penjaga yang selama ini ia berikan
penghormatan dan persembahan.
Ketika
tiba di pohon jawi yang dimaksud, Puṇṇa melihat Petapa Gotama yang sedang duduk
menghadap ke timur, di kaki pohon tersebut. Dengan mengira Petapa Gotama
sebagai dewa penjaga pohon yang telah datang, Puṇṇa bergegas pulang dan
melaporkan hal itu kepada Sujātā. Mendengar berita tersebut Sujātā sangat
bahagia. Ia menempatkan nasi susu yang telah ditanaknya ke dalam sebuah mangkuk
emas yang kemudian ia bungkus dengan sehelai kain putih bersih, kemudian ia
pergi bersama Puṇṇa menuju pohon jawi di mana Petapa Gotama duduk bermeditasi.
Melihat
Petapa Gotama yang dianggapnya sebagai dewa penjaga pohon dengan wajah-Nya yang
tampan dan tenang, hati Sujātā meluap gembira. Kemudian ia mendekati Petapa
Gotama dengan hormat lalu duduk di tempat yang sesuai, menurunkan mangkuk emas
dari kepalanya lalu membukanya dan mempersembahkan nasi susu dengan penuh bakti
dan kebahagiaan kepada Petapa Gotama seraya mengungkapkan pengharapannya agar
segala cita-cita Petapa Gotama juga terpenuhi seperti keinginannya memiliki
putra yang juga telah terpenuhi. Petapa Gotama menerima mangkuk emas berisi
nasi susu itu dari tangan Sujātā.
Sekali
lagi, Sujātā memberi hormat kepada Petapa Gotama, bangkit dari duduknya,
berjalan mundur beberapa langkah, lalu memutar badannya, dan pulang tanpa
sedikitpun memikirkan mangkuk emas yang telah ia berikan kepada Petapa Gotama.
Petapa
Gotama juga bangkit dari tempat duduk-Nya, membawa mangkuk emas berisi nasi
susu tersebut, dan berjalan menuju ke tepi Sungai Nerañjarā. Ia meletakkan
mangkuk itu, kemudian membersihkan diri di Arungan Suppatiṭṭhita. Setelah
keluar dari arungan tersebut, Ia membawa mangkuk emas itu dan duduk di bawah
naungan sebatang pohon. Mula-mula Ia membuat nasi susu itu menjadi empat puluh
sembulan cuil dan merenungkan dengan berharap keempat puluh sembilan cuil nasi
susu tersebut bisa menjadi zat makanan yang dapat menghidupi tubuh-Nya selama
tujuh minggu penuh. Setelah itu, Ia mulai memakannya.
Seusai
makan, Ia membawa mangkuk emas itu menuju sungai dan mengucapkan tekad-Nya
menjadi Buddha. Ia kemudian mengapungkan mangkuk emas tersebut di Sungai
Nerañjarā.
Catatan:
[1] Rājagaha,
sekarang bernama Rajgir terletak di negara bagian Bihar di India Utara.
[2] Raja
Bimbisāra (tradisi:628 SEU – 556 SEU; konsensus: 558 SEU – 491 SEU) merupakan
raja Magadha dari Dinasti Haryanka. Ia kemudian hari menjadi penyokong
kehidupan Sang Buddha dan para bhikkhu.
[3] Vesāli
(Sanskerta: Vaiśālī), sekarang bernama Vaishali terletak di negara
bagian Bihar di India Utara.
[4]
Konfederasi Vajjī merupakan sebuah negara republik yang mayoritas penduduknya
terdiri dari tiga kaum atau klan (Pali: gotta; Sanskerta: gotra)
yaitu Licchavī, Malla dan Sākya.
[5] 16
Mahājanapada (Negara Besar) yaitu Kāsī, Kosala, Anga, Magadha, Vajji, Mallā,
Ceti, Vamsā, Kuru, Pañcāla, Macchā, Sūrasena, Assaka, Avantī, Gandhāra dan
Kamboja.
[6] Jhāna
ke-7 dari kedelapan jhāna atau jhāna ke-3 dari Arupa jhāna. Jhāna merupakan
kondisi pikiran yang mencerap obyek saat meditasi dilakukan.
[7] Jhāna
ke-8 dari kedelapan jhāna atau jhāna ke-4 dari Arupa jhāna, merupakan jhāna
yang tertinggi.
[8]
Senā-nigāma, kota niaga (nigama) prajurit (senā). Juga disebut
Senānīnigama (kota niaga Senānī) karena tempat di mana hartawan Senānī tinggal.
[9] Koṇḍañña
(Aññāta-Kondañña atau Yañña) adalah brahmana yang pernah memastikan bayi Pangeran
Siddhattha akan menjadi Buddha. Ia juga disebut Aññā-Kondañña, Kondañña Yang
Berpengetahuan Tinggi.
[10] Beberapa
sumber mengisahkan setelah Petapa Gotama diambang kematian dan ditolong oleh
anak laki-laki gembala, Ia mendengarkan syair dari sekelompok gadis.
Ketika Petapa Gotama merenung bahwa
Ia akan mati jika tidak mendapatkan pertolongan dari anak laki-lagi gembala,
sekelompok gadis penyanyi yang tengah berjalan menuju kota berlalu di dekat
tempat Ia bermeditasi. Seraya berjalan, mereka berdendang: “Jika dawai kecapi
ditala terlalu longgar, suaranya tak akan muncul. Jika dawai ditala terlalu
kencang, dawai akan putus. Jika dawai ditala tidak terlalu longgar dan tidak
terlalu kencang, kecapi akan menghasilkan suara merdu.”
Batin
Petapa Gotama sungguh tergugah oleh syair tembang yang dilantunkan para gadis
itu. Ia telah terlalu banyak menikmati kepuasan indrawi dengan segala
kemewahannya selagi masih tinggal di istana dulu. Sebagaimana halnya dawai
kecapi yang ditala terlalu longgar, demikian pula Pencerahan tak akan tercapai
dengan pemanjaan diri. Ia juga telah menjalankan tapa sedemikian ketat hingga
hampir mati. Sebagaimana halnya dawai kecapi yang ditala terlalu kencang,
demikian pula Pencerahan tak dapat dicapai melalui penyiksaan diri.
Pencapaian Pencerahan Sempurna Petapa Gtama
Setelah menerima persembahan nasi susu dari
Sujātā di pagi hari, pada hari kelima belas di bulan Vesākha, tahun 588 Sebelum
Era Umum (528 SEU) atau tahun 45 Sebelum Era Buddhis, Petapa Gotama kemudian
pergi menuju hutan pohon
sāla (Latin:
Shorea robusta) di tepi
Sungai Nerañjarā. Di sana Ia beristirahat sejenak dan melewati sisa hari itu di
bawah naungan rindang sebatang pohon
sāla sambil berkonsentrasi dalam
keluar-masuk nafas (Pali:
ānāpāna bhāvanā)
[1].
Pada senja sore hari itu, kala udara terasa sejuk dan angin berhembus
sepoi-sepoi, Ia menuju ke Hutan Gayā, ke kaki pohon bodhi (Pali:
assattha;
Latin:
Ficus religiosa).
Dalam perjalanan, Ia bertemu dengan seorang
pengumpul rumput bernama Sotthiya, yang tengah datang dari arah yang berlawanan
sambil memikul rumput. Sotthiya sangat terkesan oleh penampilan agung Petapa
Gotama. Setelah tahu bahwa Petapa Gotama memerlukan sedikit rumput, ia lalu
mempersembahkan delapan genggam rumput kusa kepada-Nya.
Sesampainya di pohon bodhi, Petapa Gotama memeriksa
sekeliling untuk mencari tempat yang sesuai untuk bermeditasi. Setelah itu, Ia
duduk menghadap ke timur dengan bersilang kaki. Ia menyatakan tekad-Nya yang
bulat untuk tidak akan bangkit dari tempat duduk-Nya walaupun hanya kulit, urat
daging, dan tulang-Nya yang tertinggal, seluruh tubuh, daging, dan darah-Nya
mengering dan berkerut, kecuali dan sampai Ia mencapai Kebuddhaan.
TERCAPAINYA TIGA PENGETAHUAN
SEJATI
Setelah mengalami pergulatan batin yang berat
selama beberapa waktu sebelum matahari terbenam, dengan Bumi sebagai saksi-Nya,
akhirnya Petapa Gotama berhasil menundukkan rasa ngeri, keinginan duniawi, niat
buruk, dan kekejaman. Kemenangan-Nya atas pergulatan batin ditandai dengan
berjajarnya bulan purnama yang tengah menyingsing di ufuk timur dengan bulatan
merah matahari yang tengah terbenam di ufuk barat. Petapa Gotama akhirnya
mengetahui bahwa itulah saat yang tepat untuk meneruskan perjuangan-Nya
mencapai Pencerahan Agung. Pada malam bulan purnama, bulan Vesak, 588 SEU,
Petapa Gotama tetap duduk tenang memusatkan perhatian-Nya.
Setelah Ia memasuki jhāna pertama,
kedua, ketiga dan keempat dalam meditasi-Nya, pikiran-Nya yang terkonsentrasi
menjadi murni, cermelang, tanpa noda, tanpa cacat, mudah ditempa, mudah
dikendalikan, serta tak tergoyahkan. Saat itu Ia mengarahkan pikiran-Nya dan
mencapai tiga pengetahuan (Pali: tevijjā; Sanskerta: trividyā)
Pengetahuan pertama merupakan pengetahuan melihat
dengan jelas dan rinci kelahiran-kelahiran-Nya yang terdahulu (Pali: pubbenivāsānussati
ñāṇa; Sanskerta: purvanivāsānusmṛti jnāna). Hal ini terjadi pada
waktu jaga pertama, yaitu antara jam 18.00 sampai 22.00.
Pengetahuan kedua merupakan pengetahuan mata dewa
(Pali:
dibbacakkhu ñāṇa; Sanskerta:
divyacaksus jnāna)
[2]
yang dapat melihat dengan jelas lenyapnya dan munculnya kembali makhluk hidup
setelah mereka mati. Ia melihat makhluk-makhluk lenyap dan muncul kembali ke
dalam kondisi rendah dan mulia, cantik dan buruk, mujur dan malang. Hal ini
terjadi pada waktu jaga kedua, yaitu antara jam 22.00 sampai 02.00.
Pengetahuan ketiga merupakan pengetahuan akan
penghancuran noda-noda batin (Pali: āsavakkhaya ñāṇa; Sankserta: Asravaksaya
jnāna). Ia mengetahui secara langsung segala sesuatu sebagaimana
adanya. Ia menyadari dan mencerap bahwa pikiran-Nya terbebas dari noda
keinginan indrawi, noda kehidupan, dan noda kebodohan batin. Dan ketika Ia
terbebas, muncullah pengetahuan bahwa Ia telah terbebas. Ia menyadari langsung
bahwa sumber kelahiran-Nya sudah dihancurkan; hidup suci sudah dijalankan; apa
yang harus dilakukan sudah dilakukan; tiada lagi kelahiran kembali di alam mana
pun juga. Hal ini terjadi pada waktu jaga ketiga, yaitu antara jam 02.00 sampai
04.00. Ia mengetahui bahwa “inilah penderitaan”, bahwa “inilah sumber
penderitaan”, bahwa “inilah berakhirnya penderitaan”, dan bahwa “inilah jalan
menuju akhirnya penderitaan”.
Dengan tercapainya Pengetahuan Sejati Ketiga
tersebut maka Petapa Gotama mencapai
Arahatta-Magga[3].
Dan tanpa jeda waktu sedikit pun, Ia mencapai
Arahatta-Phala[4],
saat pikiran-Nya menjadi benar-benar murni. Demikianlah Petapa Gotama menjadi
Yang Sadar (Buddha), Yang Terberkahi (Pali:
Bhagavā; Sanskerta:
Bhagavant),
Yang Tercerahkan Sempurna (Pali:
Sammāsambuddha; Sanskerta:
Samyaksambuddha).
Seiring dengan Pencerahan-Nya, Petapa Gotama juga
memperoleh pengetahuan sempurna tentang Empat Kebenaran Ariya (Pali: Cattāri
Ariya Saccāni; Sanskerta: Catvāri Ārya Satyāni), Empat Pengetahuan Analisa
(Pali: paṭisambhidā ñāṇa; Sanskerta: pratisambhidā jnāna),
serta Enam Pengetahuan Khusus (Pali: Asādhāraṇa ñāṇa;
Sanskerta:Asādhāraṇa jnāna), yang kesemuanya merupakan Kebijaksanaan
Beruas Empat Belas dari seorang Buddha.
Demikianlah menjelang fajar pada hari keenam
belas, bulan Vesākha 588 SEU, atau tahun 45 Sebelum Era Buddhis, pada usia tiga
puluh lima tahun, Petapa Gotama mencapai Kemahatahuan (
Sabbaññutta ñāṇa;
Sanskerta:
Sarvajña jnāna) dan menjadi Buddha
[5]
dari tiga dunia dengan usaha-Nya sendiri.
UNGKAPAN KEBAHAGIAAN
Saat fajar, pada hari Pencerahan-Nya, pikiran
Buddha dipenuhi dengan kegiuran mendalam (Pali:
pīti; Sanskerta:
priti)
saat Ia tengah merenungkan bahwa Ia mampu menemukan kedamaian dan kebahagiaan abadi
dari Pembebasan (Pali:
Nibbāna; Sanskerta:
Nirvāṇa)
[6]
yang telah dicari-Nya begitu lama, Ia mengungkapkan kebahagiaan-Nya dengan
mengucapkan dua bait syair nyanyian pujian kebahagiaan (
udāna).
Gahakārakaṃ gavesanto dukkhā jāti punappunaṃ.”
“Gahakāraka diṭṭho’si puna gehaṃ na kāhasi
Sabbā te phāsukā bhaggā gahakauṭaṃ visaṅkhitaṃ
Visaṅkhāragataṃ cittaṃ taṇhānaṃ khayamajjhagā.”
“Beraneka kelahiran di samsara telah Kulalui
Untuk mencari, namun tak Kutemukan, pembuat rumah ini.
Sungguh menyedihkan, terlahir berulang kali!”
“O pembuat rumah! Sekarang engkau telah
terlihat!
Engkau tak dapat membuat rumah lagi!
Semua kasaumu telah dihancurkan!
Batang bubunganmu telah diruntuhkan!
Kini batin-Ku telah mencapai Yang Tak Terkondisi!
Tercapai sudah berakhirnya nafsu keinginan!”
TUJUH MINGGU SETELAH
PENCERAHAN
Setelah Pencerahan, Buddha tinggal selama tujuh
minggu di tujuh tempat yang berlainan di bawah pohon bodhi dan sekitarnya.
Selama masa itu, Ia tidak makan sama sekali; tubuh-Nya terpelihara oleh zat
makanan dari nasi susu yang dipersembahkan oleh Sujātā.
Minggu Pertama – Duduk di Bawah Pohon
Bodhi
Buddha duduk bersilang kaki di bawah pohon bodhi tanpa mengubah posisi
tubuh-Nya selama minggu pertama, sambil mengalami kebahagiaan Pembebasan (Pali:
vimuttisukha; Sankserta: vimuktisukha). Pada hari ketujuh, Ia
keluar dari keadaan konsentrasi, dan selama waktu dari jaga pertama hingga
ketiga malam itu Ia merenungkan Sebab Musabab Yang Saling Bergantungan (Pali: Paṭiccasamuppāda;
Sanskerta: Pratītyasamutpāda). Minggu pertama ini dikenal sebagai
Minggu Duduk (Pali: pallaṅka-sattāha; Sankserta: palyaṅka-saptaha).
Minggu Kedua – Menatapi Pohon Bodhi
Pada hari kedelapan, Buddha bangkit dari duduk lalu berjalan beberapa
langkah ke arah timur laut, kemudian Ia berdiri sambil menatap pohon bodhi
terus-menerus tanpa mengejapkan mata selama seminggu penuh. Hal ini
dilakukan-Nya sebagai tanda terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada
pohon bodhi yang telah menaungi-Nya selama perjuangann-Nya mencapai Pencerahan.
Minggu kedua ini dikenal sebagai Minggu Menatap Tanpa Berkedip (Pali: animisa-sattāha;
Sankserta: animiṣa-saptaha).
Minggu Ketiga – Berjalan di Sekitar Pohon
Bodhi
Pada hari kelima belas, Buddha tetap tinggal di sekitar pohon bodhi dan
berjalan-jalan sambil merenungkan Dhamma
[7]
dan terserap dalam Buah Kesucian/Hasil Pencapaian (Pali, Sanskerta:
Samāpatti
Phala)
[8].
Minggu ketiga ini dikenal sebagai Minggu Berjalan (Pali:
caṅkama-sattāha;
Sankserta:
caṅkrama-saptaha).
Minggu Keempat – Merenungkan Dhamma Lebih
Lanjut
Pada hari kedua puluh dua, Buddha tinggal di sebuah bangunan di sebelah barat
laut pohon bodhi. Ia melakukan perenungan terhadap Dhamma lebih lanjut hingga
sampai dengan menguraikan (Pali: paṭṭhāna; Sanskerta: prasthāna)
Dhamma yang berkaitan dengan 24 kondisi dari sebab dan akibat (Pali: paccaya
24; Sanskerta: pratyaya 24). Minggu keempat ini dikenal sebagai
Minggu Gerha Permata (Pali: ratanaghara-sattāha; Sanskerta: ratnagrha-saptaha).
Minggu Kelima – Berada di Pohon Jawi
Ajapāla
Pada hari kedua puluh sembilan, Buddha berjalan kaki kembali ke pohon jawi
ajapala (Pali: ajapāla nigrodha; Latin: Ficus benghalensis;
banyan India) yang terletak di sebelah timur pohon bodhi dan duduk bersilang
kaki di sana. Pada minggu ini Buddha bertemu dengan brahmin yang congkak (huhunkajātika)
dan selanjutnya bermeditasi di sana. Minggu kelima ini dikenal sebagai Minggu
Jawi (Pali: ajapāla–sattāha; Sanskerta: ajapāla-saptaha).
Minggu Keenam – Duduk di Bawah Pohon
Putat
Pada hari ketiga puluh enam, Buddha menuju ke kaki pohon putat (Pali,
Sanskerta:
ambuja; Latin:
Barringtonia acutangula; putat
India)
[9]
yang tidak jauh dari pohon jawi. Ia melewatkan tujuh hari dengan duduk
bersilang kaki dan menikmati kebahagiaan Pembebasan. Saat itu hujan turun
dengan deras, seekor Raja Ular Kobra (Pali, Sanskerta:
Nāga) Mucalinda
keluar dari kediamannya dan membelitkan dirinya sebanyak tujuh lingakaran pada
tubuh Sri Buddha serta menaungi kepala-Nya dengan kudungnya yang lebar sampai
pada akhir minggu keenam. Minggu keemam ini dikenal sebagai Minggu Mucalinda
(Pali:
mucalinda–
sattāha; Sanskerta:
mucalinda-saptaha).
Minggu Ketujuh – Duduk di Bawah Pohon Rājāyatana
Pada hari keempat puluh tiga, Buddha menuju ke kaki pohon rājāyatana
(Pali: piyāla; Sanskerta: rājānadanha, priyāla;
Latin: Buchanania latifolia; chironji) yang terletak di selatan pohon
bodhi. Ia duduk bersilang kaki di bawah pohon itu tanpa gangguan apa pun,
sambil menikmati kebahagiaan Pembebasan, selama seminggu. Minggu ketujuh ini
dikenal sebagai Minggu Rājāyatana (Pali: rājāyatana–sattāha;
Sanskerta: rājānadanha-saptaha).
PERSEMBAHAN DANA MAKANAN
PERTAMA
Pada senja hari pertama dari minggu kedelapan
setelah Pencerahan, saat Buddha sedang duduk di kaki pohon rājāyatana, dua
orang pedagang bersaudara bernama Tapussa dan Bhallika yang berasal dari
Pokkharavatī (Sanskerta: Puṣkalāvatī – sekarang Charsadda), di daerah Ukkalā
(sekarang di daerah Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan), dengan berkereta kuda menuju
Majjhimadesa (sekarang India Tengah), melewati jalan utama yang tidak jauh dari
pohon di mana Sri Buddha berada.
Setelah melihat Buddha, Tapussa dan Bhallika
mempersembahkan kue nasi dan
laḍḍu[10]
kepada-Nya. Kemudian Buddha menerima kue nasi dan
laḍḍu itu dengan
mangkuk dana yang baru. Setelah memakan persembahan itu, Ia menyatakan terima
kasih kepada pedagang bersaudara itu, yang menjadi sangat terkesan. Dan mereka
menyatakan diri bernaung kepada Buddha dan Dhamma. Demikianlah Tapussa dan
Bhallika menjadi dua siswa awam pertama dari Buddha dengan mengambil Dua
Pernaungan yaitu Buddha dan Dhamma saja.
Ketika saatnya telah tiba untuk melanjutkan
perjalanan, Tapussa dan Bhallika mengajukan permohonan agar mereka diberikan
sesuatu untuk diingat dan dipuja setiap waktu. Lalu, Buddha mengusap kepala-Nya
dengan tangan kanannya dan memberikan mereka beberapa helai rambut-Nya. Mereka
menerima relik rambut (Pali: kesadhātu; Sanskerta: kēśyadhātu)
tersebut dengan penuh hormat dengan kedua tangan mereka. Relik itu kemudian
mereka simpan dalam sebuah peti emas. Kemudian mereka meninggalkan tempat itu
dengan penuh sukacita.
Catatan:
[1]
Meditasi dengan cara memperhatikan keluar-masuknya nafas yang terjadi secara
alami.
[2]
Sering juga juga disebut dengan pengetahuan
cutūpapāta ñāṇa.
[3]
Arahatta-Magga, jalan masuk mencapai kesucian, merupakan kondisi
kesucian bagi Makhluk Suci tingkat ketujuh.
[4]
Arahatta-Phala, pahala atau hasil mencapai kesucian sempurna,
merupakan kondisi kesucian bagi Makhluk Suci tingkat kedelapan.
[5]
Berasal dari kata “
budh” dalam bahasa Pali maupun Sanskerta, yang
artinya “sadar”. Kata “
buddha “berarti “yang telah sadar” atau “yang
telah terjaga” atau “yang telah cerah”.
[6]
Nibbāna, (Sanskerta:
Nirvāna), secara harfiah berarti “padam”
(
nir +
√vā, meniup padam, menjadi padam); berdasarkan kitab
komentar berarti “bebas dari nafsu” (
nir +
vana) merupakan
tujuan akhir dan tertinggi dari semua aspirasi Buddhis. Padamnya keserakahan,
kebencian, dan kebodohan batin.
[7]
Pali: Dhamma; Sanskerta: Dharma, berasal dari kata “
dhṛ“. Secara
harfiah berarti “penopang” atau “menahan”; norma, konstitusi, hukum, ajaran;
kebenaran, keadilan; fenomena. Pengertiannya tergantung pada penggunaanya dalam
teks.
[8]
Istilah yang sama dengan kata
jhāna (Pali) atau
dhyāna
(Sankserta), yaitu kondisi pikiran yang mencerap obyek saat meditasi dilakukan.
[9]
Karena saat itu pohon putat tersebut merupakan kediaman raja naga Mucalinda, maka
sering disebut sebagai pohon Mucalinda.
[10]
Makanan manis terbuat dari tepung dan gula, yang penyajiannya dibentuk menjadi
bola-bola kecil.
Pemutaran Roda Dhamma
Setelah mencapai Pencerahan Sempurna, muncul
dalam pikiran Sri Bhagavā
[1] mengenai betapa
dalamnya, sungguh halusnya Dhamma yang telah ditemukan-Nya. Ia mempertanyakan
apakah manusia dapat memahaminya. Namun setelah dengan welas asih-Nya, Ia
memindai seluruh dunia dengan menggunakan Mata Buddha-Nya (
Buddhacakkhu),
melihat bahwa ada manusia yang dapat memahami Dhamma yang ditemukan-Nya, maka
Sri Bhagavā memiliki niat kuat untuk menyebarkan Dhamma. Kemudian Ia berkata: “
Apārutā
tesaṃ amatassa dvārā,. Ye sotavanto pamuñcantu saddhaṃ” – “Pintu menuju
tiada kematian, Nibbana, sekarang telah terbuka. Akan Kubabarkan Dhamma kepada
semua makhluk agar mereka yang memiliki keyakinan dan pendengaran yang baik
bisa sama-sama memetik manfaatnya.”
Setelah memantapkan niat untuk mengajarkan
Dhamma, Sri Bhagavā lalu menimbang-nimbang kepada siapakah Ia perlu mengajarkan
Dhamma untuk pertama kalinya, siapakah yang akan segera memahami Dhamma yang Ia
temukan. Lalu Ia berpikir bahwa Āḷāra Kālāma, salah satu guru-Nya adalah orang
yang bijaksana, terpelajar, dan berpikiran tajam, serta sedikit debu saja di
matanya. Jika Ia mengajarkan Dhamma pertama kalinya kepadanya, Āḷāra Kālāma
akan segera memahaminya. Namun kemudian Sri Bhagavā mengurungkan niat-Nya
setelah menyadari bahwa Āḷāra Kālāma telah meninggal tujuh hari yang lalu.
Kemudian, Sri Bhagavā berpikir tentang guru-Nya
yang lain, Uddaka Rāmaputta, namun lagi-lagi Sri Bhagavā mengurungkan niat-Nya
setelah menyadari bahwa Uddaka Rāmaputta telah meninggal kemarin malam.
Akhirnya Sri Bhagavā memikirkan kelima petapa (
pañcavaggiyā)
yang melayani-Nya semasa Ia melakukan tapa berat di Hutan Uruvelā. Dengan Mata
Buddha-Nya yang murni melampaui kemampuan pandang manusia, Ia mengetahui bahwa
mereka tengah berdiam di Isipatana
[2], di dekat
Banārasī (Varanasi/Banāras/Benares). Demikianlah, setelah tinggal di Uruvelā
selama yang dikehendaki-Nya, Ia berjalan menuju Banārasī, yang berjarak delapan
belas
yojana.
LIMA SISWA PERTAMA
Pada senja yang sejuk, di hari purnama bulan
Āsāḷha, 588 S.E.U, Sri Bhagavā tiba di Taman Rusa di Isipatana. Kemudian,
ketika kelima petapa melihat Sri Bhagavā semakin dekat, mereka mulai
memperhatikan bahwa Ia tidak tampak seperti Petapa Gotama yang dulu mereka
layani di Hutan Uruvelā selama enam tahun. Mereka melihat bahwa tubuh-Nya
bercahaya cemerlang tiada banding, dan mereka juga mendapatkan kesan tenteram
dan damai dari diri-Nya. Tak seorang pun di antara mereka yang sadar apa yang
tengah terjadi karena mereka akhirnya tak kuasa menaati kesepakatan awal mereka
yang menolak menghormati-Nya. Dengan segera mereka berdiri. Salah satu
mendekati-Nya dan membawakan mangkuk serta jubah luar-Nya; yang lain menyiapkan
tempat duduk; yang lainnya membawakan air, tatakan kaki, dan handuk untuk
mencuci kaki-Nya. Dan setelah Sri Bhagavā duduk, mereka memberikan hormat dan
menyapa-Nya.
Setelah itu, Sri Bhagavā menyatakan bahwa
diri-nya telah berhasil mengatasi kelahiran dan kematian dalam hidup ini dan
akan mengajarkan Dhamma yang Ia temukan kepada mereka. Dan setelah kelima
petapa itu dapat diyakinkan oleh Sri Bhagavā, kelima petapa itu duduk diam, dan
siap menerima petunjuk-Nya.
Sri Bhagavā membabarkan kotbah pertama-Nya,
Dhammacakkappavattana
Sutta (Sanskerta:
Dharmacakra Pravartana Sūtra – Khotbah Mengenai
Pemutaran Roda Dhamma)
[3].
Dalam khotbah ini, Sri Bhagavā membabarkan kepada kelima petapa tersebut
mengenai keberadaan dua jalan ekstrem – yaitu pemanjaan diri dan penyiksaan
diri – yang harus dihindari oleh orang yang telah meninggalkan keduniawian.
Kemudian Ia membabarkan Empat Kebenaran Mulia (Pali:
cattāri ariyasaccāni;
Sanskerta:
catvāri āryasatyāni). Ia juga menunjukkan praktik Jalan
Tengah (Pali:
majjhimā paṭipadā; Sanskerta:
madhyamā-pratipada),
yang terdiri dari delapan faktor, yang juga disebut Jalan Mulia Berfaktor
Delapan (Pali:
ariyo aṭṭhaṅgiko maggo; Sanskerta: āryāṣṭāṅgamārga).
Kelima petapa mendengarkan dengan saksama dan
membuka hati mereka terhadap ajaran-Nya. Dan ketika khotbah itu tengah
dibabarkan, pandangan tanpa noda dan murni terhadap Dhamma muncul dalam diri
Koṇḍañña. Ia memahami: “
Yaṃ kiñci samudayadhammaṃ sabbaṃ taṃ nirodhadhammaṃ”
– “Apa pun yang muncul pasti akan berakhir”. Demikianlah, ia menembus Empat
Kebenaran Mulia dan mencapai tataran kesucian pertama, Memasuki Arus (Pali:
Sotāpatti;
Sanskerta:
Srotāpatti)
[4] pada akhir
pembabaran itu. Karena itu, ia juga dikenal sebagai Aññata Kondañña – Kondañña
Yang Mengetahui. Lalu ia memohon penahbisan lanjut (Pali, Sankserta:
upasampadā) kepada Sri Bhagavā. Untuk itu, Sri Bhagavā menahbiskannya dengan
berkata: “
Ehi bhikkhu, svākkhāto Dhammo caro brahmacariyaṃ sammā dukkhasa
antakiriyāyā” – Mari, Bhikkhu, Dhamma telah dibabarkan dengan sempurna.
Jalanilah hidup suci demi berakhirnya penderitaan secara penuh”. Dengan
demikian, ia menjadi bhikkhu pertama dalam Buddha Sasana melalui penahbisan
Ehi
Bhikkhu Upasampadā, “Penahbisan Mari Bhikkhu”.
Setelah itu, ketika ketiga petapa lainnya pergi
menerima dana makanan, Sri Bhagavā mengajarkan dan memberikan bimbingan Dhamma
kepada Vappa dan Bhaddiya. Mereka akhirnya menjadi murni dan mencapai tataran
kesucian
Sotāpatti. Dengan segera mereka memohon untuk ditahbiskan
sebagai bhikkhu di bawah bimbingan-Nya. Keesokan harinya, Mahānāma dan Assaji
juga menembus Dhamma dan menjadi
Sotāpanna. Tanpa jeda lagi mereka
juga memohon penahbisan lanjut dari Sri Bhagavā dan menjadi bhikkhu. Dengan
demikian, kelima petapa itu menjadi lima siswa bhikkhu yang pertama, yang juga
dikenal sebagai “
Bhikkhū Pañcavaggiyā”. Sejak saat itu, Persamuhan
Bhikkhu (
Sangga Bhikkhu)
[5] terbentuk.
Setelah kelima bhikkhu itu menjadi
Sotāpanna,
pada hari kelima Sri Bhagavā membabarkan
Anattalakkhaṇa Sutta (Sanskerta:
Anātmalakṣaṇa Sūtra – Khotbah Mengenai Ciri Tiadanya Inti Diri)
[6], yang
dibabarkan sebagai tanya-jawab antara Sri Bhagavā dan kelima siswa suci-Nya.
Pada intinya, Sri Bhagavā menyatakan bahwa bentuk (Pali, Sanskerta:
rūpa),
perasaan (Pali, Sanskerta:
vedanā), pencerapan (Pali:
sañña;
Sanskerta:
saṃjñā), bentukan batin (Pali:
saṅkhāra; Sankserta:
samskāra), dan kesadaran (Pali:
viññāṇa; Sanskserta:
vijñāna)
adalah selalu berubah; dan apa yang selalu berubah tidaklah memuaskan (
dukkha).
Kemudian, kesemuanya ini yang selalu berubah dan tidak memuaskan, harus dilihat
sebagaimana adanya dengan pengertian benar: “Ini bukan milikku (
n’etaṃ mama);
ini bukan aku (
n’eso’hamasmi); ini bukan diriku (
na m’eso atta)”.
Mendengar kata-kata-Nya, kelima bhikkhu tersebut
menjadi gembira dan bahagia. Dan setelah Sri Bhagavā membabarkan khotbah ini,
pikiran mereka terbebas dan kotoran batin, tanpa kemelekatan; mereka mencapai
tataran kesucian
Arahatta[7].
PARA DUTA DHAMMA PERTAMA
Setelah Sri Bhagavā memberikan Pencerahan kepada
kelima petapa, Beliau bersama kelima siswa pertama-Nya itu berdiam di Taman
Rusa di Isipatana untuk melewati musim hujan. Dan ketika Sri Bhagavā sedang berjalan-jalan
ditempat terbuka, Ia bertemu putra seorang saudagar kaya, bernama Yasa yang
mengalami kegundahan batin terhadap kehidupannya dan pergi dari rumahnya. Yasa
tidak lain adalah putra dari Sujātā dari Senā-nigāma, seorang wanita yang
pernah mempersembahkan nasi susu kepada Petapa Gotama sebelum Pencerahan-Nya.
Setelah bertemu dengan Sri Bhagavā, Yasa
mendengarkan Dhamma yang dibabarkan oleh Sri Bhagavā dengan saksama. Dan ketika
batinnya sudah siap, bisa menerima, bebas rintangan, bersemangat, dan yakin,
Sri Bhagavā membabarkan Empat Kebenaran Mulia.
Ketika ayah Yasa mencari putranya yang telah
pergi dari rumah, ia pun bertemu dengan Sri Bhagavā. Kemudian Sri Bhagavā juga
mengajarkannya ajaran bertahap dan Empat Kebenaran Mulia seperti yang telah dilakukan-Nya
terhadap Yasa. Setelah pembabaran Dhamma selesai, ayah Yasa mencapai tataran
kesucian
Sotāpatti dan mengambil pernaungan kepada Tiga Permata (Pali:
Tiratana; Sanskerta:
Triratna – Buddha, Dhamma dan
Saṅgha).
Ia kumudian mengundang Sri Bhagavā ke rumahnya. Setelah ayahnya pergi, dengan
hormat Yasa memohon penahbisan awal (Pali:
pabbajjā; Sanskerta:
pravrajyā)
[8] dan ditahbiskan
dengan “
Ehi bhikkhu, pabbajjā” – “Mari Bhikkhu, tinggalkan
keduniawian” kemudian dilanjutkan dengan penahbisan lanjut. Demikianlah Yasa
menjadi seorang bhikkhu dan saat itu mencapai tataran kesucian
Arahatta.
Saat fajar tiba, Sri Bhagavā disertai enam
siswa-Nya, menuju ke rumah Yasa untuk memenuhi undangan. Setelah mengajarkan
Dhamma kepada ibu Yasa yaitu Sujātā, dan mantan istri Yasa, mereka menjadi Sotāpanna
dan mengambil pernaungan kepada Buddha, Dhamma dan Saṅgha.
Begitu pula kelima puluh empat teman Yasa yang
empat diantaranya adalah sahabat karib Yasa yang bernama Vimala, Subāhu,
Puṇṇaji, dan Gavampati, mereka juga menerima pengajaran dari Sri Bhagavā,
menerima penahbisan menjadi bhikkhu, dan mencapai tataran kesucian Arahatta.
Demikianlah, pada saat itu terdapat enam puluh
satu Arahant di dunia, yaitu, Buddha, Bhikkhū Pañcavaggiyā,
Bhikkhu Yasa, dan kelima puluh empat sahabat Yasa.
Pada saat berakhirnya tiga bulan masa kediaman
musim hujan (Pali: vassā; Sanskerta: varṣā), Sri Bhagavā
telah mencerahkan enam puluh tiga orang. Di antara mereka, enam puluh orang
mencapai tataran kesucian Arahatta dan memasuki Persamuhan Bhikkhu,
sementara yang lainnya – ayah, ibu, dan mantan istri Yasa menjadi Sotāpanna
dan terkukuhkan sebagai siswa awam sampai akhir hayat mereka. Kemudian, Sri
Bhagavā bermaksud menyebarkan Dhamma kepada semua makhluk di alam semesta,
tanpa memandang apakah mereka adalah dewa ataupun manusia, tanpa memandang
apakah mereka berkasta tinggi, rendah, atau paria; tanpa memandang apakah
mereka raja ataupun pelayan, kaya ataupun miskin, cantik ataupun buruk, sehat
ataupun sakit, patuh ataupun tidak patuh pada hukum.
Kemudian Sri Bhagavā berkata kepada keenam puluh
bhikkhu Arahant tersebut: “Caratha, bhikkhave, cārikaṃ
bahujanahitāya bahujanasukhāya lokānukampāya atthāya hitāya sukhāya
devamanussānaṃ. Mā ekena dve agamittha. Desetha, bhikkhave, dhammaṃ ādikalyāṇaṃ
majjhekalyāṇaṃ pariyosānakalyāṇaṃ sātthaṃ sabyañjanaṃ kevalaparipuṇṇaṃ
parisuddhaṃ brahmacariyaṃ pakāsetha. Santi sattā apparajakkhajātikā, assavanatā
dhammassa parihāyanti. Bhavissanti dhammassa aññātāro. Ahampi, bhikkhave, yena
uruvelā senānigamo tenupasaṅkamissāmi dhammadesanāyā.” (“Para Bhikkhu,
Saya telah terbebas dan semua ikatan yang mengikat makhluk hidup, baik para
dewa maupun manusia. Kalian juga telah terbebas dan semua ikatan yang mengikat
makhluk hidup, baik para dewa maupun manusia. Pergilah, para Bhikkhu, demi
kesejahteraan dan kebahagiaan banyak makhluk, atas dasar welas asih kepada
dunia, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan para dewa dan manusia.
Janganlah pergi berdua dalam satu jalan! Para Bhikkhu, babarkanlah Dhamma yang
indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, dan indah pada akhirnya, dalam
makna maupun isinya. Serukanlah hidup suci, yang sungguh sempurna dan murni.
Ada makhluk dengan sedikit debu di mata yang akan tersesat karena tidak
mendengarkan Dhamma. Ada mereka yang mampu memahami Dhamma. Para Bhikkhu, Saya
sendiri akan pergi ke Uruvelā di Senā-nigāma untuk membabarkan Dhamma.”)
Demikianlah, Sri Bhagavā mengutus keenam puluh
siswa-Nya yang telah tercerahkan untuk mengembara dan satu tempat ke tempat
lain. Ini menandakan karya duta Dhamma
[9] pertama dalam
sejarah umat manusia. Mereka menyebarluaskan Dhamma yang luhur atas dasar welas
asih terhadap makhluk lain dan tanpa mengharapkan pamrih apa pun. Mereka
membahagiakan orang dengan mengajarkan moralitas, memberikan bimbingan
meditasi, dan menunjukkan manfaat hidup suci.
Catatan:
[1]
Pali:
bhagavā; Sanskerta:
bhagavant,
bhagavan – berarti
Yang Beruntung atau Yang Terberkahi atau Yang Termulia. Kata
sri dalam
bahasa Indonesia merupakan gelar kehormatan bagi raja atau orang besar dsb;
yang mulia.
[2]
Pali: Isipatana; Sanskerta:
Rishipāṭhana – berarti tempat mengajar
atau petirahan para resi atau waskitawan (Pali:
isi; Sanskerta;
rishi).
[3]
Dhammacakkappavattana Sutta terdapat dalam Kanon Tipitaka Pali di
Saṃyutta
Nikāya,
Sacca Saṃyutta No. 11 (SN 56.11 – versi
Chaṭṭha
Saṅgāyana CD-ROM – CSCD).
[4]
Secara harfiah,
Sotāpatti berarti memasuki (Pali, Sanskerta:
āpatti)
arus (Pali:
sota; Sanskerta:
srota). Orang yang mencapainya
disebut Pemasuk Arus (Pali:
Sotāpanna; Sanskerta:
Srotāpanna).
[5]
Pali:
Bhikkhu Saṅgha (baca: biku sangga); Sanskerta:
Bhikṣu Saṃgha
(baca: biksu sangga).
[6]
Anattalakkhaṇa Sutta disebut juga
Pañcavaggiyā Sutta terdapat
dalam Kanon Tipitaka Pali di
Saṃyutta Nikāya,
Khandha Saṃyutta No.
59 (SN 22.59 – versi
Chaṭṭha Saṅgāyana CD-ROM – CSCD).
[7]
Merupakan tingkat kesucian keempat dan terakhir. Secara harfiah, berarti
berharga atau pantas atau unggul.Orang yang mencapainya disebut Yang Berharga
atau Yang Pantas atau Yang Unggul (Pali:
Arahant; Sanskerta:
Arhant).
[8]
Secara harfiah,
pabbajjā berarti keluar meninggalkan rumah atau dunia.
Kemudian menjadi istilah untuk penahbisan menjadi calon bhikkhu (Pali:
sāmaṇera;
Sanskerta:
srāmaṇera).
[9]
Duta Dhamma (Pali:
Dhamma-duta; Sanskerta:
Dharma-duta)
merupakan orang yang diutus untuk melakukan tugas berupa menyebarkan Dhamma
(Kebenaran).
Empat Puluh Lima Tahun Membabarkan Dhamma
Setelah Sri Bhagavā (Buddha) mengutus keenam puluh siswa-Nya, Ia sendiri
tetap melanjutkan pembabaran Dhamma tanpa kenal lelah selama empat puluh lima
tahun. Selama dua puluh tahun pertama masa pembabaran Dhamma ini, Sri Bhagavā
melewatkan masa berdiam musim hujan di berbagai tempat dan
vihāra
(baca: wihara)
[1].
Namun, selama dua puluh lima tahun terakhir, Ia melewatkan sebagian besar masa
berdiam-Nya di Sāvatthī. Berikut adalah kronologi pembabaran Dhamma yang
dilakukan oleh Sri Bhagavā selama empat puluh lima tahun dari tahun 588 Sebelum
Era Umum (SEU) berdasarkan penanggalan tradisi, atau 528 SEU berdasarkan
penanggalan sejarah, atau 45 Sebelum Era Buddhis (SEB), hingga 544 SEU, atau
484 SEU, atau tahun 1 SEB.
TAHUN PERTAMA (588 SEU/528 SEU/45 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Taman Rusa (Pali: Migadāya, Sanskerta: Mrigadava), di
Isipatana dekat Bārānasī (Benares; Varanasi), Kāsi.
Peristiwa utama:
Buddha membabarkan khotbah pertama Dhammacakkappavattana Sutta, Anattalakkhaṇa
Sutta, dan Ādittapariyāya Sutta; mengalihyakinkan kelima petapa (Pañcavaggiyā);
mendirikan Persamuhan (Saṅgha) Bhikkhu dan Tiga Pernaungan (Tisaraṇa);
mengalihyakinkan Yasa dan kelima puluh empat sahabatnya; mengutus para duta
Dhamma pertama; mengalihyakinkan ketiga puluh pangeran yang dikenal sebagai bhaddavaggiyā
di hutan Kappāsika; mengalihyakinkan ketiga Kassapa bersaudara beserta seribu
orang pengikut mereka.
TAHUN KEDUA SAMPAI KEEMPAT (587 – 585
SEU/527-525/44-42 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Vihara Hutan Bambu (Pali: Veluvanāramā; Sanskerta: Venuvanāramā),
di dekat Rājagaha, Magadha.
Peristiwa utama:
Buddha memenuhi janji kepada Raja Bimbisāra; menerima Vihara Veluvana sebagai
pemberian dana; menyabdakan Nasihat Menuju Pembebasan (Pali:
Ovāda
Pāṭimokkha; Sanskerta:
Avavāda Prātimokṣa)
[2];
menunjuk Sāriputta dan Moggallāna sebagai siswa bhikkhu utama (Pali:
aggasāvaka;
Sanskerta: agraśrāvaka); mengunjungi Kapilavatthu; mempertunjukkan mukjizat
ganda (Pali:
yamaka pāṭihāriya; Sanskerta:
yamaka prātihārya);
menahbiskan Pangeran Rāhula dan Pangeran Nanda; mengukuhkan Raja Suddhodana,
Ratu Mahāpajāpatī Gotamī, serta Yasodharā ke dalam arus kesucian; menahbiskan
keenam pangeran Sākya (Ānanda, Anuruddha, Bhaddiya, Bhagu, Devadatta, dan
Kimbila); bertemu dengan Anāthapiṇḍika; menerima Vihara Hutan Jeta (Jetavana)
di Sāvatthi, Kosala, sebagai pemberian dana dari Anāthapiṇḍika yang telah
membelinya dari Pangeran Jeta; bertemu dengan Raja Pasenadi (Sanskerta:
Prasenajit) dari Kosala; mendamaikan sengketa antara suku Sākya dan Koliya;
membabarkan
Mahāsamaya Sutta.
TAHUN KELIMA (584 SEU/524 SU/41 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Balairung Puncak (Pali: Kūtāgārasālā; Sanskerta: Kūṭāgārasālā),
Mahāvana, di dekat Vesāli, Vajjī.
Peristiwa utama:
Wafatnya Raja Suddhodana; Sri Bhagavā mengizinkan Ratu Mahāpajāpatī Gotamī
bersama kelima ratus putri untuk menjadi bhikkhunī; mendirikan Saṅgha
Bhikkhunī; membabarkan Khotbah Penyaluran Derma (Pali: Dakkhiṇāvibhaṅga
Sutta; Sankserta: Dakṣiṇāvibhāga Sūtra).
TAHUN KEENAM (583 SEU/523 SEU/40 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Bukit Mankula (Pali: Mankulapabbata; Sanskerta: Mankulaparvata),
di dekat Kosambī, Vamsā.
Peristiwa utama:
Ratu Khemā dari Magadha menjadi bhikkhunī dan kemudian ditunjuk
sebagai salah satu dari kedua siswi bhikkhunī utama bersama dengan
Uppalavannā dari Sāvatthi; Sri Bhagavā melarang mempertunjukkan mukjizat demi
keuntungan pribadi dan harga diri mereka sendiri; Sri Bhagavā melakukan
mukjizat ganda.
TAHUN KETUJUH (582 SEU/522 SEU/39 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Surga Tāvatiṃsa (Sankserta:
Trāyastriṃśa)
Peristiwa utama:
Buddha melakukan mukjizat; melakukan pembabaran mengenai Dhamma
[3]
di Surga Tāvatiṃsa; Ciñcāmānavikā dari Sāvatthi, memfitnah Sri Bhagavā di
Vihara Jetavana.
TAHUN KEDELAPAN (581 SEU/521 SEU/38 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Hutan Bhesakala (Pali:
Bhesakalāvana; Sanskerta:
Bhēśkalāvana),
di dekat Sumsumāragiri, Distrik Bhaggā, Vamsā.
Peristiwa utama:
Pangeran Bodhi (Bodhirājakumāra) mengundang Sri Bhagavā ke Kokanada, istana
barunya, untuk menerima dana makanan dan Sri Bhagavā membabarkan Khotbah kepada
Bodhirājakumāra (Pali:
Bodhirājakumāra Sutta; Sanskerta:
Bodhirājakumāra
Sūtra).
TAHUN KESEMBILAN (580 SEU/520 SEU/37 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Vihara Ghosita (Pali:
Ghositārāma; Sanskerta:
Ghuṣitārāma) di
Kosambī, Vamsā.
Peristiwa utama:
Māgandiyā membalas dendam karena Sri Bhagavā menolaknya sebagai istri; terjadi
sengketa di antara para bhikkhu di Kosambī.
TAHUN KESEPULUH (579 SEU/519 SEU/36 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Hutan Kecil Rakkhita (Pali:
Rakkhitavanaṣaṇḍa; Sanskerta:
Rakṣitavanaṣaṇḍa)
di dekat Desa Pārileyyaka, Vamsā.
Peristiwa utama:
Karena terjadi sengketa yang berkepanjangan di antara para bhikkhu di Kosambī,
Sri Bhagavā akhirnya menyendiri di Hutan Belukar Rakkhita, di dekat Desa
Pārileyyaka, ditemani oleh gajah Pārileyyaka. Pada penghujung kediaman musim
hujan tersebut Ānanda, atas nama para warga Sāvatthi, mengundang Sri Bhagavā
untuk kembali ke Sāvatthi. Para bhikkhu Kosambī yang bersengketa tersebut
kemudian memohon maaf kepada Sri Bhagavā dan kemudian menyelesaikan sengketa
mereka.
TAHUN KESEBELAS (578 SEU/518 SEU/35 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Vihara Dakkhināgiri (Sankserta: Dakṣiṇagiri), di Avanti.
Peristiwa utama:
Buddha mengalihyakinkan Brahmin Kasī-Bhāradvāja dari Desa Ekānalā, dengan
membabarkan Khotbah kepada Kasī-Bhāradvāja (Pali:
Kasī-Bhāradvāja Sutta);
menuju ke Kammasadamma di Negeri Kuru serta membabarkan Khotbah Besar/Panjang
tentang Perhatian Penuh (Pali:
Mahā-satipaṭṭhāna Sutta; Sankserta:
Maha-smṛtyupasthāna
Sūtra) dan Khotbah Besar/Panjang tentang Penyebab (Pali:
Mahā-Nidāna
Sutta; Sanskerta:
Mahā-Nidāna Sūtra).
TAHUN KEDUA BELAS (577 SEU/517 SEU/34 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Verañjā, di Pañcāla.
Peristiwa utama:
Sri Bhagavā memenuhi undangan seorang brahmin di Verañja untuk melewatkan
kediaman musim hujan sana. Sayangnya, waktu itu terjadi bencana kelaparan di
sana. Akibatnya, Sri Bhagavā dan para siswa-Nya hanya memperoleh makanan mentah
yang biasanya diberikan kepada kuda yang dipersembahkan oleh sekelompok
pedagang kuda.
TAHUN KETIGA BELAS (576 SEU/516 SEU/33 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Bukit Batu Cadas Cālikā (Pali:
Cālikāpabbata; Sankserta:
Cālikāparvata),
di Ceti
[4].
Peristiwa utama:
Setelah melewati kediaman musim hujan, Sri Bhagavā menuju ke Kota Bhaddiya di
Anga untuk mengalihyakinkan sang hartawan Mendaka beserta istrinya yaitu
Candapadumā, putranya yaitu Dhanañjaya, menantunya yaitu Sumanadevī, cucu
putrinya yang berumur tujuh tahun yaitu Visākhā, serta pembantunya yaitu Punna;
mengalihyakinkan Sīha, seorang panglima di Vesali yang sekaligus merupakan
pengikut Nigantha Nātaputta
[5];
membabarkan Khotbah Besar/Panjang Nasihat kepada Rāhula (Pali: Mahā-rāhulovāda
Sutta; Sanskerta:
Mahā-rāhulovāda Sūtra).
TAHUN KEEMPAT BELAS (575 SEU/515 SEU/32 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Vihara Jetavana, di Savatthi, Kosala.
Peristiwa utama:
Rāhula, putra dari Pangeran Siddhattha yang kini menjadi Buddha, menerima
penahbisan lanjut dan menjadi bhikkhu; Sri Bhagavā membabarkan Khotbah
Kecil/Singkat kepada Rāhula (Pali:
Cūla-rāhulovāda Sutta; Sanskerta:
Kṣulla-
rāhulovāda Sūtra), Khotbah mengenai Bukit Semut (Pali:
Vammīka
Sutta; Sanskerta:
Valmīka Sūtra) dan Khotbah Pali:
Sūciloma
Sutta; Sanskerta:
Sūciloma Sūtra).
TAHUN KELIMA BELAS (574 SEU/514 SEU/31 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Vihara Nigrodha (Pali:
Nigrodhārāma; Sanskerta:
Nyagrodhārāma)
di Hutan Kecil Pohon Jawi
[6],
di Kapilavatthu, Kosala.
Peristiwa utama:
Wafatnya Raja Suppabuddha, ayah-mertua Pangeran Siddhattha (Sri Buddha).
TAHUN KEENAM BELAS (573 SEU/513 SEU/30 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Cetiya Aggālava, Kota Ālavī, di antara Sāvatthi (Kosala) dan Rājagaha
(Magadha).
Peristiwa utama:
Sri Bhagavā menyelamatkan Ālavaka yang juga dikenal dengan nama Hatthaka.
TAHUN KETUJUH BELAS (572 SEU/512 SEU/29 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Vihara Hutan Bambu (Pali:
Veluvanāramā; Sanskerta:
Venuvanāramā),
Kalandakanivāpa (suaka alam tempat memberi makan tupai hitam), di dekat
Rājagaha, Magadha.
Peristiwa utama:
Buddha membabarkan Khotbah Kemenangan (Pali:
Vijaya Sutta; Sanskerta:
Vijaya
Sūtra); membabarkan Khotbah Nasihat kepada Sigāla (Pali:
Sigālovāda
Sutta; Sanskerta:
Sr̥gālovāda Sūtra), seorang perumah tangga muda
Sigāla .
TAHUN KEDELAPAN BELAS Sampai KESEMBILAN BELAS (571 – 570 SEU/511-510
SEU/28-27 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Bukit Batu Cadas Cālikā (Pali:
Cālikāpabbata; Sankserta:
Cālikāparvata),
di Ceti.
Peristiwa utama:
Sri Bhagavā memberikan khotbah kepada seorang gadis penenun beserta ayahnya di
Kota Ālavī; Sri Bhagavā mengalihyakinkan Kukkutamitta sang pemburu dan
keluarganya.
TAHUN KEDUA PULUH (569 SEU/509 SEU/26 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Veluvanāramā, di dekat Rājagaha, Magadha.
Peristiwa utama:
Buddha menetapkan aturan-aturan Pārājika
[7];
menunjuk Ananda sebagai pengiring tetap; pertemuan pertama dengan Jīvaka
Komārabhacca; mengalihyakinkan Angulimāla; Sri Bhagavā dituduh atas pembunuhan
Sundarī; meluruskan pandangan salah Brahmā Baka; menundukkan Raja Kobra (Pali,
Sanskerta:
Nāga) Nandopananda.
TAHUN KEDUA PULUH SATU SAMPAI KEEMPAT PULUH EMPAT (568-545
SEU/508-485/25-2 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Vihara Jetavana dan Vihara Pubba (Pali:
Pubbārāma; Sanskerta:
Purvārāma)
di Sāvatthi, Kosalā.
Peristiwa utama:
Kisah mengenai Raja Pukkusāti dari Gandhāra; Sri Bhagavā membabarkan Khotbah
kepada Ambattha (Pali:
Ambattha Sutta; Sanskerta:
Ambartha Sūtra)
di Desa Iccānanagala; penyerahan Vihara Pubba sebagai dana; wafatnya Raja
Bimbisāra; Bhikkhu Devadatta berusaha membunuh Sri Bhagavā; menjinakkan Gajah
Nālāgiri; Bhikkhu Devadatta menciptakan perpecahan di dalam
Sangga;
meninggalnya Bhikkhu Devadatta; pertemuan Sri Bhagavā dengan Raja Ajatāsattu
(Sanskerta:
Ajātaśatru); wafatnya Raja Pasenadi dari Kosala;
membabarkan Khotbah mengenai Pertanyaan Sakka (Pali:
Sakka Pañha Sutta;
Sanskerta:
Śakra Praśna Sūtra).
TAHUN KEEMPAT PULUH LIMA (544 SEU/484 SEU/1 SEB)
Tempat kediaman musim hujan:
Desa Beluva/Veluva (Pali:
Beluvagāma; Sanskerta:
Veluvagrāma),
di dekat Vesāli, Vajjī.
Peristiwa utama:
Buddha mengalihyakinkan Upāli Gahapati, siswa utama Nigantha Nātaputta;
membabarkan ketujuh kondisi kesejahteraan bagi para penguasa dunia dan para
bhikkhu; menyampaikan ceramah Cermin Dhamma (Pali:
Dhammādāsa
dhammapariyāya; Sanskerta:
Dharmādarśa Dharmaparyāya); menerima
Hutan Mangga (Pali:
Ambapālivana; Sanskerta:
Amrapālivana)
dari Ambapālī sebagai persembahan dana; wafatnya Sāriputta dan Moggallāna; Sri
Bhagavā sakit keras; membabarkan Empat Sumber Acuan Utama (Pali:
Cattāro
Mahāpadesā; Sankserta:
Catu Mahāpadeśa); menyantap
Sūkaramaddava[8]
yang dipersembahkan oleh Cunda Kammāraputta (Sanskerta:
Kārmāraputra –
Putra Pandai Besi) di Pāvā, Mallā ; menerima petapa kelana Subhadda sebagai
siswa terakhir.
KEGIATAN SEHARI-HARI SRI
BHAGAVA
Selama empat puluh lima tahun Sri Bhagavā membabarkan Dhamma dengan
semangat. Dan setiap hari Ia melakukan kegiatan rutin-Nya tanpa mengenal jenuh.
Kegiatan harian yang dilakukan Sri Bhagavā bisa dibagi ke dalam lima sesi,
yaitu: (1) kegiatan pagi (
pure-bhatta kicca), (2) kegiatan siang (
pacchā-bhatta
kicca), (3) kegiatan waktu jaga pertama malam (
purimāyāma kicca),
(4) kegiatan waktu jaga pertengahan malam (
majjhimāyāma kicca), dan
(5) kegiatan waktu jaga terakhir malam (
pacchimāyāma kicca).
Kegiatan Pagi (sekitar pukul 06.00 – 12.00)
Sri Bhagavā bangun pukul 04.00, kemudian setelah mandi Ia bermeditasi selama
satu jam. Setelah itu pada pukul 05.00, Beliau memindai dunia dengan Mata
Buddha-Nya untuk melihat siapa yang bisa Ia bantu. Pukul 06.00, Sri Bhagavā
menata jubah bawah, mengencangkan ikat pinggang, mengenakan jubah atas, membawa
mangkuk dana-Nya, lalu pergi menuju ke desa terdekat untuk menerima dana
makanan. Terkadang Sri Bhagavā melakukan perjalanan untuk menuntun beberapa
orang ke jalan yang benar dengan kebijaksanaan-Nya. Setelah menyelesaikan makan
sebelum tengah hari, Sri Bhagavā akan membabarkan khotbah singkat; Ia akan
mengukuhkan sebagian pendengar dalam Tiga Pernaungan. Kadang Ia memberikan
penahbisan bagi mereka yang ingin memasuki Persamuhan.
Kegiatan Siang (sekitar pukul 12.00 – 18.00)
Pada waktu ini, biasanya digunakan oleh Sri Bhagavā untuk memberikan petunjuk
kepada para bhikkhu dan untuk menjawab pertanyaan dari para bhikkhu. Setelah
itu Sri Bhagavā akan kembali ke bilik-Nya untuk beristirahat dan memindai seisi
dunia untuk melihat siapa yang memerlukan pertolongan-Nya. Lalu, menjelang
senja, Sri Bhagavā menerima para penduduk kota dan desa setempat di aula
pembabaran serta membabarkan khotbah kepada mereka. Saat Sri Bhagavā
membabarkan Dhamma, masing-masing pendengar, walaupun memiliki perangai yang
berlainan, berpikir bahwa khotbah Sri Bhagavā ditujukan secara khusus kepada
dirinya. Demikianlah cara Sri Bhagavā membabarkan Dhamma, yang sesuai dengan
waktu dan keadaannya. Ajaran luhur dari Sri Bhagavā terasa menarik, baik bagi
khalayak ramai maupun kaum cendekia.
Kegiatan Waktu Jaga Pertama Malam (sekitar pukul 18.00 – 22.00)
Setelah para umat awam pulang, Sri Bhagavā bangkit dari duduk-Nya pergi mandi.
Setelah mandi, Sri Bhagavā mengenakan jubah-Nya dengan baik dan berdiam sejenak
seorang diri di bilik-Nya. Sementara itu, para bhikkhu akan datang dari tempat
berdiamnya masing-masing dan berkmpul untuk memberikan penghormatan kepada Sri
Bhagavā. Kali ini, para bhikkhu bebas mendekati Sri Bhagavā untuk menghilangkan
keraguan mereka, untuk meminta nasihat-Nya mengenai kepelikan Dhamma, untuk
mendapatkan objek meditasi yang sesuai, dan untuk mendengarkan ajaran-Nya.
Kegiatan Waktu Jaga Pertengahan Malam (sekitar pukul 22.00 – 02.00)
Rentang waktu ini disediakan khusus bagi para makhluk surgawi seperti para dewa
dan brahma dari sepuluh ribu tata dunia. Mereka mendekati Sri Bhagavā untuk
bertanya mengenai Dhamma yang selama ini tengah mereka pikirkan. Sri Bhagavā
melewatkan tengah malam itu sepenuhnya untuk menyelesaikan semua masalah dan
kebingungan mereka.
Kegiatan Waktu Jaga Terakhir Malam (sekitar pukul 02.00 – 06.00)
Rentang waktu ini dipergunakan sepenuhnya untuk Sri Bhagavā sendiri. Pukul
02.00 sampai 03.00, Sri Bhagavā berjalan-jalan untk mengurangi penat tubuh-Nya
yang menjadi kaku karena duduk sejak fajar. Pukul 03.00 sampai 04.00, dengan
perhatian murni, Ia tidur di sisi kanan-Nya di dalam Bilik Harum-Nya (
Gandhakuti)
[9].
Pada pukul 04.00 sampai 05.00, Sri Bhagavā bangkit dari tidur, duduk bersilang
kaki dan bermeditasi menikmati
Nibbāna.
Demikianlah kegiatan harian yang dilakukan oleh Sri Bhagavā, yang Ia lakukan
sepanjang hidup-Nya.
Catatan:
[1]
Vihāra atau vihara (dibaca: wihara) secara harfiah berarti tempat
tinggal. Sering disebut juga dengan
saṅghārāma atau
ārāma
(Indonesia: asrama), merupakan bangunan yang dipergunakan oleh para
bhikkhu
dan
bhikkhunī untuk menetap hanya pada masa berdiam musim hujan.
Istilah Indonesia untuk “biara” berasal dari kata
vihāra.
[2]
Pātimokkha juga merupakan istilah untuk kode atau peraturan dasar
disiplin keviharaan (baca: kewiharaan) untuk para
bhikkhu dan
bhikkhunī.
[3]
Pembabaran mengenai Dhamma sering disebut dengan
Abhidhamma
(Sanskerta:
Abhidharma), dari kata
abhi- (mengenai) dan
dhamma/dharma.
Abhidhamma juga sering diterjemahkan sebagai Dhamma yang lebih dalam
atau tinggi.
[4]
Ceti atau Cetiya (Sanskerta : Chedi) merupakan salah satu dari 16 Mahājanapada
(Negara Besar), yang lainnya: Kāsī, Kosala, Anga, Magadha, Vajji, Mallā, Vamsā,
Kuru, Pañcāla, Macchā, Sūrasena, Assaka, Avantī, Gandhāra dan Kamboja.
[5]
Sanskerta: Nirgrantha Nathaputra. Juga dikenal dengan nama Mahavira atau
Vardhamana, merupakan seorang guru aliran Nigantha/Nirgrantha atau Jain.
[6]
Pohon banyan India (Pali:
Nigrodha; Sanskerta:
N’yagrōdha;
Latin:
Ficus benghalensis).
[7]
Peraturan mengenai pelanggaran yang serius, berat, yang tidak dapat diperbaiki,
dan menyebabkan pelanggarnya dikeluarkan dari kebhikkhuan.
[8]
Sūkaramaddava (Sanskerta:
Sūkaramārdava), adalah nama dari
sejenis makanan. Hingga sekarang, jenis makanan ini masih belum diketahui
secara pasti. Secara harfiah berasal dari kata
sūkara (babi) dan
maddava
(lunak). Menurut Dīgha Nikāya Atthakathā (kitab komentar),
Sūkaramaddava atau
daging babi lunak adalah daging dari seekor babi yang tidak terlalu muda atau
terlalu tua, yang sudah tersedia (pavattamaṃsa) dan tidak dibunuh khusus untuk
Sri Bhagavā; sebagian ahli menafsirkannya sebagai beras lunak yang ditanak
dengan lima macam makanan olahan dari sapi; sebagian ahli lainnya mengatakan
bahwa makanan tersebut adalah makanan khusus yang dipersiapkan dengan ramuan
tertentu yang disebut
rasāyana yang lezat dan sangat bergizi, dan
sementara sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa makanan tersebut adalah
tumbuhan jamur yang digemari oleh babi.
[9]
Gandhakuti secara harfiah dari kata “
gandha” (harum) dan “
kuti”
(bilik, pondok).
Perjalanan Terakhir Buddha Gotama
Menjelang tengah hari, setelah mempersiapkan
diri, membawa mangkuk dan jubah-Nya, Sri Bhagavā berjalan menuju Vesāli untuk
mengumpulkan dana makanan. Saat itu adalah tahun 544 Sebelum Era Umum (SEU)
berdasarkan tradisi, atau 484 SEU berdasarkan sejarah, tiga bulan sebelum
memasuki bulan Vesākha tahun 543 SEU (483 SEU), beberapa bulan setelah
Sāriputta dan Moggallāna, kedua Siswa Utama Sri Bhagavā mencapai Nibbāna
Seutuhnya (Pali:
Parinibbāna; Sanskerta:
Parinirvāṇa)
[1] di
hari bulan purnama bulan Kattikā.
Setelah makanan terkumpul dan disantap, dalam
perjalanan pulang Sri Bhagavā meminta Bhikkhu Ānanda untuk mengambil sehelai
tikar dan mengajaknya ke Cetiya Cāpāla di dekat Vesāli. Setelah tiba di Cetiya
Cāpāla, Sri Bhagavā memberikan sebuah petunjuk kepada Bhikkhu Ānanda mengenai
batas waktu kehidupan-Nya. Namun, saat itu Bhikkhu Ānanda tidak menyadari petunjuk
tersebut meskipun Sri Bhagavā mengulanginya sebanyak tiga kali.
Setelah mengulangi peringatan tersebut sebanyak
tiga kali dan Bhikkhu Ānanda tidak menanggapinya, Sri Bhagavā mempersilahkan
Bhikkhu Ānanda untuk melakukan hal lain yang sepatutnya ia perbuat. Bhikkhu
Ānanda lalu bangkit dari tempat duduknya, memberi hormat kepada Sri Bhagavā,
dan mengundurkan diri dengan Sri Bhagavā tetap di sebelah kanannya. Kemudian
Bhikkhu Ānanda duduk di bawah sebatang pohon pada jarak yang tidak jauh dari
tempat tersebut.
Pada saat kesendirian-Nya itu, Sri Bhagavā
menetapkan bahwa Ia akan Parinibbāna tiga bulan dari saat itu.
Kemudian, Sri Bhagavā bersama dengan Bhikkhu
Ānanda menuju Balairung Puncak (Pali: Kūtāgārasālā; Sanskerta: Kūṭāgārasālā)
di Mahāvana, dan memintanya untuk memanggil semua bhikkhu yang berada di
sekitar Vesāli untuk berkumpul di aula pertemuan.
Setelah membabarkan mengenai Ketiga Puluh Tujuh
Syarat Pencerahan (Pali: Bodhipakkhiyādhammā; Sanskerta: Bodhipākṣikadharma)
kepada Sangga (Pali: Saṅgha; Sanskerta: Saṃgha) Bhikkhu, Sri
Bhagavā memberitahukan saat Parinibbāna-Nya:
“
Handa dāni, bhikkhave, āmantayāmi vo,
vayadhammā saṅkhārā, appamādena sampādetha. Naciraṃ tathāgatassaparinibbānaṃ
bhavissati. Ito tiṇṇaṃ māsānaṃ accayena tathāgato parinibbāyissatī.”
(“Saat ini, para Bhikkhu, Saya nyatakan kepada kalian: semua hal yang terbentuk
dari perpaduan pasti akan hancur. Berusahalah dengan tekun! Mangkatnya
Tathāgata tak lama lagi akan terjadi. Tiga bulan sejak saat ini, Tathāgata
[2]
akan mencapai Parinibbāna.”)
Inilah yang dikatakan Sri Bhagavā. Setelah
mengatakan hal tersebut, Sri Bhagavā melantunkan syair berikut:
‘‘Paripakko vayo mayhaṃ, parittaṃ mama
jīvitaṃ; Pahāya vo gamissāmi, kataṃ me saraṇamattano. Appamattā satīmanto,
susīlā hotha bhikkhavo; Susamāhitasaṅkappā, sacittamanurakkhatha. Yo imasmiṃ
dhammavinaye, appamatto vihassati; Pahāya jātisaṃsāraṃ, dukkhassantaṃ
karissatī.” (“Telah lanjut usia-Ku, hidup-Ku hanya tersisa sedikit. Aku
akan berangkat meninggalkan kalian. Aku telah menjadikan diri-Ku sebagai
pernaungan-Ku sendiri. Berusahalah dengan tekun dan dengan perhatian penuh!
Bersikap baik, O para Bhikkhu! Dengan pikiran yang terpusat penuh, jagalah
batin kalian! Barang siapa berusaha dengan tekun dalam ajaran ini, akan
meninggalkan lingkaran tumimbal lahir dan mencapai akhir segala derita.”)
Di hari berikutnya, saat fajar, Sri Bhagavā
menata jubah-Nya; sambil membawa mangkuk dana dan jubah luar-Nya, Ia menuju
Vesāli untuk menerima dana makanan. Setelah menerima dana makanan dan
bersantap, saat meninggalkan tempat itu Ia membalikkan badan dan menatap Vesāli
dengan tatapan sesosok gajah pengading suci. Lalu ia berkata kepada Bhikkhu
Ānanda, “Ānanda, inilah terakhir kalinya Tathāgata menatap Vesāli. Mari,
Ānanda, mari kita pergi ke Bhandagāma!”
Dengan diiringin sejumlah besar bhikkhu, Sri
Bhagavā menempuh perjalanan ke Bhandagāma di Vajjī. Setelah tinggal di Bhandagāma
selama yang dikehendaki-Nya, Sri Bhagavā menempuh perjalanan secara bertahap
dengan sejumlah besar bhikkhu ke Hatthigāma, Ambagāma, Jambugāma, dan kemudian
ke Bhoganagara (Bhogagāmanagara). Selagi di Bhoganagara, Sri Bhagava
mengajarkan kepada sekumpulan banyak bhikkhu mengenai Empat Sumber Acuan Utama
(Pali: Cattāro Mahāpadesā; Sankserta: Catu Mahāpadeśa).
MAKANAN TERAKHIR SRI BHAGAVĀ
Kemudian, setelah Sri Bhagavā tinggal di
Bhoganagara, Ia melanjutkan perjalanan ke Pāvā dengan sekumpulan besar bhikkhu
dan tinggal di hutan mangga milik Cunda Kammāraputta (Sanskerta: Kārmāraputra
– Putra Pandai Besi).
Mendengar berita kedatangan Sri Bhagavā di hutan
mangganya, Cunda segera menghadap Sri Bhagavā dan memberi sembah hormat
pada-Nya. Sri Bhagavā memberinya dorongan dengan pembabaran Dhamma serta
membahagiakannya dalam latihan Dhamma. Setelah mendengarkan Dhamma, Cunda
mengundang Sri Bhagavā beserta Sangha bhikkhu untuk menerima persembahan dana
makanan keesokan harinya. Sri Bhagavā menyetujuinya dengan berdiam diri.
Keesokan harinya, Cunda mempersiapkan makanan
yang mewah, termasuk masakan khusus yang disebut Sūkaramaddava
[3].
Ketika makanan dipersembahkan, Sri Bhagavā meminta
Cunda untuk menghidangkan Sūkaramaddava kepada diri-Nya semata, dan
menghidangkan makanan lainnya bagi Sangha bhikkhu. Seusai makan, Sri Bhagavā
meminta Cunda untuk memendam sisa Sūkaramaddava itu di dalam lubang karena Ia
tidak melihat siapa pun yang mampu mencernanya dengan baik. Dan setelah memakan
makanan yang dipersembahkan oleh Cunda, Sang Bhagavā diserang oleh penyakit
parah hingga mengalami diare berdarah disertai dengan rasa sakit yang sangat
menusuk. Sri Bhagavā menahan rasa sakit tersebut tanpa mengeluh dan tetap
berperhatian penuh dengan kesadaran jernih. Dengan menahan sakit, Sri Bhagavā
berkata, “Mari, kita pergi ke Kusinārā.”
PERJALANAN MENUJU KUSINĀRĀ
Dalam perjalanan ke Kusinārā di negara Mallā, Sri
Bhagavā merasa letih dan haus. Ia duduk di bawah sebatang pohon dan meminta
Bhikkhu Ānanda untuk mengambilkan air di aliran air di sekitar tempat itu.
Namun beberapa kereta baru saja lewat sehingga aliran air tersebut menjadi
keruh. Bhikkhu Ānanda menyarankan Sri Bhagavā, “Bhante, Sungai Kakutthā berada
tidak jauh dari sini; air dingin di sungai itu jernih, menyegarkan, tidak
kotor; tepian sungai itu bersih dan menyenangkan. Sri Bhagavā bisa minum dan
menyejukkan tungkai di sana.”
Untuk kedua kalinya, Sri Bhagavā meminta dan
menerima jawaban yang sama. Setelah yang ketiga kalinya, Bhikkhu Ānanda menurut
dan berkata, “Baiklah, Bhante.” Dan ketika Bhikkhu Ānanda tiba di aliran air
itu, berkat kekuatan Sri Bhagavā, ia mendapatkan aliran air yang dangkal itu
menjadi jernih, murni, dan tidak kotor. Lalu ia mengambil air dan memasukkannya
ke dalam mangkuk dananya. Kemudian ia kembali menghadap Sri Bhagavā dan
memberitahukan-Nya apa yang telah terjadi, seraya menambahkan: “Semoga Sri
Bhagavā bersedia minum air ini! Semoga Yang Mahasuci bersedia minum air ini!”
Lalu, Sri Bhagavā pun minum.
Setelah Sri Bhagavā minum dan ketika masih duduk
di kaki pohon itu, seorang pangeran Mallā yang bernama Pukkusa – seorang siswa
Āḷāra Kālāma yang sedang menempuh perjalanan dari Kusinārā menuju Pava, melihat
Sri Bhagavā dan menghadap-Nya. Ia menceritakan pengalaman gurunya dalam
meditasi. Kemudian Sri Bhagavā menceritakan pengalaman-Nya kepada Pukkusa.
Pukkusa sungguh terkesan dengan ketenangan Sri Bhagavā, lalu ia mengambil
pernaungan dalam Tiga permata sampai akhir hayatnya. Setelah itu, ia
mempersembahkan sepasang jubah berwarna keemasan kepada Sri Bhagavā. Akan
tetapi, Sri Bhagavā meminta Pukkusa untuk mempersembahkan sehelai jubah
kepada-Nya dan sehelai lainnya kepada Bhikkhu Ānanda.
Segera setelah Pukkusa pergi, Bhikkhu Ānanda
memakaikan pasangan jubah keemasan itu di tubuh Sri Bhagavā. Ia terkejut karena
warna cemerlang dari jubah keemasan itu pudar ketika dipakaikan pada tubuh Sri
Bhagavā. Melihat hal ini, Bhikkhu Ānanda berseru terhadap apa yang dilihatnya.
Untuk itu, Sri Bhagavā menjelaskan bahwa ada dua peristiwa yang bisa
menyebabkan warna alami dari kulit Tathāgata menjadi sangat bersih dan
bersinar, yaitu pada malam hari saat Ia mencapai Nibbāna, dan pada malam Ia
mencapai Parinibbāna.
Sri Bhagavā lalu menyatakan bahwa pada waktu jaga
malam terakhir hari itu juga di antara kedua pohon sāla kembar di
hutan sāla (Latin: Shorea robusta) milik kaum Mallā, di dekat
Kusinārā, Tathāgata akan mencapai Parinibbāna.
Kemudian, Sri Bhagavā melanjutkan perjalanan ke
Sungai Kakutthā, dan di sana Ia mandi untuk yang terakhir kalinya, dan meminum
air sungai tersebut. Setelah itu, Ia menuju ke sebuah hutan mangga dan
beristirahat sejenak di sana, dengan berbaring di sisi kanan-Nya laksana singa
yang tengah tidur. Ia berbaring pada jubah luar yang telah disiapkan oleh
Bhikkhu Cundaka.
Ketika beristirahat di sana, Sri Bhagavā berkata
kepada Bhikkhu Ānanda agar menghalau rasa sesal yang muncul dalam diri Cunda,
putra si pandai besi ketika ada orang yang menganggap bahwa ia adalah orang
yang tidak beruntung karena Tathāgata wafat setelah menyantap makanan
terakhir-Nya yang ia siapkan. Rasa sesal Cunda perlu dihilangkan dengan
mengatakan bahwa ia adalah seseorang yang mujur besar karena Tathāgata wafat
setelah menyantap makanan terakhir-Nya yang ia siapkan. Sri Bhagavā juga
menyatakan bahwa ada dua pemberian dana yang luar biasa, yaitu dana yang
dimakan Tathāgata tepat sebelum Ia mencapai Nibbana dan dana yang dimakan
Tathāgata tepat sebelum Ia mencapai Parinibbāna.
DI BAWAH POHON SĀLA KEMBAR
Setelah istirahat singkat itu, Sri Bhagavā
melanjutkan perjalanan akhir-Nya dengan serombongan besar bhikkhu, Mereka
menyeberangi Sungai Hiraññavatī dan menuju ke hutan sāla milik kaum
Mallā di dekat Kusinārā, tempat peristirahatan-Nya yang terakhir.
Saat tiba di sana, Sri Bhagavā meminta Bhikkhu
Ānanda untuk meyiapkan dipan di antara dua pohon sāla kembar itu,
dengan bagian kepala dipan menghadap ke utara. Setelah siap, Sri Bhagavā
berbaring di sisi kanan-Nya dalam postur singa, dengan tungkai kaki yang satu
tertumpu pada yang lainnya, berperhatian penuh dan sangat sadar. Saat itu,
banyak sekali bunga bermekaran di pohon sāla kembar tersebut, meskipun
saat itu belum musim bunga.
Pada kesempatan itu, Sri Bhagavā memberikan
petunjuk mengenai empat tempat yang layak diziarahi oleh umat yang penuh
keyakinan dan yang akan menginspirasikan kebangkitan spiritual dalam diri
mereka. Tempat-tempat itu meliputi:
1. Lumbini, tempat kelahiran Tathāgata.
2. Buddha Gaya, tempat Tathāgata mencapai Pencerahan Sempurna.
3. Taman Rusa di Isipatana dekat Bārānasī (Benares; Varanasi), tempat Tathāgata
memutar roda Dhamma pertama kali.
4. Kusinārā, tempat Tathāgata mencapai Parinibbāna, Pembebasan Akhir,
terhentinya kelima gugus secara penuh.
Lalu Bhikkhu Ānanda menanyakan berbagai hal di
antaranya bagaimana sebaiknya para bhikkhu memperlakukan sisa-sisa tubuh
Tathāgata. Sri Bhagavā menjawab, “Ānanda, janganlah merepotkan diri dengan
menghormati sisa-sisa tubuh Tathāgata. Engkau harus berusaha untuk mencapai
tujuan tinggi. Curahkanlah usahamu untuk mencapai Nibbana! Berlatihlah dengan
gigih, tekun, dan tanpa lalai demi kebaikan tertinggi dirimu sendiri. Ada kaum
kesatria, kaum brahmana, dan perubah tangga yang bijaksana, yang memiliki
keyakinan teguh terhadap Tathāgata; mereka akan menghormati sisa-sisa tubuh
Tathāgata.”
Setelah tanya jawab tersebut, Bhikkhu Ānanda
merasa sedih bahwa hari itu juga Tathāgata akan mencapai Parinibbāna. Ia lalu
masuk ke sebuah gubuk tempat tinggal, bersandar pada tiang pintu, dan berdiri
sambil meratap. Menyadari bahwa Bhikkhu Ānanda tidak berada di sisi-Nya, Sri
Bhagavā meminta seorang bhikkhu untuk memanggilnya menghadap, lalu Sri Bhagavā
menghibur Bhikkhu Ānanda.
Sri Bhagavā memuji Bhikkhu Ānanda sebagai
seseorang yang bijaksana dan piawai dalam mengatur waktu yang tepat bagi para
bhikkhu, bhikkhuni, upasaka, dan upasika untuk datang menjumpai Sri Bhagavā.
Sri Bhagavā juga mengagumi Bhikkhu Ānanda karena memiliki empat sifat yang
sangat baik dan mengagumkan.
Setelah itu Sri Bhagavā membabarkan Khotbah
mengenai Raja Sudassana Yang Agung (Pali: Mahāsudassana Sutta;
Sanskerta: Mahāsudarśana Sūtra – Kemegahan Agung) dan kemudian Ia
meminta Bhikkhu Ānanda untuk pergi ke Kusinārā untuk mengumumkan kepada kaum
Mallā dari Kusinārā bahwa Tathāgata akan mencapai Parinibbāna pada
waktu jaga malam yang ketiga, yaitu antara jam 02.00 sampai 04.00. Mendengar
pesan yang disampaikan oleh Bhikkhu Ānanda, para pangeran Mallā, dengan para
putra, putri, menantu perempuan, serta para istri mereka merasa sangat sedih
dan sangat terpukul oleh derita dan duka. Mereka menuju ke hutan sāla
itu untuk memberikan penghormatan yang terakhir pada Sri Bhagavā.
PENAHBISAN TERAKHIR
Saat itu, seorang petapa kelana (paribbājaka)
bernama Subhaddha sedang tinggal di Kusinārā. Ia mendengar bahwa Petapa Gotama
akan mencapai Parinibbāna pada waktu jaga malam yang ketiga. Ia berpikir,
”Telah kudengar dari para sesepuh yang mulia serta guru-guru dari para petapa
kelana bahwa sungguh amat langka para Yang Tercerahkan Sempurna, para
Tathāgata, muncul di dunia ini. Dan malam ini, pada waktu jaga malam yang
terakhir, Petapa Gotama akan mencapai Nibbana Akhir. Keraguan telah muncul
dalam batinku dan aku memiliki keyakinan terhadap Petapa Gotama bahwa Ia bisa mengajarkanku
ajaran tersebut sedemikian rupa agar aku bisa menghalau keraguanku.”
Tanpa menunda waktu, Subhadda pergi ke hutan sāla
itu dan menghadap Bhikkhu Ānanda, menyatakan pemikirannya, namun Bhikkhu Ānanda
menolak mempertemukannya dengan Sri Bhagavā dengan alasan bahwa Sri Bhagavā
merasa letih. Subhadda mengulangi permintaannya untuk yang kedua dan ketiga
kalinya, namun Bhikkhu Ānanda menjawab dengan cara yang sama dan menolaknya.
Mendengar percakapan antara Bhikkhu Ānanda dan Subhadda, Sri Bhagavā memanggil
Bhikkhu Ānanda: “Cukup, Ānanda! Jangan halangi Subhadda! Biarkan ia menghadap
Tathāgata! Karena apa pun yang akan ditanyakan Subhadda kepada Saya, ia hendak
bertanya demi memuaskan keinginannya memperoleh pengetahuan sempurna, bukan
untuk mengganggu Saya, dan apa pun jawaban Saya terhadap pertanyaannya akan
segera dipahaminya.”
Lalu Bhikkhu Ānanda berkata: “Pergilah, Sahabat
Subhadda! Sri Bhagavā memperkenankanmu.”
Setelah bertukar salam hangat dengan Sri Bhagavā
dan duduk di satu sisi, Subhadda mengajukan pertanyaan yang membuatnya ragu.
Kemudian Sri Bhagavā membabarkan Dhamma kepadanya:
“Subhadda, dalam Dhamma dan Vinaya mana pun yang
tidak mengandung empat Kebenaran Arya, tidak akan terdapat satu pun petapa
dengan tingkat kesucian pertama (Sotāpatti), tidak akan terdapat satu pun
petapa dengan tingkat kesucian kedua (Sakadāgāmī), tingkat kesucian ketiga
(Anāgāmī), maupun tingkat kesucian keempat (Arahatta). Dalam Dhamma dan Vinaya
mana pun yang mengandung Empat Kebenaran Mulia, akan terdapat pula para petapa
dengan tingkat kesucian pertama, tingkat kesucian kedua, tingkat kesucian
ketiga, dan tingkat kesucian keempat.”
Setelah Sri Bhagavā selesai membabarkan Dhamma,
Subhadda merasa takjub dan menyatakan bernaung kepada Buddha, Dhamma, dan
Sangha, serta memohon untuk ditahbiskan. Sri Bhagavā menerima Subhadda dalam
Persamuhan para bhikkhu tanpa menjalani masa percobaan.
Lalu Subhadda menerima penahbisan awal dan
penahbisan penuh ke dalam Persamuhan selaku bhikkhu di hadapan Sri Bhagavā. Ia
dibimbing oleh-Nya untuk bermeditasi dengan cara yang tepat. Setelah itu
Bhikkhu Subhadda memencilkan diri, bermeditasi dengan menjaga perhatian penuh
secara berkesinambungan, berusaha dengan tekun, dan mengarahkan batinnya untuk
mencapai kesucian Arahatta. Ia merupakan orang terakhir diterima oleh Sri
Bhagavā memasuki Persamuhan dan yang terakhir menjadi Arahant saat Sri Bhagavā
masih hidup.
SABDA TERAKHIR
Sri Bhagavā berkata kepada Bhikkhu Ānanda:
“Ānanda, engkau mungkin berpikir: ‘Bimbingan dan Sang Guru tak ada lagi;
sekarang kita tak lagi memiliki guru.’ Namun, engkau tak seharusnya berpikir
demikian karena apa yang telah Saya ajarkan dan Saya babarkan kepadamu sebagai
Dhamma dan Vinaya
[4]
akan menjadi gurumu setelah Saya wafat.”
“Sampai saat ini, para bhikkhu saling menyapa
dengan sebutan ‘Āvuso’
[5],
namun mereka sebaiknya tidak melakukan hal ini setelah Saya mangkat. Bhikkhu
yang lebih tua seharusnya menyapa bhikkhu yang lebih muda dengan nama bhikkhu
atau nama keluarganya, atau sebagai ‘Āvuso’. Dan bhikkhu yang lebih muda
seharusnya menyapa bhikkhu yang lebih tua sebagai ‘Bhante’
[6]
atau Āyasmā
[7].”
“Ānanda, jika memang diinginkan, Sangha boleh
menghapuskan aturan-aturan kecil dan yang kurang penting setelah Saya mangkat.”
“Dan Ānanda, setelah Saya mangkat nanti, hukuman
berat sekali (brahmadaṇḍa) harus dijatuhkan kepada Channa.
[8]”
“Tapi, Bhante, apa hukuman berat sekali itu?”
“Apa pun yang diinginkan ataupun yang dikatakan
Channa, ia tak boleh disapa, ditegur, ataupun dibimbing oleh para bhikkhu
lainnya.”
Lalu Sri Bhagavā berkata kepada para bhikkhu
demikian: “Para Bhikkhu, mungkin saja ada bhikkhu yang memiliki keraguan atau
ketidakpastian mengenai Buddha, Dhammu, Sangha, Jalan Suci, ataupun mengenai
cara latihan. Bertanyalah sekarang, Para Bhikkhu! Jangan menyesal kelak dengan
berpikir: ‘Kami berhadapan muka dengan Sang Guru, namun kami gagal bertanya
kepada Yang Terberkahi langsung untuk menghalau keraguan kami’”
Ketika hal mi disampaikan, para bhikkhu diam
saja. Untuk kedua dan ketiga kalinya, Sri Bhagavā mengulangi kata-kata¬Nya, dan
mereka tetap saja diam. Lalu Sri Bhagavā berkata: “Para Bhikkhu, mungkin karena
rasa hormat terhadap Sang Gurulah kalian tidak bertanya kepada Saya. Kalau
begitu, Para Bhikkhu, biarlah sahabat yang satu menyampaikannya kepada yang
lainnya!” Akan tetapi, mereka tetap saja diam.
Lalu Bhikkhu Ānanda berkata kepada Sri Bhagavā:
“Menakjubkan, Bhante! Menakjubkan, Bhante! Saya begitu yakin bahwa di dalam
kumpulan mi tak seorang bhikkhu pun yang memiliki keraguan atau kebimbangan
mengenai Buddha, Dhamma, Sangha, Jalan Suci, ataupun mengenai cara latihan.”
“Ānanda, engkau berkata atas keyakinan, namun
Tathāgata mengetahui bahwa di dalam kumpulan ini tak seorang bhikkhu pun yang
memiliki keraguan atau kebimbangan mengenai Buddha, Dhamma, Sangha, Jalan Suci,
ataupun mengenai cara latihan. Ānanda, di antara kelima ratus bhikkhu ini, yang
paling rendah pun adalah seorang Sotāpanna
[9],
yang tak akan terjatuh ke alam rendah, namun kelak pasti akan mencapai
Pencerahan.”
Lalu Yang Terberkahi berkata kepada para bhikkhu
dan memberikan bimbingan-Nya yang terakhir:
“
Handa dāni, bhikkhave, āmantayāmi vo,
vayadhammā saṅkhārā, appamādena sampādetha.”
[10]
(“Saat ini, para Bhikkhu, Saya nyatakan kepada kalian: semua hal yang terbentuk
dari perpaduan pasti akan hancur. Berusahalah dengan tekun!”)
Catatan:
[1]
Parinibbāna (Sanskerta:
Parinirvāṇa), secara harfiah berarti
nibbāna
seutuhnya, berasal dari kata “
pari” (seutuhnya, seluruhnya, komplet)
dan kata “
nibbāna” (padam). Disebut juga
anupādisesa nibbāna
yang berarti
nibbāna tanpa lima gugusan/kelompok kehidupan yang
tersisa. Merupakan pencapaian
Nibbāna bagi para Arahant yang telah
mangkat.
[2]
Tathāgata, secara harfiah berarti Yang Datang atau Pergi dengan Cara
Demikian, berasal dari kata “
tathā” (dengan cara demikian) dan kata “
gata”
(pergi atau datang). merupakan sebutan atau gelar bagi Buddha.
[3]
Sūkaramaddava (Sanskerta:
Sūkaramārdava), adalah nama dari
sejenis makanan. Hingga sekarang, jenis makanan ini masih belum diketahui
secara pasti. Secara harfiah berasal dari kata
sūkara (babi) dan
maddava
(lunak). Menurut Dīgha Nikāya Atthakathā (kitab komentar),
Sūkaramaddava atau
daging babi lunak adalah daging dari seekor babi yang tidak terlalu muda atau
terlalu tua, yang sudah tersedia (pavattamaṃsa) dan tidak dibunuh khusus untuk
Sri Bhagavā; sebagian ahli menafsirkannya sebagai beras lunak yang ditanak
dengan lima macam makanan olahan dari sapi; sebagian ahli lainnya mengatakan
bahwa makanan tersebut adalah makanan khusus yang dipersiapkan dengan ramuan
tertentu yang disebut
rasāyana yang lezat dan sangat bergizi, dan
sementara sebagian ahli lainnya mengatakan bahwa makanan tersebut adalah
tumbuhan jamur yang digemari oleh babi.
[4]
Disiplin, peraturan, penuntun.
[5]
Teman atau Saudara.
[6]
Yang Terhormat atau Guru.
[7]
Yang Mulia.
[8]
Channa adalah kusir Pangeran Gotama, dan telah lama bergabung dalam Sangha,
namun memperlihatkan sikap yang suka melawan. Perlakuan yang dikenakan
kepadanya oleh perintah Sri Buddha adalah untuk mengembalikan kesadarannya.
[9]
Sanskerta:
Srotāpanna, dari kata “
srota” (arus) dan “
āpanna”
(masuk) yang berarti Pemasuk Arus, yaitu mereka yang telah mencapai tingkat
kesucian pertama karena telah masuk ke dalam arus atau Jalan kesucian.
[10]
Appamādena sampādetha, berasal dari kata “
appamādena” (tanpa
lengah, tanpa lalai; lawan kata: tekun) dan “
sampādetha” (berusaha,
berjuang). Kata-kata ini juga muncul sebelumnya di
Kūtāgārasālā ketika
Buddha Gotama
memberitahukan
kepada Sangga Bhikkhu mengenai Parinibbāna-Nya .
Mahaparinibbana Buddha Gotama
Setelah Sri Bhagavā menyampaikan pesan
terakhir-Nya, seluruh hutan sala itu menjadi sunyi senyap. Sri Bhagavā memasuki
jhāna pertama. Dan setelah keluar dari
jhāna tersebut, Ia
memasuki
jhāna kedua, ketiga, dan keempat. Lalu keluar dari
jhāna
keempat, Ia memasuki Tataran Ruang Nirbatas (Pali:
ākāsānañcāyatana;
Sanskerta:
ākāśa-anantya-āyatana)
[1],
Tataran Kesadaran Nirbatas (Pali:
viññāṇañcāyatana; Sanskerta:
vijñāna-anantya-āyatana)
[2],
Tataran Tanpa Ada Apa Pun (Pali:
ākiñcaññāyatana; Sankserta:
akiñcana-āyatana)
[3], serta
Tataran Bukan Pencerapan Maupun Bukan Tanpa-Pencerapan (
nevasaññā-n’asaññāyatana)
[4]. Dan
setelah itu, Ia mencapai dan terserap dalam Padamnya Pencerapan dan Perasaan (
saññāvedayita-nirodha)
[5].
Bhikkhu Ānanda, yang memperhatikan bahwa Sri
Bhagavā tidak bernafas, menjadi cemas dan berkata kepada Bhikkhu Anuruddha:
“Sahabat Anuruddha, Sri Bhagavā telah mangkat.”
“Tidak, Sahabat Ānanda, Sri Bhagavā belum
mangkat. Ia hanya memasuki Padamnya Pencerapan dan Perasaan.”
Lalu, keluar dari Padamnya Pencerapan dan
Perasaan itu, Sri Bhagavā memasuki Tataran Bukan Pencerapan Maupun Bukan
Tanpa-Pencerapan. Setelah itu Ia memasuki Tataran Tanpa Ada Apa Pun, Tataran
Kesadaran Nirbatas, dan Tataran Ruang Nirbatas. Lalu keluar dari Tataran Ruang
Nirbatas, Ia memasuki jhāna keempat, jhāna ketiga, jhāna
kedua, dan jhāna pertama.
Kemudian, keluar dari jhāna pertama, Ia
memasuki jhāna kedua, jhāna ketiga, dan jhāna
keempat. Setelah keluar dari jhāna keempat, Sri Bhagavā mencapai Nibbāna
Seutuhnya atau Parinibbāna.
Tepat saat Sri Bhagavā mencapai Parinibbāna,
terjadilah gempa yang dahsyat dan mengerikan, diiringi guntur yang menyebabkan
orang berdiri kudunya dan merinding.
Pada saat itulah, pada waktu jaga malam yang
terakhir, pada hari bulan purnama, bulan Vesākha 543 SEU
[6] dan
pada usia delapan puluh tahun, Sri Bhagavā mangkat tanpa meninggalkan sisa apa
pun.
PROSESI KREMASI
Demikianlah, ketika Sri Bhagavā mangkat, beberapa
bhikkhu yang belum melenyapkan kesenangan nafsu dengan mengangkat tangan mereka
menangis, membanting diri di tanah sambil berguling-guling kian ke mari, dan
meratap. Tetapi para bhikkhu yang telah bebas dari hawa nafsu dengan penuh
kesadaran dan pengertian yang benar, merenung dalam batin: “Segala sesuatu
adalah tidak kekal, bersifat sementara. Bagaimanakah yang akan terjadi, jika
tidak terjadi demikian?”
Kini Bhikkhu Anuruddha dan Bhikkhu Ānanda selama
satu malam suntuk memperbincangkan Dhamma. Kemudian Bhikkhu Anuruddha berkata
kepada Bhikkhu Ānanda : “Ānanda, sekarang pergilah ke Kusinārā, umumkanlah
kepada suku Malla : “Vasetha, ketahuilah bahwa Sri Bhagavā telah mangkat.
Sekarang terserahlah kepada saudara-saudara sekalian.” “Baiklah, Sahabat.” Lalu
Bhikkhu Ānanda dengan seorang kawannya mempersiapkan diri sebelum tengah hari
dan sambil membawa patta serta jubahnya menuju ke Kusinārā. Pada saat itu suku
Malla dari Kusinārā sedang berkumpul dalam ruang persidangan untuk merundingkan
soal itu juga. Takala Bhikkhu Ānanda menemui mereka, lalu mengumumkan :
“Vasetha, ketahuilah bahwa Sri Bhagavā telah mangkat. Sekarang terserahlah
kepada saudara-saudara sekalian.”
Demikianlah, ketika mereka mendengar kata-kata
Bhikkhu Ānanda, suku Malla dengan semua anak, istri, menantu mereka menjadi
sedih, berduka cita dan sangat susah kelihatannya, ada di antara mereka dengan
rambut yang kusut serta mengangkat tangan mereka menangis, membanting diri di
tanah sambil berguling-guling kian ke mari dan meratap
Setelah suku Malla tiba di tempat dimana Sri
Bhagavā mangkat, mereka mengadakan penghormatan dengan menyajikan tari-tarian,
nyanyi-nyanyian dan lagu kebaktian, serta mempersembahkan bunga-bungaan,
wangi-wangian dan segala sesuatu yang dibawanya; lalu mereka mendirikan
kemah-kemah dan kubu-kubu untuk bernaung selama mereka ada di sana, melakukan
upacara penghormatan terhadap jenazah Sri Bhagavā itu selama tujuh hari.
Pada hari ketujuh, dengan hikmat dan tertib
mereka mengusung jenazah Sri Bhagavā itu ke arah Utara, ke bagian Utara dari
kota, dan sesudah melalui pintu gerbang Utara, lalu menuju ke pusat kota, dan
sesudah melewati pintu gerbang sebelah Timur mereka menuju ke Makuṭabandhana,
sebuah cetiya dari suku Malla, dan di sanalah jenazah Sri Bhagavā
dibaringkan.
Kemudian mereka membungkus jenazah Sri Bhagavā
seluruhnya dengan kain linen baru, lalu dengan kain wol-katun yang telah
disiapkan; dan demikian seterusnya sehingga lima ratus lapisan kain linen dan
lima ratus lapisan kain wol-katun. Setelah itu dikerjakan, mereka membaringkan
jenazah Sri Bhagavā di dalam sebuah penampung minyak berwarna keemasan, lalu
ditutup dengan penampung keemasan lainnya. Kemudian mereka mendirikan pancaka
yang dibuat dari segala macam kayu-kayu harum dan di atas pancaka itulah jenazah
Sri Bhagavā ditempatkan.
Waktu kremasi pun tiba, Bhikkhu Mahā Kassapa dan
rombongan lima ratus bhikkhu yang mengiringinya dari Pāvā tiba di tempat
pancaka Sri Bhagavā di Makuṭabandhana, cetiya dari suku Malla, di
Kusinārā. Beliau lalu mengatur jubahnya pada salah satu bahunya, dan dengan
tangan tercakup di muka, beliau memberi hormat kepada Sri Bhagavā; beliau
berjalan mengitari pancaka sebanyak tiga kali, kemudian menghadap pada jenazah
Sri Bhagavā, lalu beliau berlutut menghormat pada jenazah Sri Bhagavā. Hal yang
serupa itu juga dilakukan oleh kelima ratus bhikkhu itu.
Demikianlah setelah dilakukan penghormatan oleh
Mahā Kassapa beserta kelima ratus bhikkhu itu, maka di pancaka Sri Bhagavā lalu
terlihat api menyala dengan sendirinya dan membakar seluruhnya.
Demikanlah terjadi ketika itu jenazah Sri Bhagavā
mulai dibakar; yang mula-mula terbakar adalah kulitnya, jaringan daging,
urat-urat dan cairan-cairan semua itu tiada yang nampak, abu maupun
bagian-bagiannya, hanya tulang-tulanglah yang tertinggal. Tepat sama seperti
lemak atau minyak saat dibakar tidak meninggalkan bagian-bagiannya atau
debu-debunya, demikian pula dengan jenazah Sri Bhagavā setelah terbakar, apa
yang dinamakan kulit, jaringan, daging, urat-uratan serta cairan, tidak nampak
debu atau bagian-bagiannya, hanya tulang-tulang yang tertinggal. Dari kelima
ratus lapisan kain linen pembungkusnya, hanya dua yang tidak musnah, yaitu yang
paling dalam dan yang paling luar.
Setelah api kremasi padam, suku Malla dari
Kusinārā, mengambil relik (sisa jasmani) Sri Bhagavā, lalu ditempatkan di
tengah-tengah ruangan sidang mereka, yang kemudian dipagari sekelilingnya
dengan anyaman tombak-tombak, lalu dilapisi lagi dengan pagar dari panah dan
busur-busur.
Di sanalah mereka mengadakan upacara puja bakti
selama tujuh hari. Untuk menghormati relik Sri Bhagavā dengan tari-tarian,
nyanyian dan lagu-lagu kebaktian, serta mempersembahkan bunga-bungaan dan
wangi-wangian, melakukan puja bakti terhadap relik Sri Bhagavā.
PEMBAGIAN RELIK-RELIK SRI
BHAGAVĀ
Kemudian Raja Magadha, Ajātasattu, putera Ratu
Videhi, mendengar bahwa Sri Bhagavā telah mangkat di Kusinārā. Ia mengirim
utusan kepada suku Malla di Kusinārā dan menyatakan: “Sri Bhagavā adalah
seorang kesatria; demikianlah pula saya. Karena itu saya pantas untuk menerima
sebagian relik Sri Bhagavā. Untuk relik Sri Bhagavā itu saya akan dirikan
sebuah stupa; dan untuk menghormati-Nya, saya akan mengadakan suatu kebaktian
dan perayaan.”
Demikian pula halnya dengan orang Licchavi dari
Vesāli, suku Sakya dari Kapilavatthu, suku Bulī dari Allakappa, suku Koliya
dari Rāmagāma, sang Brahmana dari Vethadīpa, Suku Malla dari Pāvā, mereka telah
mendengar Sri Bhagavā telah mangkat di Kusinārā, mereka segera mengirim utusan
mereka untuk mendapatkan bagian relik Sri Bhagavā.
Tetapi suku Malla di Kusinārā menolak untuk
memberikan kepada mereka. Dan situasi menjadi memanas. Pada saat kritis ini,
Brahmana Dona datang untuk mendamaikan mereka, ia berkata:
“Wahai saudara-saudara dengarlah sepatah kata
dariku, Sang Buddha, Maha Guru yang kita junjung tinggi, telah mengajarkan,
agar kita selalu bersabar, sungguh tak layak, jika timbul ketegangan nanti,
timbul perkelahian, peperangan karena relik Beliau, Manusia Agung yang tak
ternilai. Marilah kita bersama, wahai para hadirin, dalam suasana persaudaraan
yang rukun dan damai, membagi menjadi delapan, peninggalan yang suci ini,
sehingga setiap penjuru, jauh tersebar di sana sini, terdapat stupa-stupa yang
megah menjulang tinggi, dan jika melihat semua itu, lalu timbul dalam sanubari,
suatu keyakinan yang teguh terhadap Beliau.”
Lalu kumpulan orang-orang itu menjawab, “Jika
demikian, Brahmana, bagilah relik Sri Bhagavā dengan cara terbaik dan teradil
menjadi delapan bagian yang sama rata!’
Kemudian Brahmana Dona membagi dengan adil, dalam
delapan bagian yang sama, semua peninggalan Sri Bhagavā itu. Setelah selesai
membagi itu, ia berkata kepada sidang demikian: “Biarlah tempayan ini,
saudara-saudara berikan kepadaku. Untuk tempayan ini akan kudirikan sebuah
stupa, dan sebagai penghormatan, aku akan mengadakan perayaan dan kebaktian.”
Tempayan itu lalu diberikan kepada Brahmana Dona.
Namun kemudian suku Moriya dari Pippalivana
mengetahui bahwa Sri Bhagavā telah mangkat di Kusinārā. Mereka mengirim suatu
utusan pada kaum Malla dari Kusinārā untuk mendapatkan relik Sri Bhagavā.
Tetapi oleh karena relik sudah habis terbagi, maka mereka dianjurkan mengambil
abu-abu dari peninggalan Sri Bhagavā. Dan mereka mengambil abu-abu dari Sri
Bhagavā, lalu dibawa pulang ke kotanya.
Kemudian raja dari Magadha, Ajatasattu, putera
dari ratu Videhi, mendirikan sebuah stupa besar untuk relik Sri Bhagavā, di
Rajagaha, dan sebagai penghormatan diadakan suatu perayaan dan kebaktian. Orang
Licchavi dari Vesāli mendirikan sebuah stupa besar untuk relik Sri Bhagavā di Vesāli.
Suku Sakya dari Kapilavasthu mendirikan sebuah stupa besar untuk relik Sri
Bhagavā di Kapilavatthu. Suku Bulī dari Allakappa mendirikan sebuah stupa besar
untuk relik Sri Bhagavā di Allakappa. Suku Koliya dari Rāmagāma mendirikan
sebuah stupa besar untuk relik Sri Bhagavā di Rāmagāma. Brahmana dari Vethadīpa
mendirikan sebuah stupa besar untuk relik Sri Bhagavā di Vethadīpa. Kaum Malla
dari Pāvā mendirikan sebuah stupa besar untuk relik Sri Bhagavā di Pāvā. Suku
Malla dari Kusinārā mendirikan sebuah stupa besar untuk relik Sri Bhagavā di
Kusinārā. Brahmana Dona mendirikan sebuah stupa besar untuk Tempayan (bekas
tempat relik Sri Bhagavā). Suku Moriya dari Pipphalivana mendirikan sebuah
stupa besar untuk abu Sri Bhagavā di Pipphalivana, dan sebagai penghormatan
diadakan suatu perayaan dan kebaktian.
Demikian maka terdapat delapan stupa untuk relik
Sri Bhagavā dan stupa yang kesembilan untuk tempayan dan stupa yang kesepuluh
untuk abu Sri Bhagavā.
Demikianlah riwayat hidup Buddha Gotama, Sri
Bhagavā, Arahant, Sammāsambuddha.
Evam
PERMASALAHAN SEJARAH
Secara tradisi, riwayat hidup Buddha Gotama
dihiasi dengan peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang tidak umum, yang tidak
bisa ditemukan pada masa sekarang dengan kaca mata awam, seperti bunga yang
bermekaran sebelum musimnya, bayi baru lahir yang bisa berjalan, perjalanan ke
surga, dan sebagainya. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa kisah
mengenai Siddhattha adalah suatu mitos dan tokoh Siddhattha sebenarnya tidak
pernah ada.
Namun, Prof. Hermann Oldenberg (1854 – 1920),
seorang sarjana Indologi asal Jerman, berpendapat bahwa kisah mengenai
Siddhattha disesuaikan dengan keadaan pada masa itu. Oleh karena itu jika kita
ingin mengetahui kebenarannya, maka segala kisah yang luar biasa harus
ditiadakan. Kemudian sisa dari kisah tersebut disusun sehingga mendekati
keadaan yang sebenarnya. Sebagai kesimpulan, Prof. Oldenberg berpendapat bahwa
Siddhattha memang benar-benar pernah ada. Begitu juga dengan Prof. Johan
Hendrik Caspar Kern (1833 – 1917) salah seorang pendiri dari Studi Oriental di
Belanda. Beliau mengakui bahwa Siddhattha, memang pernah ada.
Beberapa penemuan arkeologi seperti penemuan
situs Lumbini pada tahun 1896 oleh para arkeolog Nepal, penemuan situs
Kapilavatthu (Kapilavastu) di Tilaurakot, Nepal pada abad ke-19, serta penemuan
situs Nigrodharama yang juga berada di Nepal, memperkuat bahwa kisah mengenai
Pangeran Siddhattha bukanlah fiksi. Ia adalah tokoh sejarah.
Pada masa sekarang, pada umumnya para ahli
sejarah mengakui bahwa Siddhattha adalah tokoh yang pernah ada. Namun, terlepas
dari pendapat dari para ahli sejarah maupun penemuan arkeologi di atas,
kehidupan pribadi Pangeran Siddhattha sebelum menjadi Buddha tidaklah menjadi
hal yang utama bagi umat Buddha. Tetapi, yang menjadi hal utama bagi umat
Buddha adalah ajaran-Nya – ajaran yang membawa pada pembebasan dari dosa
(kebencian), lobha (keserakahan) dan moha (kegelapan batin).
Catatan:
[1]
ākāsānañcāyatana, berasal dari kata
ākāsā (ruang) +
ananca
(nirbatas) + āyatana (dasar batin, tataran), merupakan tingkat ke-1 dari
kondisi batin mencerap yang disebut
arūpajhāna (
jhāna tanpa
bentuk); disebut juga
jhāna ke-5.
[2]
viññāṇañcāyatana, berasal dari kata
viññāṇa (kesadaran) +
ananca
(nirbatas) + āyatana (dasar batin, tataran), merupakan tingkat ke-2 dari
kondisi batin mencerap yang disebut
arūpajhāna (
jhāna tanpa
bentuk); disebut juga
jhāna ke-6.
[3]
ākiñcaññāyatana, berasal dari kata
ākiñcañña (tanpa ada apa
pun, ketiadaaan) + āyatana (dasar batin, tataran), merupakan tingkat ke-3 dari
kondisi batin mencerap yang disebut
arūpajhāna (
jhāna tanpa
bentuk); disebut juga
jhāna ke-7.
[4]
nevasaññā-n’asaññāyatana, berasal dari kata
nevasaññā (bukan
pencerapan) +
n’asañña (bukan tanpa pencerapan)+ āyatana (dasar batin,
tataran), merupakan tingkat ke-4 dari kondisi batin mencerap yang disebut
arūpajhāna
(
jhāna tanpa bentuk); disebut juga
jhāna ke-8.
[5]
saññāvedayita-nirodha, berasal dari kata
saññā (pencerapan)
+ vedayita (perasaan, pengalaman) +
nirodha (padam, berhenti,
berakhir), merupakan kondisi saat fungsi batin atau kesadaran yaitu perasaan
dan pencerapan berhenti atau padam.
[6]
Berdasarkan konsensus sejarawan awal abad ke-20 menetapkan tahun 483 Sebelum
Era Umum (SEU).
Disusun oleh:
Bhagavant.com
Editor:
Sumita
Kepustakaan:
Maha Parinibbana Sutta; Pandita Pannasiri, Cornelis Wowor, MA, CV.
Lovina Indah, Jakarta, 1989.
The Great Chronicle of Buddhas; Tipiṭakadhara Miṅgun Sayadaw (Mingun
Sayadaw U Vicittasarabivamsa), Myanmar, 1960.
Riwayat Hidup Buddha Gotama; Pandita. S. Widyadharma, Yayasan Dana
Pendidikan Buddhis Nalanda, Jakarta, 1993.
Kronologi Hidup Buddha; Bhikkhu Kusaladhamma, Yayasan Penerbit
Karaniya, Jakarta, 2006.
Buddha: His Life, His Doctrine, His Order; Hermann Oldenberg,
Williams, London,1882
Samanta Buddhist Glossaries; Buddhistdoor.com
Sanskrit Dictionary for Spoken Sanskrit; Spokensanskrit.de