Jangan membuat kepalamu menjadi
perpustakaan. Sebarluaskanlah semua pengetahuanmu.
Renungan Waisak
Oleh Batara R. Hutagalung
Menjelang perayaan Trisuci Waisak -yaitu hari kelahiran Pangeran Siddharta Gotama (Gautama), hari tatkala Sang Pertapa Gotama mencapai pencerahan yang sempurna setelah bersamadhi di bawah pohon Bodhi, dan juga hari meninggalnya Sang Budhha Gotama yang oleh penganut ajaran Buddha dinamakan Parinibbana (Sansekerta: parinirvana) Sang Buddha- aku merenungkan banyak hal yang menyangkut diriku, putraku, keluargaku, masyarakat di lingkunganku, bangsaku dan juga masyarakat internasional, terutama yang sehubungan dengan kehidupan dan kerukunan beragama.
Beberapa tahun belakangan, di seluruh dunia banyak terjadi konflik kekerasan yang menggunakan simbol-simbol keagamaan dan mengatasnamakan agama, bahkan pembunuhan ratusan sampai ribuan manusia juga atas nama agama. Masing-masing pihak menyatakan bahwa yang dilakukannya adalah demi agamanya, demi Tuhannya, demi Allahnya.
Aku sungguh tidak dapat mengerti, mengapa agama yang seharusnya membawa kedamaian di muka bumi, mengajarkan manusia untuk saling mengasihi, justru digunakan sebagai alasan dan pembenaran untuk pembunuhan sesama manusia, dan bahkan yang berasal dari satu agama, namun berbeda aliran. Kelompok yang satu menyatakan, bahwa yang diyakini oleh kelompok lain adalah aliran sesat.
Ada kelompok yang selalu merasa terganggu bukan hanya dengan keberadaan komunitas agama yang berbeda, namun juga tidak memberikan toleransi terhadap perbedaan sekecil apapun, selain keyakinan yang dianutnya. Semua ingin diseragamkan. Budaya, perilaku, ukuran moral, cara berbusana dsb. ingin diseragamkan.
Apakah agamanya yang salah? Apakah Tuhannya atau Allahnya yang salah menurunkan ajaran? Ataukah manusianya yang tidak mengerti makna ajaran yang sebenarnya? Aku tak tahu. Belum tahu. Mungkin tak akan pernah tahu.
Aku sendiri dibesarkan di keluarga Kristen Protestan. Mengenai atribut Protestan baru kuketahui ketika aku kuliah di Universitas Hamburg, Jerman (dahulu Barat), di tahun 70-an. Kata tersebut berasal dari kata protes, yaitu protes terhadap gereja katholik di Jerman. Pada 31 Oktober 1517 di Wittenberg, Jerman, Dr. Martin Luther yang waktu itu beragama Katholik, menyampaikan 95 thesisnya yang merupakan reformasi terhadap gereja Katholik. Dia membentuk komunitasnya sendiri dan komunitasnya disebut sebagai Protestan, yaitu yang melakukan protes. Di Jerman sendiri, pengikut Martin Luther menamakan diri sebagai Evangelis Lutheran.
Abad 16 - 17 di Eropa sedang berkecamuk wabah reformasi, bukan hanya di Jerman. Namun sempalan Katholik di Jerman tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh sempalan Katholik di Perancis, yang dinamakan kaum Hugenott. Tahun 1685 sekitar 50.000 orang Hugenott dari Perancis melarikan diri ke Jerman dan sebagian besar ditampung di Prusia.
Konflik antara Kristen Katholik dan Kristen Protestan di Eropa berlangsung cukup lama dan mengakibatkan pertumpahan darah yang besar, seperti juga yang terjadi antara Islam aliran Syiah dan Islam aliran Suni, yang juga telah berlangsung lebih dari seribu tahun dan menelan korban yang luar biasa besarnya di kedua belah pihak. Konflik ini masih berlangsung hingga sekarang, seperti terlihat di Irlandia Utara antara Kristen Katholik dengan Kristen Protestan, dan di Irak antara kelompok Suni dan kelompok Syiah.
Di Universitas Hamburg, aku mengambil jurusan sosiologi dan psikologi sebagai vak utama (Hauptfächer), dan filosofi sebagai vak tambahan wajib (Pflicht-Nebenfach). Aku harus membiayai sendiri biaya hidup dan kuliahku, dan karena menghadapi beberapa kesulitan, aku tak dapat menamatkan kuliahku.
Gedung fakultas teologi letaknya tepat di muka asrama tempatku tinggal. Aku memang juga gemar membaca buku-buku berbagai agama, sehingga aku juga sering mengikuti kuliah-kuliah teologi Kristen Protestan. Di Uni Hamburg, untuk banyak jurusan dan sejauh tempat tersedia, para mahasiswa dapat mengikuti kuliah dari beragam jurusan. Apabila telah terdaftar sebagai mahasiswa di Uni Hamburg, dia cukup mencatatkan nama di fakultas yang bersangkutan, dan mencatatkan nama pada daftar yang tersedia di awal semester, kemudian dia dapat mengikuti kuliah yang diminatinya.
Yang mengambil jurusan Teologi Kristen di Uni Hamburg, tidak hanya dari yang beragama Kristen Protestan, melainkan juga yang berlatarbelakang agama lain, bahkan ada beberapa pendeta Buddhis.
Waktu itu di Hamburg ada seorang Pendeta Kristen dari Indonesia, Mangasi S. Siahaan, yang sedang melanjutkan studinya di bidang teologi, dan kemudian berhasil meraih gelar Doktor Theologi di Uni Hamburg, kalau tak salah, dengan predikat Magna Cum Laude. Seringkali sebelum kuliah, dia mampir ke asramaku untuk ngopi dan ngobrol, dan berdiskusi mengenai berbagai hal, termasuk mengenai keagamaan.
Juga ada Pendeta Kristen muda dari Indonesia, Sahat Tobing, yang juga melanjutkan studinya di Uni Hamburg. Dan masih ada beberapa Pendeta Kristen Indonesia lain, yang juga sering berdiskusi denganku mengenai agama.
Aku juga mempunyai seorang teman baik orang Jerman, Peter Marwedel, anggota Partai Komunis Jerman (KPD). Aku sering menyindir dia, karena dia memiliki mobil Mercedez Benz. Aku bilang, “ Peter, kamu seorang komunis, kok naik Mercedez? Seharusnya kamu naik Volkswagen (VW).” Dia menjawab:” Aku ‘kan sering ke luar kota, jadi perlu mobil dengan mesin yang kuat.”
Aku katakan: “Ah Peter, itu cuma alasan pembenaranmu. Menurutku, kau seorang komunis yang berpikiran kapitalistik.” Peter cuma cengar-cengir saja dan bilang: “Terserah. Apapun pendapatmu, itu hakmu untuk menilai tindakanku. Aku tak akan berubah hanya karena ucapanmu.” Kami tetap berteman baik, walaupun sering berdebat dan berbeda pendapat.
Dengan merekalah aku sering berdiskusi. Mendiskusikan berbagai agama, berbagai ajaran, berbagai jalan keselamatan, berbagai thesis dan anti-thesis.
Dari semua ajaran yang aku pelajari dan diskusikan, jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Sidharta Gotama (Gautama) yang paling menarik bagiku. Yang sangat terkesan bagiku dari ajarannya adalah, bahwa segala sesuatunya terpulang pada diri kita sendiri. Semua perbuatannmu adalah tanggungjawabmu sendiri. Untuk perbuatan baik, kau akan menerima balasan yang baik, dan untuk perbuatanmu yang buruk, kau akan menerima akibat yang buruk juga. Ini yang dikenal sebagai Hukum Karma, atau Hukum Perbuatan. Jangan menggantungkan nasibmu atau apapun kepada sesuatu yang kau tak ketahui. Itulah esensi yang kutangkap dari sekian banyak buku mengenai ajarannya yang dinamakan Buddhisme.
Menurut pendapatku, di dalam ajaran Buddha, tidak ada dogma, melainkan semuanya anjuran. Mengenai apakah mematuhi dan menjalankannya atau tidak, adalah tanggungjawab kita sendiri.
Salah satu dasar ajaran Buddha adalah Panca – Sila. Kata Panca-Sila ini diadopsi oleh Ir. Sukarno untuk memberi nama lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dibacakannya pada 1 Juni 1945.
Kata Panca-Sila sendiri berasal dari bahasa Pali. Panca artinya lima dan Sila pengertian sebenarnya adalah dasar, namun dalam pengertian Buddhis, Sila adalah kerelaan jiwa diri sendiri, setelah memahami mengenai sebab dan akibat, untuk kemudian memegang dan menjalankannya agar kita dapat mencapai Pencerahan dan Nirvana (Pali: Nibbana). Nirvana bukanlah suatu tempat seperti surga, melainkan suatu keadaan, di mana mata-rantai atau lingkaran dari kelahiran-dewasa-sakit-mati-lahir kembali, dst. telah diputus.
Jika melanggar Sila, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya dan ini bukan merupakan hukuman dari Buddha.
Kelima sila dalam Panca – Sila yang dianjurkan untuk dipegang dan dilaksanakan adalah
Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami (Menahan diri dari pembunuhan),
Adinadana veramani (Menahan diri dari pencurian),
Kamesumicchacara veramani (Menahan diri dari perzinaan)
Musavada veramani (Menahan diri dari pendustaan),
Sura-meraya-majja pamadtthana veramani (Menahan diri dari minuman dan barang-barang yang memabukkan).
Sejak tahun 1974, aku memutuskan masuk agama Buddha dan mencoba mengikuti semua anjuran Buddha. Dalam pemahamanku mengenai sila pertama, yang dimaksud dengan pembunuhan, adalah termasuk pembunuhan terhadap hewan untuk santapan manusia. Aku dapat menerima pendapat, bahwa hewanpun mempunyai hak hidup yang sama. Oleh karena itu, juga sejak tahun 1974 aku memutuskan untuk hidup sebagai seorang vegetarian, alias tidak makan daging dan ikan samasekali. Sehubungan dengan sila kelima, sejak lima tahun aku sudah berhenti minum alkohol. Dahulu ketika masih di Jerman, itulah minumanku sehari-hari. Mengenai sila-sila yang lain, perlahan-lahan aku usahakan untuk kupenuhi. Terus terang aku akui, masih sulit sekali untuk dilaksanakan sepenuhnya. Sangat sulit! Mungkin kalau aku bisa menjalankan kelima sila tersebut dengan sempurna, maka aku dapat mencapai pencerahan yang sempurna juga. Tapi sekarang belum …
Dari kumpulan tulisan ucapan Buddha Gotama –yang ditulis oleh muridnya, Ananda- yaitu Tripitaka, atau Tiga Keranjang (Bahasa Jerman: Drei Körbe) yang tebalnya ribuan halaman, mungkin belum separuhnya yang kubaca.
Aku juga tidak mau mengikuti aliran apapun, apakah itu Mahayana, Hinayana, Theravada, Zen Buddhisme, Buddhisme Tibet, karena semua aliran itu merupakan sinkretisme, telah bercampur dengan nilai-nilai agama setempat, sebelum datangnya Buddhisme. Sinkretisme ini terdapat di semua agama. Masih banyak orang Jawa yang beragama Islam, dalam melakukan ritual adat, memberikan sesajen untuk Dewi Sri. Dalam ajaran Islam ‘kan tak ada Dewi Sri. Juga tak ada Nyai Roro Kidul.
Oleh karena itu, aku tidak mengikuti aliran apapun dalam Buddhisme. Aku hanya membatasi diri untuk memahami nilai-nilai dasar yang terkandung dalam inti ajaran Buddha, dengan pemahamanku sendiri, bukan berdasarkan pemahaman atau penafsiran orang lain. Aku hanya berpegang pada Tripitaka ... dan penafsiranku sendiri.
Aku bersyukur, bahwa belum pernah terjadi, ada aliran dalam Buddhisme disebut sebagai aliran sesat dan dilarang oleh aliran atau kelompok lain, seperti yang terjadi pada komunitas Ahmadiyah di Indonesia, atau pada Lia Aminuddin, yang ditangkap oleh Polisi, dengan tuduhan penghinaan terhadap agama. Lia Aminuddin mengaku mendapat wahyu dari Malaikat Jibril. Demikian juga dengan seseorang yang katanya biasa melakukan Shalat dengan bersiul. Kini diapun mendekam di tahanan.
Padahal Undang-Undang Dasar ’45 (UUD ’45) menjamin kebebasan beragama setiap warga. Bab XI mengenai Agama, Pasal 29 (2) berbunyi::
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Selain itu, Bab X A mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E (2) berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”
Pasal 28 I (2) berbunyi:
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Pasal 28 J (1) berbunyi:
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
Jadi sangat mengherankan, bahwa para penyelenggara negara, tidak memperhatikan Undang-Undang Dasar, yang seharusnya menjadi landasan dan acuan semua ucapan, keputusan dan tindakan mereka.
Kini, tahun 2006, oleh Mendagri dan Menteri Agama diterbitkan Surat Peraturan Bersama (SPB) yang menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, SKB no. 01 BER/MDN-MAG/1969, tahun 1969, yang mengatur agar pendirian tempat ibadah harus dengan seizin masyarakat setempat. Sepertinya, di negeri ini, segala sesuatu yang semakin dicoba untuk diatur, semakin ambur-adul. Dari data-data yang diperoleh berbagai pihak, sebelum dikeluarkannya SKB tahun 1969, perusakan, pembakaran dan penutupan gereja relatif kecil, dibandingkan setelah dikeluarkannya SKB dua Menteri.
Bahkan, apabila dicermati, SPB dua Menteri tahun 2006 ini jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan SKB tahun 1969, karena dalam SPB, kehidupan dan kerukunan beragama “dikendalikan” oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat-pejabat setempat.
Dari tahun 1965 s/d 1974 (10 tahun) terjadi perusakan 46 Gereja atau rata-rata 4,6 gedung Gereja yang dirusak per tahun. Kemudian antara tahun 1975 s/d 1984 (10 tahun) jumlah Gereja yang dirusak meningkat 89 atau rata-rata 8,9 per tahun. Demikian pula antara tahun 1985 s/d 1994 (10 tahun) terjadi peningkatan 2 x lipat dari jumlah sebelumnya, yaitu 132 Gereja atau rata-rata 13,2 per tahun. Dan kemudian antara 1995-1997 (2 tahun), terjadi peningkatan yang sangat mencolok dimana jumlah Gereja yang dirusak menjadi 105 atau rata-rata 52,5 per tahun. Hingga 1 Juli 1997, telah terjadi penutupan, perusakan dan pembakaran 374 Gereja. Perusakan tersebut diatas, belum termasuk perusakan rumah ibadah agama lain seperti Vihara maupun fasilitas Pemerintah, swasta dan fasilitas umum. Selanjutnya lihat tabel di:
lihat:http://www.fica.org/persecution/374.html
Sayang aku belum mendapat data yang akurat mengenai jumlah gereja, vihara, dll. yang dirusak, dibakar atau ditutup paksa antara 1997 – 2006. Menurut perkiraan beberapa pihak, hingga tahun 2006, jumlah gereja saja yang dirusak, dibakar atau ditutup paksa dapat melebihi angka 1.000 (!). Luar biasa! Ini terjadi di negara, di mana salah satu prinsip dasar negara adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Sudah seharusnya, para penyelenggara negara memperhatikan UUD ’45 dan melaksanakannya secara konsekwen, karena apabila diteliti, baik SKB maupun SPB dua Menteri mengenai pendirian rumah ibadah, jelas melanggar UUD ’45.
Mungkin ada yang dapat mengajukan hal ini sebagai Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.
Buddhisme Tibet, sebagaimana diakui oleh Dalai Lama, dibawa oleh Atisha, seorang murid dari Dharmakirti, yang hidup di Sriwijaya, Sumatera pada abad ke 10. Dharmakirti dikenal sebagai Swarnadwipa Dharmakirti, atau Dharmakirti di Pulau Emas (Sumatera). Ajarannya mengenai Boddhicitta sangat ternama di seluruh dunia Buddhis di Asia Timur. Banyak orang datang ke Sriwijaya dari berbagai penjuru dunia, untuk berguru pada Dharmakirti. Di masa itu, Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Sriwijaya, sebagai negara maritim, tidak hanya dikenal dengan kekuatan armadanya, melainkan juga kebudayaan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan berbagai Candi di Jawa, seperti Candi Borobudur dan Candi Mendut.
Memang sangat mengherankan, di Sumatera sendiri tidak terlihat sisa candi Buddha peninggalan kerajaan Sriwijaya. Mengapa dibangun candi hanya di Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera sendiri, sebagai pusatnya waktu itu, tidak dibangun candi sama sekali? Ataukah seperti halnya di banyak tempat, ketika masuk agama-agama baru, maka tempat-tempat beribadah atau pemujaan dari agama lama dihancurkan total? Seperti patung Buddha terbesar di dunia yang berada di Afghanistan, yang dihancurkan oleh Taliban ketika mereka berkuasa? Apabila demikian halnya, maka hal ini sangat disayangkan, karena kita kehilangan sebagian dari budaya kita yang kaya dengan ragamnya.
Candi Borobudur pun, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha, ditelantarkan sehingga tertutup hutan lebat selama sekitar 5 abad, sampai ditemukan kembali oleh Thomas Stamford Raffles, ketika Inggris berkuasa di Nusantara tahun 1811 – 1816.
Mengenai perkembangan agama Islam di Nusantara ada dua pendapat, yang masing-masing merasa paling benar. Pendapat pertama menyatakan, bahwa perkembangan Islam di Nusantara berlangsung damai, dan semua –dari raja sampai rakyatnya- masuk Islam dengan sukarela. Pendapat kedua menyatakan, bahwa masuknya Islam memang secara damai, yaitu dibawa oleh para pedagang dan tokoh-tokoh Islam waktu itu, namun dalam perkembangan dan penyebaran selanjutnya, dilakukan dengan kekerasan senjata, sebagaimana digambarkan dalam beberapa penulisan, antara lain Serat Dharmogandul, mengenai jatuhnya Majapahit, dan buku yang disusun oleh Ir. M.O. Parlindungan Siregar yang berjudul “Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao. Teror Agama Islam Mazhab Hambali Di Tanah Batak 1816 – 1833.”
Parlindungan Siregar menulis berdasarkan catatan ayahnya yang mendengar sendiri dari beberapa saksi mata. Catatan sejarah tersebut dihimpun dari tahun 1851 – 1941. Disebutkan, bahwa bala tentara kaum Paderi dari Sumatera Barat menyerbu Tanah Batak tahun 1816, dan memaksa semua orang di wilayah yang telah ditaklukkan untuk masuk Islam. Mungkin hal ini yang menerangkan, mengapa Batak Selatan yang berbatasan dengan Sumatera Barat boleh dikatakan seluruhnya beragama Islam, dan di Batak Utara banyak yang memeluk agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, dan masih banyak juga yang menganut ajaran Batak asli, yaitu Parmalim.
Kembali ke keluargaku.
Kedua orang tuaku beragama Kristen Protestan dan mereka sangat rajin ke gereja, bahkan sampai di hari tua mereka, menjelang usia 90 tahun. Walaupun harus didorong di kursi roda, setiap hari minggu mereka ke gereja. Kini mereka telah tiada.
Kakak perempuanku yang paling tua, menikah dengan seorang pria dari Bali, Prof. Ida Bagus Adnyana Manuaba, dari kasta Brahmana. Suami kakakku beragama Hindu, sedangkan kakakku tetap beragama Kristen. Mereka dikaruniai tiga putri dan dua putra. Ketiga putrinya menikah dengan tiga pria beragama Islam, dan keluarga mereka beragama Islam, sedangkan keluarga kedua putranya beragama Hindu.
Abangku yang kedua, keempat dan kelima beragama Kristen, sedangkan abangku yang ketiga, menikah dengan seorang perempuan dari Purwokerto yang beragama Islam. Abangku memilih untuk pindah ke agama Islam. Tak ada seorangpun dari keluarga kami yang Kristen menuduhnya “murtad.” Tahun lalu dia menunaikan ibadah Haji. Aku sekarang dengan senang hati memanggilnya Pak Haji, dan dia gembira dengan sebutan ini.
Ketika aku menyatakan, bahwa aku kini beragama Buddha dan isteriku yang berasal dari Jawa Tengah beragama Islam, aku tidak dikucilkan dari keluarga besar, apalagi dianggap “murtad.” Semua biasa-biasa saja. Semua diterima dengan tangan terbuka dan hati yang jernih.
Dengan demikian, kami enam orang kakak-beradik menganut empat agama –Kristen, Islam, Hindu dan Buddha- dan hidup rukun, tanpa pernah ada pertengkaran mengenai agama. Saling menghargai agama yang lain, dan tidak pernah memaksakan, bahwa yang lain harus mengikuti agama yang dianutnya.
Bila aku sedang berkunjung ke rumah abangku dan sedang ada kebaktian Kristen, aku juga mengikutinya dan juga sembahyang secara Kristen. Tak masalah bagiku. Juga bila abangku yang Islam meneleponku dan menanyakan bagaimana kabarku, sering aku menjawab: “Alhamdulillah baik-baik saja. Insya Allah semua tetap berlangsung dengan baik.” Tak masalah bagiku untuk menggunakan bahasa yang dia pergunakan.
Di keluarga besar Hutagalung yang berasal dari kakek kami yang biasa dipanggil sebagai Opung (kakek) Thomas (bila dihitung sampai cucu dan buyut jumlahnya sudah mencapai ratusan), yang beragama Islam dan Kristen cukup seimbang, dan saling mengunjungi di hari besar masing-masing agama.
Ikatan adat orang Batak cukup kuat, sehingga berbagai upaya untuk mengadu-domba orang Batak hingga kini tidak berhasil. Dalam upacara-upacara adat, tidak dilihat seseorang memeluk agama apa. Yang dilihat hanya kaitannya dalam adat Batak yang berpegang pada Dalihan Na Tolu. Juga tidak peduli, apakah dia seorang Menteri atau Jenderal. Apabila dalam hirarki keluarga dan adat dia berada di posisi agak rendah, maka dalam upacara adat, dia kebagian kerja yang sesuai dengan tingkatnya menurut adat.
Putraku tahun ini berusia 11 tahun. Suatu hari, ketika dia di kelas 3 SD, dia pulang dari sekolah dan bertanya kepadaku: “Papa, apa sih artinya Kafir?”
Aku balik bertanya kepadanya: “Mengapa kamu tanya itu?”
Dia menjawab: “Tadi ada temanku bilang kepadaku, Kafir lu!”
Aku tertegun. Sejenak aku tak tahu apa yang harus kukatakan kepada putraku. Apakah dia harus membalas temannya dengan mengatakan, “dasar Islam goblok lu”, atau maki-makian lain? Temannya itu pasti juga akan mengadukan kepada ayahnya, apa yang dikatakan oleh putraku. Dan ini pasti akan berbuntut panjang. Bisa jadi panjang buntutnya seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Akhirnya aku hanya mengatakan kepada putraku: “Sudah, tak usah dihiraukan omongannya. Bilang saja, ngomong gitu nggak baik.”
Saat itu aku menyadari, bagaimana rawannya kehidupan beragama di negara yang berdasarkan Pancasila ini. Seandainya aku juga seorang yang emosinya tinggi, tentu sudah terjadi keributan. Aku juga menyadari, bahwa tak mungkin anak kelas 3 SD akan terpikir untuk memaki-maki teman sekelasnya dengan persoalan agama. Aku tak tahu, apakah ini hasil didikan orang tuanya, kakaknya, guru agamanya, pamannya atau entah siapa. Yang jelas tak mungkin dari anak kelas 3 SD.
Sejak itu, aku selalu sangat berhati-hati dalam mendidik putraku mengenai hal-hal yang sehubungan dengan agama, etnis dan kehidupan di masyarakat.
Mengingat latarbelakang diriku sendiri, juga sesuai dengan esensi ajaran Buddha yang kutangkap dan kupahami, sudah sejak tiga tahun aku bekali putraku dengan pesan, bahwa segala sesuatunya terpulang pada dirinya sendiri. Semua perbuatannnya adalah tanggungjawabnya sendiri. Untuk perbuatan baik, dia akan menerima balasan yang baik, dan untuk perbuatan yang buruk, dia akan menerima akibat yang buruk juga. Jangan menggantungkan nasibnya atau apapun kepada sesuatu yang dia tak ketahui. Semua yang dilakukannya, haruslah berdasarkan keputusannya sendiri, termasuk dalam masalah agama.
Kelak dia sendiri yang harus memutuskan, agama mana yang akan dia anut, ajaran mana yang akan dia ikuti.
Aku melihat diriku sendiri, yang pindah agama dari Kristen ke Buddha.
Selain ajaran Buddha, puisi Gibran Khalil Gibran mengenai anak-anak sangat berkesan di hatiku. Di dalam bukunya yang berjudul “The Prophet” (Sang Nabi), Gibran, warga Amerika kelahiran Libanon menulis puisi berjudul “On children.”
Khalil Gibran dilahirkan pada 6 Januari 1883 di Bsharri, Libanon dan meninggal pada 10 April 1931 di New York City. Dia seorang penyair dan seniman yang beragama Kristen Katolik Maronit.
Ketika aku membaca puisinya itu, aku merasa, dia memaparkan kepadaku suasana batinku. Gibran telah membaca apa yang kupikirkan mengenai putraku dan masa depannya. Gibran telah menulis hampir seratus tahun yang lalu mengenai apa yang kupikirkan sekarang, tahun 2006. Luar biasa Gibran Khalil Gibran ini …
Pusi Khalil Gibran dalam The PROPHET, tersebut berbunyi:
On Children
And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of Children."
And he said:
Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life's longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you, yet they belong not to you.
You may give them your love but not your thoughts.
For they have their own thoughts.
You may house their bodies but not their souls,
For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams.
You may strive to be like them, but seek not to make them like you.
For life goes not backward nor tarries with yesterday.
You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.
The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far.
Let your bending in the archer's hand be for gladness;
For even as He loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.
Terjemahannya kira-kira sebagai berikut (mungkin ada yang dapat lebih baik menerjemahkannya?):
Tentang anak-anak
Dan seorang perempuan yang sedang mendekap bayi di dadanya berkata, bicaralah kepada kami mengenai anak-anak.
Dan dia berkata:
Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu.
Mereka adalah putra putri dari kehidupan yang merindukan dirinya sendiri
Mereka datang melaluimu tetapi bukan darimu,
Dan walaupun mereka tinggal bersamamu, mereka bukanlah milikmu.
Kau dapat memberikan kasih-sayangmu tetapi tidak pikiranmu.
Karena mereka mempunyai pemikiran sendiri.
Kau dapat memberikan tempat untuk raga tetapi tidak untuk jiwa mereka,
Karena jiwa mereka menghuni rumah masa depan, yang tak dapat kau kunjungi, bahkan tak juga dalam mimpi-mimpimu.
Kau dapat berupaya keras untuk menjadi seperti mereka, tetapi jangan mencoba membuat mereka sepertimu.
Karena kehidupan tidak berjalan ke belakang juga tak tinggal di masa lalu.
Kau adalah busur dari mana anak-anakmu melesat ke depan sebagai anak panah hidup.
Sang pemanah melihat sasaran di atas jalur di tengah keabadian, dan DIA meliukkanmu dengan kekuatanNYA sehingga anak panahNYA dapat melesat dengan cepat dan jauh.
Biarkanlah liukkanmu di tangan sang pemanah menjadi keceriaan;
Bahkan DIA pun mengasihi anak panah yang terbang, demikian juga DIA mengasihi busur yang mantap.
Demikian puisi Khalil Gibran, yang namanya di Amerika salah ditulis menjadi Kahlil Gibran.
Mengenai kumpulan puisi “The Prophet” ini, George Russel menulis:
" I do not think that East has spoken with so beautiful a voice since the "Gitanjali" of Rabindranath Tagore as in The Prophet of Kahlil Gibran, who is artist as well as poet. I have not seen for years a book more beautiful in its thought, and when reading it I understand better than ever before what Sokrates meant in the "Banquet" when he spoke of the beauty of thought which exercises a deeper enchantment than the beauty of form . . . I could quote from every page, and from every page I could find some beautiful and liberating thought "
Aku tak dapat membayangkan dunia putraku di masa depan, sebagaimana orang tuaku dahulu tak dapat membayangkan dunia di mana aku hidup sekarang. Aku tak akan mengekang putraku dengan nilai-nilai dan agama yang kuyakini sekarang. Biarlah dia menemukan nilai-nilai yang diyakininya bahwa itu adalah yang terbaik baginya. Biarlah dia menentukan agama yang diyakininya sebagai yang terbaik baginya. Apapun pilihannya –atau tidak memilih apapun- aku akan berbahagia atas keputusannya, karena itulah keputusan putraku sendiri yang sangat kukasihi, dan bukan keputusanku.
Kelak, apabila putraku menyatakan akan pindah agama –apapun pilihannya- aku akan mengatakan kepadanya:
“Alhamdulillah, Puji Tuhan, Buddha Memberkati. Kau telah memilih jalanmu, aku berbahagia bersamamu!”
Mengenai langkahku ini aku sangat yakin, bahwa aku berada di jalan yang benar.
Aku ingin menutup renungan Waisak ini, dengan lyrik lagu John Lennon:
Imagine
Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today...
Imagine there's no countries,
It isnt hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace...
Imagine no possesions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say Im a dreamer,
but Im not the only one,
I hope some day you'll join us,
And the world will live as one.
Putraku kuajarkan untuk menutup meditasi dan sembahyangnya dengan kata-kata yang digunakan oleh umat Buddha:
“Semoga semua machluk berbahagia!”
“Selamat Merayakan Trisuci Waisak Bagi Yang Beragama Buddha!”
Wassalam,
Shalom,
Salam Sejahtera,
Om, Santi, Santi, Santi, Om,
Namo Buddhaya, Buddha Memberkati
Oleh Batara R. Hutagalung
Menjelang perayaan Trisuci Waisak -yaitu hari kelahiran Pangeran Siddharta Gotama (Gautama), hari tatkala Sang Pertapa Gotama mencapai pencerahan yang sempurna setelah bersamadhi di bawah pohon Bodhi, dan juga hari meninggalnya Sang Budhha Gotama yang oleh penganut ajaran Buddha dinamakan Parinibbana (Sansekerta: parinirvana) Sang Buddha- aku merenungkan banyak hal yang menyangkut diriku, putraku, keluargaku, masyarakat di lingkunganku, bangsaku dan juga masyarakat internasional, terutama yang sehubungan dengan kehidupan dan kerukunan beragama.
Beberapa tahun belakangan, di seluruh dunia banyak terjadi konflik kekerasan yang menggunakan simbol-simbol keagamaan dan mengatasnamakan agama, bahkan pembunuhan ratusan sampai ribuan manusia juga atas nama agama. Masing-masing pihak menyatakan bahwa yang dilakukannya adalah demi agamanya, demi Tuhannya, demi Allahnya.
Aku sungguh tidak dapat mengerti, mengapa agama yang seharusnya membawa kedamaian di muka bumi, mengajarkan manusia untuk saling mengasihi, justru digunakan sebagai alasan dan pembenaran untuk pembunuhan sesama manusia, dan bahkan yang berasal dari satu agama, namun berbeda aliran. Kelompok yang satu menyatakan, bahwa yang diyakini oleh kelompok lain adalah aliran sesat.
Ada kelompok yang selalu merasa terganggu bukan hanya dengan keberadaan komunitas agama yang berbeda, namun juga tidak memberikan toleransi terhadap perbedaan sekecil apapun, selain keyakinan yang dianutnya. Semua ingin diseragamkan. Budaya, perilaku, ukuran moral, cara berbusana dsb. ingin diseragamkan.
Apakah agamanya yang salah? Apakah Tuhannya atau Allahnya yang salah menurunkan ajaran? Ataukah manusianya yang tidak mengerti makna ajaran yang sebenarnya? Aku tak tahu. Belum tahu. Mungkin tak akan pernah tahu.
Aku sendiri dibesarkan di keluarga Kristen Protestan. Mengenai atribut Protestan baru kuketahui ketika aku kuliah di Universitas Hamburg, Jerman (dahulu Barat), di tahun 70-an. Kata tersebut berasal dari kata protes, yaitu protes terhadap gereja katholik di Jerman. Pada 31 Oktober 1517 di Wittenberg, Jerman, Dr. Martin Luther yang waktu itu beragama Katholik, menyampaikan 95 thesisnya yang merupakan reformasi terhadap gereja Katholik. Dia membentuk komunitasnya sendiri dan komunitasnya disebut sebagai Protestan, yaitu yang melakukan protes. Di Jerman sendiri, pengikut Martin Luther menamakan diri sebagai Evangelis Lutheran.
Abad 16 - 17 di Eropa sedang berkecamuk wabah reformasi, bukan hanya di Jerman. Namun sempalan Katholik di Jerman tidak mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh sempalan Katholik di Perancis, yang dinamakan kaum Hugenott. Tahun 1685 sekitar 50.000 orang Hugenott dari Perancis melarikan diri ke Jerman dan sebagian besar ditampung di Prusia.
Konflik antara Kristen Katholik dan Kristen Protestan di Eropa berlangsung cukup lama dan mengakibatkan pertumpahan darah yang besar, seperti juga yang terjadi antara Islam aliran Syiah dan Islam aliran Suni, yang juga telah berlangsung lebih dari seribu tahun dan menelan korban yang luar biasa besarnya di kedua belah pihak. Konflik ini masih berlangsung hingga sekarang, seperti terlihat di Irlandia Utara antara Kristen Katholik dengan Kristen Protestan, dan di Irak antara kelompok Suni dan kelompok Syiah.
Di Universitas Hamburg, aku mengambil jurusan sosiologi dan psikologi sebagai vak utama (Hauptfächer), dan filosofi sebagai vak tambahan wajib (Pflicht-Nebenfach). Aku harus membiayai sendiri biaya hidup dan kuliahku, dan karena menghadapi beberapa kesulitan, aku tak dapat menamatkan kuliahku.
Gedung fakultas teologi letaknya tepat di muka asrama tempatku tinggal. Aku memang juga gemar membaca buku-buku berbagai agama, sehingga aku juga sering mengikuti kuliah-kuliah teologi Kristen Protestan. Di Uni Hamburg, untuk banyak jurusan dan sejauh tempat tersedia, para mahasiswa dapat mengikuti kuliah dari beragam jurusan. Apabila telah terdaftar sebagai mahasiswa di Uni Hamburg, dia cukup mencatatkan nama di fakultas yang bersangkutan, dan mencatatkan nama pada daftar yang tersedia di awal semester, kemudian dia dapat mengikuti kuliah yang diminatinya.
Yang mengambil jurusan Teologi Kristen di Uni Hamburg, tidak hanya dari yang beragama Kristen Protestan, melainkan juga yang berlatarbelakang agama lain, bahkan ada beberapa pendeta Buddhis.
Waktu itu di Hamburg ada seorang Pendeta Kristen dari Indonesia, Mangasi S. Siahaan, yang sedang melanjutkan studinya di bidang teologi, dan kemudian berhasil meraih gelar Doktor Theologi di Uni Hamburg, kalau tak salah, dengan predikat Magna Cum Laude. Seringkali sebelum kuliah, dia mampir ke asramaku untuk ngopi dan ngobrol, dan berdiskusi mengenai berbagai hal, termasuk mengenai keagamaan.
Juga ada Pendeta Kristen muda dari Indonesia, Sahat Tobing, yang juga melanjutkan studinya di Uni Hamburg. Dan masih ada beberapa Pendeta Kristen Indonesia lain, yang juga sering berdiskusi denganku mengenai agama.
Aku juga mempunyai seorang teman baik orang Jerman, Peter Marwedel, anggota Partai Komunis Jerman (KPD). Aku sering menyindir dia, karena dia memiliki mobil Mercedez Benz. Aku bilang, “ Peter, kamu seorang komunis, kok naik Mercedez? Seharusnya kamu naik Volkswagen (VW).” Dia menjawab:” Aku ‘kan sering ke luar kota, jadi perlu mobil dengan mesin yang kuat.”
Aku katakan: “Ah Peter, itu cuma alasan pembenaranmu. Menurutku, kau seorang komunis yang berpikiran kapitalistik.” Peter cuma cengar-cengir saja dan bilang: “Terserah. Apapun pendapatmu, itu hakmu untuk menilai tindakanku. Aku tak akan berubah hanya karena ucapanmu.” Kami tetap berteman baik, walaupun sering berdebat dan berbeda pendapat.
Dengan merekalah aku sering berdiskusi. Mendiskusikan berbagai agama, berbagai ajaran, berbagai jalan keselamatan, berbagai thesis dan anti-thesis.
Dari semua ajaran yang aku pelajari dan diskusikan, jalan keselamatan yang ditawarkan oleh Sidharta Gotama (Gautama) yang paling menarik bagiku. Yang sangat terkesan bagiku dari ajarannya adalah, bahwa segala sesuatunya terpulang pada diri kita sendiri. Semua perbuatannmu adalah tanggungjawabmu sendiri. Untuk perbuatan baik, kau akan menerima balasan yang baik, dan untuk perbuatanmu yang buruk, kau akan menerima akibat yang buruk juga. Ini yang dikenal sebagai Hukum Karma, atau Hukum Perbuatan. Jangan menggantungkan nasibmu atau apapun kepada sesuatu yang kau tak ketahui. Itulah esensi yang kutangkap dari sekian banyak buku mengenai ajarannya yang dinamakan Buddhisme.
Menurut pendapatku, di dalam ajaran Buddha, tidak ada dogma, melainkan semuanya anjuran. Mengenai apakah mematuhi dan menjalankannya atau tidak, adalah tanggungjawab kita sendiri.
Salah satu dasar ajaran Buddha adalah Panca – Sila. Kata Panca-Sila ini diadopsi oleh Ir. Sukarno untuk memberi nama lima prinsip dasar negara Republik Indonesia, yang dibacakannya pada 1 Juni 1945.
Kata Panca-Sila sendiri berasal dari bahasa Pali. Panca artinya lima dan Sila pengertian sebenarnya adalah dasar, namun dalam pengertian Buddhis, Sila adalah kerelaan jiwa diri sendiri, setelah memahami mengenai sebab dan akibat, untuk kemudian memegang dan menjalankannya agar kita dapat mencapai Pencerahan dan Nirvana (Pali: Nibbana). Nirvana bukanlah suatu tempat seperti surga, melainkan suatu keadaan, di mana mata-rantai atau lingkaran dari kelahiran-dewasa-sakit-mati-lahir kembali, dst. telah diputus.
Jika melanggar Sila, kita sendiri yang akan menanggung akibatnya dan ini bukan merupakan hukuman dari Buddha.
Kelima sila dalam Panca – Sila yang dianjurkan untuk dipegang dan dilaksanakan adalah
Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami (Menahan diri dari pembunuhan),
Adinadana veramani (Menahan diri dari pencurian),
Kamesumicchacara veramani (Menahan diri dari perzinaan)
Musavada veramani (Menahan diri dari pendustaan),
Sura-meraya-majja pamadtthana veramani (Menahan diri dari minuman dan barang-barang yang memabukkan).
Sejak tahun 1974, aku memutuskan masuk agama Buddha dan mencoba mengikuti semua anjuran Buddha. Dalam pemahamanku mengenai sila pertama, yang dimaksud dengan pembunuhan, adalah termasuk pembunuhan terhadap hewan untuk santapan manusia. Aku dapat menerima pendapat, bahwa hewanpun mempunyai hak hidup yang sama. Oleh karena itu, juga sejak tahun 1974 aku memutuskan untuk hidup sebagai seorang vegetarian, alias tidak makan daging dan ikan samasekali. Sehubungan dengan sila kelima, sejak lima tahun aku sudah berhenti minum alkohol. Dahulu ketika masih di Jerman, itulah minumanku sehari-hari. Mengenai sila-sila yang lain, perlahan-lahan aku usahakan untuk kupenuhi. Terus terang aku akui, masih sulit sekali untuk dilaksanakan sepenuhnya. Sangat sulit! Mungkin kalau aku bisa menjalankan kelima sila tersebut dengan sempurna, maka aku dapat mencapai pencerahan yang sempurna juga. Tapi sekarang belum …
Dari kumpulan tulisan ucapan Buddha Gotama –yang ditulis oleh muridnya, Ananda- yaitu Tripitaka, atau Tiga Keranjang (Bahasa Jerman: Drei Körbe) yang tebalnya ribuan halaman, mungkin belum separuhnya yang kubaca.
Aku juga tidak mau mengikuti aliran apapun, apakah itu Mahayana, Hinayana, Theravada, Zen Buddhisme, Buddhisme Tibet, karena semua aliran itu merupakan sinkretisme, telah bercampur dengan nilai-nilai agama setempat, sebelum datangnya Buddhisme. Sinkretisme ini terdapat di semua agama. Masih banyak orang Jawa yang beragama Islam, dalam melakukan ritual adat, memberikan sesajen untuk Dewi Sri. Dalam ajaran Islam ‘kan tak ada Dewi Sri. Juga tak ada Nyai Roro Kidul.
Oleh karena itu, aku tidak mengikuti aliran apapun dalam Buddhisme. Aku hanya membatasi diri untuk memahami nilai-nilai dasar yang terkandung dalam inti ajaran Buddha, dengan pemahamanku sendiri, bukan berdasarkan pemahaman atau penafsiran orang lain. Aku hanya berpegang pada Tripitaka ... dan penafsiranku sendiri.
Aku bersyukur, bahwa belum pernah terjadi, ada aliran dalam Buddhisme disebut sebagai aliran sesat dan dilarang oleh aliran atau kelompok lain, seperti yang terjadi pada komunitas Ahmadiyah di Indonesia, atau pada Lia Aminuddin, yang ditangkap oleh Polisi, dengan tuduhan penghinaan terhadap agama. Lia Aminuddin mengaku mendapat wahyu dari Malaikat Jibril. Demikian juga dengan seseorang yang katanya biasa melakukan Shalat dengan bersiul. Kini diapun mendekam di tahanan.
Padahal Undang-Undang Dasar ’45 (UUD ’45) menjamin kebebasan beragama setiap warga. Bab XI mengenai Agama, Pasal 29 (2) berbunyi::
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Selain itu, Bab X A mengenai Hak Asasi Manusia, Pasal 28 E (2) berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”
Pasal 28 I (2) berbunyi:
“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”
Pasal 28 J (1) berbunyi:
“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”
Jadi sangat mengherankan, bahwa para penyelenggara negara, tidak memperhatikan Undang-Undang Dasar, yang seharusnya menjadi landasan dan acuan semua ucapan, keputusan dan tindakan mereka.
Kini, tahun 2006, oleh Mendagri dan Menteri Agama diterbitkan Surat Peraturan Bersama (SPB) yang menggantikan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, SKB no. 01 BER/MDN-MAG/1969, tahun 1969, yang mengatur agar pendirian tempat ibadah harus dengan seizin masyarakat setempat. Sepertinya, di negeri ini, segala sesuatu yang semakin dicoba untuk diatur, semakin ambur-adul. Dari data-data yang diperoleh berbagai pihak, sebelum dikeluarkannya SKB tahun 1969, perusakan, pembakaran dan penutupan gereja relatif kecil, dibandingkan setelah dikeluarkannya SKB dua Menteri.
Bahkan, apabila dicermati, SPB dua Menteri tahun 2006 ini jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan SKB tahun 1969, karena dalam SPB, kehidupan dan kerukunan beragama “dikendalikan” oleh Gubernur, Bupati, Walikota dan pejabat-pejabat setempat.
Dari tahun 1965 s/d 1974 (10 tahun) terjadi perusakan 46 Gereja atau rata-rata 4,6 gedung Gereja yang dirusak per tahun. Kemudian antara tahun 1975 s/d 1984 (10 tahun) jumlah Gereja yang dirusak meningkat 89 atau rata-rata 8,9 per tahun. Demikian pula antara tahun 1985 s/d 1994 (10 tahun) terjadi peningkatan 2 x lipat dari jumlah sebelumnya, yaitu 132 Gereja atau rata-rata 13,2 per tahun. Dan kemudian antara 1995-1997 (2 tahun), terjadi peningkatan yang sangat mencolok dimana jumlah Gereja yang dirusak menjadi 105 atau rata-rata 52,5 per tahun. Hingga 1 Juli 1997, telah terjadi penutupan, perusakan dan pembakaran 374 Gereja. Perusakan tersebut diatas, belum termasuk perusakan rumah ibadah agama lain seperti Vihara maupun fasilitas Pemerintah, swasta dan fasilitas umum. Selanjutnya lihat tabel di:
lihat:http://www.fica.org/persecution/374.html
Sayang aku belum mendapat data yang akurat mengenai jumlah gereja, vihara, dll. yang dirusak, dibakar atau ditutup paksa antara 1997 – 2006. Menurut perkiraan beberapa pihak, hingga tahun 2006, jumlah gereja saja yang dirusak, dibakar atau ditutup paksa dapat melebihi angka 1.000 (!). Luar biasa! Ini terjadi di negara, di mana salah satu prinsip dasar negara adalah “Ketuhanan Yang Maha Esa.”
Sudah seharusnya, para penyelenggara negara memperhatikan UUD ’45 dan melaksanakannya secara konsekwen, karena apabila diteliti, baik SKB maupun SPB dua Menteri mengenai pendirian rumah ibadah, jelas melanggar UUD ’45.
Mungkin ada yang dapat mengajukan hal ini sebagai Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.
Buddhisme Tibet, sebagaimana diakui oleh Dalai Lama, dibawa oleh Atisha, seorang murid dari Dharmakirti, yang hidup di Sriwijaya, Sumatera pada abad ke 10. Dharmakirti dikenal sebagai Swarnadwipa Dharmakirti, atau Dharmakirti di Pulau Emas (Sumatera). Ajarannya mengenai Boddhicitta sangat ternama di seluruh dunia Buddhis di Asia Timur. Banyak orang datang ke Sriwijaya dari berbagai penjuru dunia, untuk berguru pada Dharmakirti. Di masa itu, Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara. Sriwijaya, sebagai negara maritim, tidak hanya dikenal dengan kekuatan armadanya, melainkan juga kebudayaan yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan berbagai Candi di Jawa, seperti Candi Borobudur dan Candi Mendut.
Memang sangat mengherankan, di Sumatera sendiri tidak terlihat sisa candi Buddha peninggalan kerajaan Sriwijaya. Mengapa dibangun candi hanya di Pulau Jawa, sedangkan di Sumatera sendiri, sebagai pusatnya waktu itu, tidak dibangun candi sama sekali? Ataukah seperti halnya di banyak tempat, ketika masuk agama-agama baru, maka tempat-tempat beribadah atau pemujaan dari agama lama dihancurkan total? Seperti patung Buddha terbesar di dunia yang berada di Afghanistan, yang dihancurkan oleh Taliban ketika mereka berkuasa? Apabila demikian halnya, maka hal ini sangat disayangkan, karena kita kehilangan sebagian dari budaya kita yang kaya dengan ragamnya.
Candi Borobudur pun, setelah runtuhnya kerajaan Majapahit yang beragama Hindu-Buddha, ditelantarkan sehingga tertutup hutan lebat selama sekitar 5 abad, sampai ditemukan kembali oleh Thomas Stamford Raffles, ketika Inggris berkuasa di Nusantara tahun 1811 – 1816.
Mengenai perkembangan agama Islam di Nusantara ada dua pendapat, yang masing-masing merasa paling benar. Pendapat pertama menyatakan, bahwa perkembangan Islam di Nusantara berlangsung damai, dan semua –dari raja sampai rakyatnya- masuk Islam dengan sukarela. Pendapat kedua menyatakan, bahwa masuknya Islam memang secara damai, yaitu dibawa oleh para pedagang dan tokoh-tokoh Islam waktu itu, namun dalam perkembangan dan penyebaran selanjutnya, dilakukan dengan kekerasan senjata, sebagaimana digambarkan dalam beberapa penulisan, antara lain Serat Dharmogandul, mengenai jatuhnya Majapahit, dan buku yang disusun oleh Ir. M.O. Parlindungan Siregar yang berjudul “Pongkinangolngolan Sinambela gelar Tuanku Rao. Teror Agama Islam Mazhab Hambali Di Tanah Batak 1816 – 1833.”
Parlindungan Siregar menulis berdasarkan catatan ayahnya yang mendengar sendiri dari beberapa saksi mata. Catatan sejarah tersebut dihimpun dari tahun 1851 – 1941. Disebutkan, bahwa bala tentara kaum Paderi dari Sumatera Barat menyerbu Tanah Batak tahun 1816, dan memaksa semua orang di wilayah yang telah ditaklukkan untuk masuk Islam. Mungkin hal ini yang menerangkan, mengapa Batak Selatan yang berbatasan dengan Sumatera Barat boleh dikatakan seluruhnya beragama Islam, dan di Batak Utara banyak yang memeluk agama Kristen, baik Protestan maupun Katolik, dan masih banyak juga yang menganut ajaran Batak asli, yaitu Parmalim.
Kembali ke keluargaku.
Kedua orang tuaku beragama Kristen Protestan dan mereka sangat rajin ke gereja, bahkan sampai di hari tua mereka, menjelang usia 90 tahun. Walaupun harus didorong di kursi roda, setiap hari minggu mereka ke gereja. Kini mereka telah tiada.
Kakak perempuanku yang paling tua, menikah dengan seorang pria dari Bali, Prof. Ida Bagus Adnyana Manuaba, dari kasta Brahmana. Suami kakakku beragama Hindu, sedangkan kakakku tetap beragama Kristen. Mereka dikaruniai tiga putri dan dua putra. Ketiga putrinya menikah dengan tiga pria beragama Islam, dan keluarga mereka beragama Islam, sedangkan keluarga kedua putranya beragama Hindu.
Abangku yang kedua, keempat dan kelima beragama Kristen, sedangkan abangku yang ketiga, menikah dengan seorang perempuan dari Purwokerto yang beragama Islam. Abangku memilih untuk pindah ke agama Islam. Tak ada seorangpun dari keluarga kami yang Kristen menuduhnya “murtad.” Tahun lalu dia menunaikan ibadah Haji. Aku sekarang dengan senang hati memanggilnya Pak Haji, dan dia gembira dengan sebutan ini.
Ketika aku menyatakan, bahwa aku kini beragama Buddha dan isteriku yang berasal dari Jawa Tengah beragama Islam, aku tidak dikucilkan dari keluarga besar, apalagi dianggap “murtad.” Semua biasa-biasa saja. Semua diterima dengan tangan terbuka dan hati yang jernih.
Dengan demikian, kami enam orang kakak-beradik menganut empat agama –Kristen, Islam, Hindu dan Buddha- dan hidup rukun, tanpa pernah ada pertengkaran mengenai agama. Saling menghargai agama yang lain, dan tidak pernah memaksakan, bahwa yang lain harus mengikuti agama yang dianutnya.
Bila aku sedang berkunjung ke rumah abangku dan sedang ada kebaktian Kristen, aku juga mengikutinya dan juga sembahyang secara Kristen. Tak masalah bagiku. Juga bila abangku yang Islam meneleponku dan menanyakan bagaimana kabarku, sering aku menjawab: “Alhamdulillah baik-baik saja. Insya Allah semua tetap berlangsung dengan baik.” Tak masalah bagiku untuk menggunakan bahasa yang dia pergunakan.
Di keluarga besar Hutagalung yang berasal dari kakek kami yang biasa dipanggil sebagai Opung (kakek) Thomas (bila dihitung sampai cucu dan buyut jumlahnya sudah mencapai ratusan), yang beragama Islam dan Kristen cukup seimbang, dan saling mengunjungi di hari besar masing-masing agama.
Ikatan adat orang Batak cukup kuat, sehingga berbagai upaya untuk mengadu-domba orang Batak hingga kini tidak berhasil. Dalam upacara-upacara adat, tidak dilihat seseorang memeluk agama apa. Yang dilihat hanya kaitannya dalam adat Batak yang berpegang pada Dalihan Na Tolu. Juga tidak peduli, apakah dia seorang Menteri atau Jenderal. Apabila dalam hirarki keluarga dan adat dia berada di posisi agak rendah, maka dalam upacara adat, dia kebagian kerja yang sesuai dengan tingkatnya menurut adat.
Putraku tahun ini berusia 11 tahun. Suatu hari, ketika dia di kelas 3 SD, dia pulang dari sekolah dan bertanya kepadaku: “Papa, apa sih artinya Kafir?”
Aku balik bertanya kepadanya: “Mengapa kamu tanya itu?”
Dia menjawab: “Tadi ada temanku bilang kepadaku, Kafir lu!”
Aku tertegun. Sejenak aku tak tahu apa yang harus kukatakan kepada putraku. Apakah dia harus membalas temannya dengan mengatakan, “dasar Islam goblok lu”, atau maki-makian lain? Temannya itu pasti juga akan mengadukan kepada ayahnya, apa yang dikatakan oleh putraku. Dan ini pasti akan berbuntut panjang. Bisa jadi panjang buntutnya seperti yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Akhirnya aku hanya mengatakan kepada putraku: “Sudah, tak usah dihiraukan omongannya. Bilang saja, ngomong gitu nggak baik.”
Saat itu aku menyadari, bagaimana rawannya kehidupan beragama di negara yang berdasarkan Pancasila ini. Seandainya aku juga seorang yang emosinya tinggi, tentu sudah terjadi keributan. Aku juga menyadari, bahwa tak mungkin anak kelas 3 SD akan terpikir untuk memaki-maki teman sekelasnya dengan persoalan agama. Aku tak tahu, apakah ini hasil didikan orang tuanya, kakaknya, guru agamanya, pamannya atau entah siapa. Yang jelas tak mungkin dari anak kelas 3 SD.
Sejak itu, aku selalu sangat berhati-hati dalam mendidik putraku mengenai hal-hal yang sehubungan dengan agama, etnis dan kehidupan di masyarakat.
Mengingat latarbelakang diriku sendiri, juga sesuai dengan esensi ajaran Buddha yang kutangkap dan kupahami, sudah sejak tiga tahun aku bekali putraku dengan pesan, bahwa segala sesuatunya terpulang pada dirinya sendiri. Semua perbuatannnya adalah tanggungjawabnya sendiri. Untuk perbuatan baik, dia akan menerima balasan yang baik, dan untuk perbuatan yang buruk, dia akan menerima akibat yang buruk juga. Jangan menggantungkan nasibnya atau apapun kepada sesuatu yang dia tak ketahui. Semua yang dilakukannya, haruslah berdasarkan keputusannya sendiri, termasuk dalam masalah agama.
Kelak dia sendiri yang harus memutuskan, agama mana yang akan dia anut, ajaran mana yang akan dia ikuti.
Aku melihat diriku sendiri, yang pindah agama dari Kristen ke Buddha.
Selain ajaran Buddha, puisi Gibran Khalil Gibran mengenai anak-anak sangat berkesan di hatiku. Di dalam bukunya yang berjudul “The Prophet” (Sang Nabi), Gibran, warga Amerika kelahiran Libanon menulis puisi berjudul “On children.”
Khalil Gibran dilahirkan pada 6 Januari 1883 di Bsharri, Libanon dan meninggal pada 10 April 1931 di New York City. Dia seorang penyair dan seniman yang beragama Kristen Katolik Maronit.
Ketika aku membaca puisinya itu, aku merasa, dia memaparkan kepadaku suasana batinku. Gibran telah membaca apa yang kupikirkan mengenai putraku dan masa depannya. Gibran telah menulis hampir seratus tahun yang lalu mengenai apa yang kupikirkan sekarang, tahun 2006. Luar biasa Gibran Khalil Gibran ini …
Pusi Khalil Gibran dalam The PROPHET, tersebut berbunyi:
On Children
And a woman who held a babe against her bosom said, "Speak to us of Children."
And he said:
Your children are not your children.
They are the sons and daughters of Life's longing for itself.
They come through you but not from you,
And though they are with you, yet they belong not to you.
You may give them your love but not your thoughts.
For they have their own thoughts.
You may house their bodies but not their souls,
For their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams.
You may strive to be like them, but seek not to make them like you.
For life goes not backward nor tarries with yesterday.
You are the bows from which your children as living arrows are sent forth.
The archer sees the mark upon the path of the infinite, and He bends you with His might that His arrows may go swift and far.
Let your bending in the archer's hand be for gladness;
For even as He loves the arrow that flies, so He loves also the bow that is stable.
Terjemahannya kira-kira sebagai berikut (mungkin ada yang dapat lebih baik menerjemahkannya?):
Tentang anak-anak
Dan seorang perempuan yang sedang mendekap bayi di dadanya berkata, bicaralah kepada kami mengenai anak-anak.
Dan dia berkata:
Anak-anakmu bukanlah anak-anakmu.
Mereka adalah putra putri dari kehidupan yang merindukan dirinya sendiri
Mereka datang melaluimu tetapi bukan darimu,
Dan walaupun mereka tinggal bersamamu, mereka bukanlah milikmu.
Kau dapat memberikan kasih-sayangmu tetapi tidak pikiranmu.
Karena mereka mempunyai pemikiran sendiri.
Kau dapat memberikan tempat untuk raga tetapi tidak untuk jiwa mereka,
Karena jiwa mereka menghuni rumah masa depan, yang tak dapat kau kunjungi, bahkan tak juga dalam mimpi-mimpimu.
Kau dapat berupaya keras untuk menjadi seperti mereka, tetapi jangan mencoba membuat mereka sepertimu.
Karena kehidupan tidak berjalan ke belakang juga tak tinggal di masa lalu.
Kau adalah busur dari mana anak-anakmu melesat ke depan sebagai anak panah hidup.
Sang pemanah melihat sasaran di atas jalur di tengah keabadian, dan DIA meliukkanmu dengan kekuatanNYA sehingga anak panahNYA dapat melesat dengan cepat dan jauh.
Biarkanlah liukkanmu di tangan sang pemanah menjadi keceriaan;
Bahkan DIA pun mengasihi anak panah yang terbang, demikian juga DIA mengasihi busur yang mantap.
Demikian puisi Khalil Gibran, yang namanya di Amerika salah ditulis menjadi Kahlil Gibran.
Mengenai kumpulan puisi “The Prophet” ini, George Russel menulis:
" I do not think that East has spoken with so beautiful a voice since the "Gitanjali" of Rabindranath Tagore as in The Prophet of Kahlil Gibran, who is artist as well as poet. I have not seen for years a book more beautiful in its thought, and when reading it I understand better than ever before what Sokrates meant in the "Banquet" when he spoke of the beauty of thought which exercises a deeper enchantment than the beauty of form . . . I could quote from every page, and from every page I could find some beautiful and liberating thought "
Aku tak dapat membayangkan dunia putraku di masa depan, sebagaimana orang tuaku dahulu tak dapat membayangkan dunia di mana aku hidup sekarang. Aku tak akan mengekang putraku dengan nilai-nilai dan agama yang kuyakini sekarang. Biarlah dia menemukan nilai-nilai yang diyakininya bahwa itu adalah yang terbaik baginya. Biarlah dia menentukan agama yang diyakininya sebagai yang terbaik baginya. Apapun pilihannya –atau tidak memilih apapun- aku akan berbahagia atas keputusannya, karena itulah keputusan putraku sendiri yang sangat kukasihi, dan bukan keputusanku.
Kelak, apabila putraku menyatakan akan pindah agama –apapun pilihannya- aku akan mengatakan kepadanya:
“Alhamdulillah, Puji Tuhan, Buddha Memberkati. Kau telah memilih jalanmu, aku berbahagia bersamamu!”
Mengenai langkahku ini aku sangat yakin, bahwa aku berada di jalan yang benar.
Aku ingin menutup renungan Waisak ini, dengan lyrik lagu John Lennon:
Imagine
Imagine there's no heaven,
It's easy if you try,
No hell below us,
Above us only sky,
Imagine all the people
living for today...
Imagine there's no countries,
It isnt hard to do,
Nothing to kill or die for,
No religion too,
Imagine all the people
living life in peace...
Imagine no possesions,
I wonder if you can,
No need for greed or hunger,
A brotherhood of man,
Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say Im a dreamer,
but Im not the only one,
I hope some day you'll join us,
And the world will live as one.
Putraku kuajarkan untuk menutup meditasi dan sembahyangnya dengan kata-kata yang digunakan oleh umat Buddha:
“Semoga semua machluk berbahagia!”
“Selamat Merayakan Trisuci Waisak Bagi Yang Beragama Buddha!”
Wassalam,
Shalom,
Salam Sejahtera,
Om, Santi, Santi, Santi, Om,
Namo Buddhaya, Buddha Memberkati
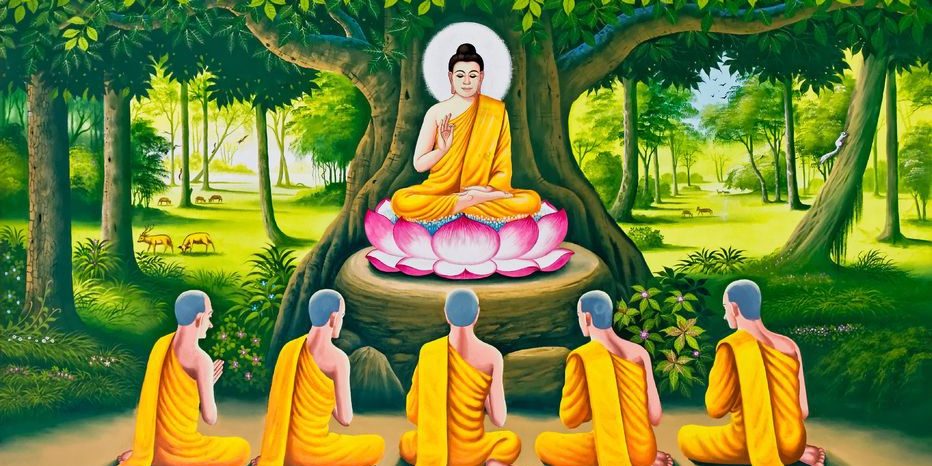


Tidak ada komentar:
Posting Komentar